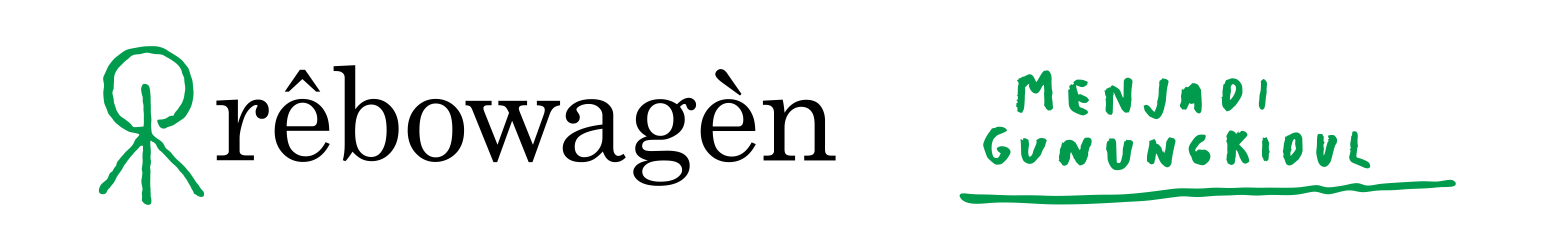Lingkungan (rebowagen.com)– Entah kesialan atau keberuntungan, perjalanan saya ke negeri di atas gunung terpaksa ditunda. Petang itu, hujan turun sejadi-jadinya. Nampaknya, cuaca menjadi penghambat sepertiga perjalanan dari Bantul Projotamansari menuju Gunungkidul Handayani. Berbah akhirnya saya pilih sebagai tempat pemberhentian. Singgah dan berteduh di penginapan seorang teman. Saya berharap, barang satu atau dua jam lagi hujan akan reda dan saya bisa melanjutkan perjalanan.
Ternyata sampai malam tiba, hujan belum juga reda. Saya dan teman saya hanya bisa mendekam di kamar tak bisa kemana-mana. Malam Minggu yang agak suram bagi orang muda seperti kami. Untung saja ada siaran sepak bola untuk hiburan malam ini. Disela keasikan melihat gulirnya bola, saya bercakap tentang rencana sebelumnya untuk ikut agenda ‘Anjo Nandur’ yang diadakan Resan Gunungkidul bersama Sanggar Lumbung Kawruh di Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop, Gunungkidul. Rencananya malam ini, saya sudah tiba di sana, tapi karena hujan, terpaksa harus tertunda sampai esok pagi.
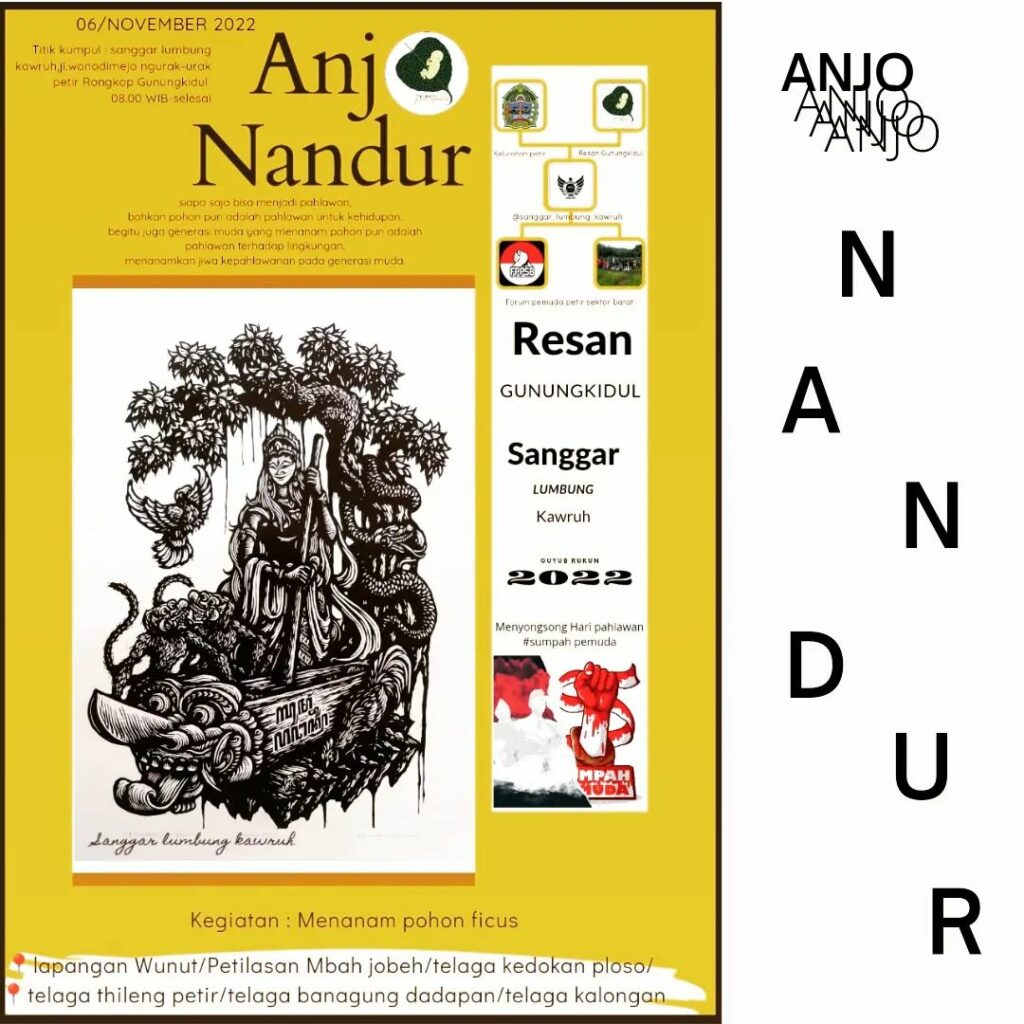
Dalam obrolan kami, acara itu juga menarik minat teman saya untuk bergabung. Rencana baru kami sepakati. Dan kembali, kami melihat pertandingan demi pertandingan sepak bola. Sampai larut malam, belum semua pertandingan bisa kami nikmati. Namun badan sudah tidak bisa diajak kompromi dan mata sudah terkantuk-kantuk. Sebelum benar-benar terlelap, ada satu pesan yang kami wanti, “Jangan sampai bangun kesiangan karena bisa fatal akibatnya.” Kemudian kami pun terbuai dalam mimpi.
Tiba-tiba, “ndert…ndertt, was wes wos…bakpao-bakpao!” entah bagaimana bunyinya, yang jelas, saat si penjual bakpao lewat di samping kamar, saya kaget bukan main. Mata langsung terbelalak, reflek, begitu juga dengan teman saya. Entah makhluk apa yang menggerakkan tubuh setengah sadarnya itu. Seketika dia bangkit dan bergegas membeli bakpao 6 buah, dan akhirnya menjadi menu sarapan kami berdua.
Hari sudah pagi. Belum tepat pukul 07.00. Hah, beruntung sekali, kalau saja penjual bakpao itu tidak beredar pagi ini, waduh, bisa kacau seharian Minggu ini. Dan kalau saja saya bangun kesiangan, ‘muspra‘ (sia-sia) sudah apa yang saya impikan sejak tempo hari. “Wahai penjual bakpao sang penyelamat sekaligus sadis bagi tidurku, terima kasih.”
Dari Berbah, Sleman, dibutuhkan lebih dari satu setengah jam perjalanan menuju titik tujuan. Melebihi estimasi yang ditunjukkan kompas di gawai pintar. Tertulis jam 08.00 acara itu dimulai. Dan pukul 09.30 saya baru tiba di lokasi. Kemoloran yang cukup lama karena sempat ‘keblasuk-blasuk‘ (tersesat) karena sama sekali belum mengenal medan.
Ternyata, Kalurahan Petir itu jauh juga. Maklum, saya bukan asli Gunungkidul. Saya orang Ponorogo, Jawa Timur, namun begitu menginjakkan kaki di Kapanewon Rongkop, Gunungkidul (kalau di Jogja kecamatan di sebut ‘kapanewon‘), kami seperti halnya berada di Kecamatan Ngrayun, Ponorogo. Jalannya yang berkelok dan beberapa rusak, pepohonan di kanan-kiri jalan, dan tanah liatnya yang berwarna merah. Ya, Gunungkidul dan Ponorogo layaknya saudara. Terhubung melalui pertalian Pegunungan Sewu sisi selatan Pulau Jawa.
GPS sudah memperlihatkan lokasi yang tepat. Sekilas, tidak nampak juga ada sanggar di sana. Saya tolah-toleh mencari bangunan bernama Sanggar Lumbung Kawruh itu. Mengakhiri kebingungan, saya menuju salah satu rumah warga. “Kula nuwun” yang saya ucapkan berbalas “Monggo” yang diikuti langkah seorang laki-laki dari dalam rumah.
Agak kaget melihatnya. Laki-laki dengan piercing sebesar uang koin di salah satu telinganya, rambutnya gimbal, celananya sobek di lutut. Saat seperti ini, pemikiran “Jangan menilai orang dari luarnya” harus dicamkan betul.
Lelaki nyentrik itu kemudian saya kenal sebagai Mas Ribut, salah seorang yang dituakan di Sanggar Lumbung Kawruh. Basa-basi, fafifu, dan tujuan yang saya utarakan dibalas dengan bahasa Jawa halus oleh beliau. Memang benar, jangan menilai orang dari luarnya saja. Jelas saya sudah tertinggal rombongan. Kemudian, Mas Ribut mengantar saya menuju Petilasan Mbah Jobeh. Di sana, teman-teman sudah memulai menanam pohon. Dan di sekitar petilasan, ada beberapa orang berpakaian ‘kejawen‘ sedang berdoa.

Melihat fenomena orang berdoa dengan pakaian adat di sekitar pemakaman atau di tempat lain, bukanlah hal aneh bagi saya. Saya sudah terbiasa dan tumbuh di lingkungan dengan tradisi tersebut. Kata Simbah sewaktu saya masih kecil, bahwa semua yang ada di alam ini harus dihormati. Salah satu caranya yaitu dengan mendoakannya.
Penanaman di sekitar petilasan Mbah Jobeh sudah selesai. Tujuan selanjutnya adalah Telaga Tileng. Dari cerita orang-orang yang ikut kegiatan, saya tahu bahwa telaga itu dulunya tidak pernah kering sekalipun di musim kemarau. Namun semenjak dindingnya disemen, telaga itu mengering setiap kemarau datang. Tidak jauh dari telaga itu juga dibangun arena bermain. Sepertinya, tempat itu akan dijadikan kawasan wisata kekinian.
Telaga yang sebetulnya menyuguhkan pemandangan indah. Dihiasi hamparan rumput hijau dan bebukitan kecil di sekelilingnya. Hawa sejuk dengan panas matahari yang tidak menyengat. Kalau surga dunia itu nyata adanya, mungkin dan bisa jadi, Gunungkidul adalah salah satunya. Dalam hati, saya ikut berdoa dan berharap, semoga kelak, keindahan ini tidak hanya menjadi cerita.

Kemudian titik penanaman selanjutnya, Telaga Banagung. Telaga ini tidak nampak seperti telaga. Sama sekali tidak ada airnya. Konon, telaga itu dulunya dipakai untuk jeguran, memandikan hewan ternak, dan mengairi sawah. Dulu, airnya masih sangat bersih. Kini, keasrian telaga itu hanya tinggal cerita. Di tempat ini, mereka tidak langsung menanam. Fokus teman-teman tertuju pada satu pohon besar. Pohon itu mereka amati, sambil sesekali mengelilinginya dan meraba-raba daunnya. Saya kira, mereka akan ‘nglangse‘ atau memakaikan kain mori di pohon. Ternyata tidak, mereka sedang mengidentifikasi jenis pohon resan itu.
“Kira-kira, itu jenis beringin,” kata salah seorang dari mereka.
Saat mereka asik mengamati pohon, saya sempat ngobrol dengan Mas Ribut, katanya, bisa jadi telaga itu kering karena berkurangnya pohon resan sebagai pelindung mata air. Atau kemungkinan lainnya, ‘luweng‘ (lubang vertikal) di dasar telaga terbuka, sehingga air masuk ke dalam tanah dan mengalir, ke sungai bawah tanah.
Sebagai orang asli Gunungkidul, beliau sedikit bercerita tentang daerahnya. Kemudian saya tahu bahwa beberapa ‘punthuk‘ (bukit) di beberapa daerah sudah dihancurkan, pepohonan banyak yang ditebang, dan sebagainya.
“Suatu saat nanti, Gunungkidul akan mengalami kondisi yang buruk jika alamnya terus dirusak atau dieksploitasi secara besar-besaran tanpa ada upaya pelestarian,”
begitu kata Mas Ribut.
Dari mengikuti kegiatan mereka, saya kemudian sedikit demi sedikit memahami bahwa Resan Gunungkidul dan komunitas-komunitas lainnya hadir sebagai wujud kesadaran merawat alam yang telah memberi banyak hal.

“Meskipun pohon yang kita tanam belum tentu akan hidup. Namun tidak berarti kita menyerah begitu saja dan membiarkan alam terus dirusak, ini salah satu bentuk upaya kami untuk melestarikan alam bagi kehidupan generasi selanjutnya,” kata Mas Anjar, salah seorang pegiat Komunitas Resan.
Titik penanaman terakhir, yakni Telaga Kalongan. Dulu, telaga itu juga harum namanya karena keasriannya. Sekarang, keadaannya sungguh sangat meprihatinkan, Kini, yang tersisa hanyalah bau bacin yang amat sangat. Bangkai kodok kata teman-teman. Tanah dasar telaga tampak kering kerontang, bahkan di musim penghujan seperti ini, kondisi tanahnya retak-retak. Lagi-lagi, telaga yang ketiga ini juga hanya menyisakan cerita seperti dua telaga sebelumnya.
Saat asik menanam, salah seorang berteriak, “Pohon yang dulu masih hidup. Di sebelah sana.” suara itu disambut dengan senyum gembira. Pohon yang mereka tanam dulu masih hidup. Rupanya, sudah dua kali komunitas Resan Gunungkidul melakukan penanaman di tempat ini.
Tak terasa, matahari sudah tepat di atas kepala. Bibit pohon juga sudah habis ditanam. Setelah bertanam-tanam ria, acaranya kemudian berpindah ke markas Sanggar Lumbung Kawruh, rumahnya Mas Ribut. Teh panas segera terhidang dengan ditemani berbagai makanan hasil kebun. Pala pendem, ganyong dan kimpul, serta jajanan lainnya. Satu dua jurus, dan “Hap!” satu per satu mengisi perut yang sudah bernyanyi. Itu baru makanan pembuka, tiwul, sambel, dan jangan (sayur) menjadi makanan utamanya. Ada juga ‘Sega Berkat‘, berisi nasi dan sayuran yang dibungkus daun Jati.

Makan bersama-sama sambil sesekali bercanda. Hangatnya kekeluargaan khas ‘wong ndesa‘ sangat kental. Siapa pun yang pernah merasakannya, pasti akan merindukannya. Saya yakin! Maka, Mas Ribut berseru, “Pulanglah pulang,” dalam lirik lagunya yang berjudul ‘Fajar Pagi‘. Mas ribut ternyata juga seorang penyanyi bergenre reggae.
Selesai makan, janganlah pulang duluan. Masih ada sesi jagongan dan rasan-rasan sembari menunggu pencernaan mengolah makanan. Kalau di lingkungan akademis disebut diskusi, kalau di pedesaan disebut ‘jagongan‘. Di ruang tengah itu, masing-masing dari kami menyampaikan keluh kesahnya, tentang lingkungan, pertanian, pembangunan desa, pariwisata, dan sebagainya. Tidak ada yang menggurui. Semuanya saling berpendapat.
Jagongan bukanlah ceramah seseorang yang omongannya tidak boleh dibantah. Dari obrolan itulah kami membahas pentingnya merawat alam. Hubungan manusia dengan sekelilingnya dan manusia sebagai bagian dari alam itu sendiri. Tidak ada satu orang pun dari mereka yang menolak pembangunan. Namun kalau pembangunan merusak alam, nah itulah yang menjadi permasalahan.

Rencana pembangunan pariwisata desa misalnya, memoles sedemikian rupa dengan menggelontorkan uang yang tidak sedikit. Membuat dinding semen di telaga beserta wahana bermain di sekitarnya. Itu bagus, tapi hanya sementara. Efek jangka panjangnya, telaga itu akan mengering karena semen bisa mempercepat penguapan. Selain itu, dinding semen membuat akar tanaman sulit menembusnya. Sehingga mata airnya tidak akan terjaga.
“Kalau semua desa dijadikan desa pariwisata? Terus, siapa yang mau mengunjunginya? Kok koyo dagelan”
satu celetukan saat rasan-rasan tentang booming pariwisata di Gunungkidul.
Nama Mbah Jobeh juga tidak terlewatkan saat jagongan waktu itu. Konon, Mbah Jobeh adalah sosok luar biasa yang hanya didengar suaranya saja. Suatu hari, Ki Kentung ‘sambat‘ di sekitar petilasan Mbah Jobeh, “Waduh, tanamanku kok kering semua”. Selang beberapa saat, kemudian Ki Kentung terlelap. Dalam tidurnya, Ki Kentung bermimpi mendapat petuah dari Mbah Jobeh, “Sudahlah, tentramkanlah hatimu. Memang begitulah seorang petani, selalu ada halangannya”. Dan ketika Ki Kentung terbangun, tiba-tiba semua tanaman di tempat itu, yakni Bulak Pakel, menjadi hijau semua. Sehingga, tempat itu disebut sebagai Petilasan Mbah Jobeh. Jobeh adalah singkatan dari ‘Ijo kabeh‘ atau hijau semua.
Cerita itu mengisyaratkan bahwa sebenarnya simbah kita dulu sudah sadar betul tentang pentingnya menjaga alam. Bapak-bapak yang sedang gayeng jagongan itu tidak lupa berpesan kepada anak muda setempat untuk menjaga alamnya. Menjaga tanaman yang tadi sudah mereka tanam. Mereka harus menganggap pohon layaknya temannya sendiri. Barang sekali atau dua kali, pohon-pohon itu harus dikunjungi, disiram dan dirawat. Kalau bukan kita yang akan menjaga alam, lalu siapa lagi?
Salam Jobeh. Ijo Kabeh!