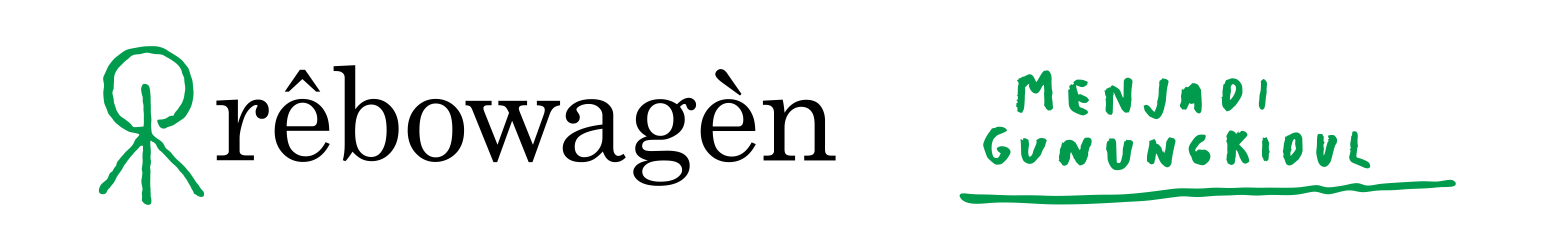Budaya(rebowagen.com)–Semasa masih hidup, simbah buyut acap bercerita kepada saya bahwa beliau pernah melakukan beberapa ritual, seperti ‘Pasa Patigeni‘ dan ‘Pasa Ngebleng‘. Menurutnya, kedua pasa/puasa tersebut merupakan ‘tirakat’ atau ‘lelaku‘ yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa zaman dahulu. Biasanya, orang yang melakukan ‘lelaku‘ ini karena memiliki tujuan atau hajat tertentu.
Setelah beranjak dewasa, saya baru paham dan mengerti bahwa apa yang dilakukan simbah saat itu merupakan salah satu ajaran dari ‘Kejawen‘. Dalam buku Kejawen: Philosofi dan Perilaku (2004), Soesilo menjelaskan bahwa ‘Kejawen’ merupakan pandangan hidup orang Jawa yang melakukan kehidupan berdasarkan moralitas atau etika dan religi yang tercermin dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan alam.
Sampai saat ini, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang masih menjalankan nilai-nilai ‘Kejawen’, seperti ‘semedi‘, ‘larungan‘, dan berbagai macam ritual sesaji. Selain sebagai bentuk aktualisasi diri terhadap nilai-nilai luhur, hal ini juga dilakukan untuk membangun ruang serta suasana kebatinan masyarakat Jawa untuk mencapai ketentraman hidup.
Ilmu Kejawen menjadi salah satu aliran kepercayaan yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, terutama di pulau Jawa. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal dan Kependudukan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada 102.508 jiwa penduduk yang menganut kepercayaan pada tahun 2020. Yang mana mayoritas beraliran Kejawen.
Sementara itu, di Gunungkidul sendiri, menurut data Agregat Kependudukan Kabupeten Gunungkidul Semester II Tahun 2021, ada sekitar 250 orang penghayat kepercayaan. Kelompok tersebut tersebar di beberapa Kapanewon, mulai dari Kapanewon Girisubo sebanyak 132 orang, Semanu 13 orang, Rongkop 68 orang, dan Saptosari sebanyak 15 orang. Sementara itu, untuk Kapanewon Playen, Karangmojo, Gedangsari, Wonosari, Panggang, tidak lebih dari 10 orang.
Penghayat kepercayaan sendiri diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PUU-XIV/2016. Dalam keputusan ini, MK memutuskan bahwa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wajib mendapatkan hak sosial dan politik yang sama dengan para penganut agama yang diakui oleh negara. Termasuk dalam hal Administrasi Kependudukan.
Tentu saja, keputusan tersebut membawa angin segar bagi para penganut kepercayaan di Indonesia, tak terkecuali di Gunungkidul. Selain mudah mengurus administrasi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK), adanya keputusan ini juga semakin memberi rasa aman bagi para penganut kepercayaan, yang dianggap rentan mendapat tindakan diskriminasi.
Adapun nama beberapa penghayat kepercayaan yang ada di Gunungkidul, yaitu Palang Putih Nusantara, Mardi Santosaning Budhi (MSB), Sapto Darmo, Umat Pran Soeh, Ngudi Utomo, Suryo Mataram, Sumarah, dan Hidup Betul. Dari sekian banyak kelompok tersebut, kini ada tujuh penghayat kepercayaan di Gunungkidul, yang mana mayoritas penghayat juga beraliran ilmu Kejawen.
Dikutip dari situs resmi Dinas Kebudayaan Gunungkidul, berikut penjelasan mengenai beberapa penghayat kepercayaan di Gunungkidul yang masih lestari, di antaranya:
Mardi Santosaning Budhi (MSB)
Salah satu kelompok penghayat kepercayaan di Gunungkidul yang masih eksis adalah Mardi Santosaning Budhi (MSB). Ajaran dari MSB sendiri, yaitu semedi, yang biasanya dilakukan saat pagi, sore, hingga malam hari atau menjelang tidur. Jenis semedi yang dilakukan pun tidak memerlukan ruang khusus dan dilakukan selama 5 hingga 30 menit.
Melansir laman resmi Warisan Budaya Takbenda Indonesia, MSB didirikan oleh Hardjodipuro bersama Abdul Madjid, RP Judodipurpo (Somadipuro), Praptoatmodjo, Prapto Mulyono, Dipososro, Warsono, B.Sc, Slamet Mangku Wasasmito, dan Dirjo Tugimin.
Kelompok penghayat kepercayaan yang didirikan pada 30 Mei 1990 di Kadipaten Wetan, Plengkung Taman Sari, Yogyakarta, ini berawal dari keprihatinan terhadap bangsa akibat penjajahan. Berangkat dari keresahan ini, Hardjodipuro, melakukan tapa brata dan mendapat tuntutan dari Tuhan agar menjalankan ajaran-ajaran yang diberkahinya, lalu dipraktikkan dalam laku kehidupan sehari-hari.
Secara umum, tujuan dari ajaran MSB adalah untuk mendalami ilmu dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar mendapat ketentraman, keselamatan, dan kebahagiaan lahir batin. Tujuan ini tergambar jelas dalam lambang MSB, yang terdapat gambar gelang rantai, padi dan kapas, gerigi, bintang tiga, serta tulisan MSB aksara Jawa.
Umat Pran Soeh

Umat Pran Soeh adalah penghayat kepercayaan di Gunungkidul yang berisi ajaran ilmu ‘kasukman‘. Kelompok ini percaya bahwa Rasul merupakan seorang priyayi atau orang Jawa asli bernama Romo Resi Pransoeh Sastrosoewignjo. Melalui Rasul-Nya, Tuhan menganugerahkan ilmu kasukman serta makrifat.
Secara etimologi, ma’rifah memiliki arti pengetahuan atau pengenalan. Sedangkan, dalam istilah sufi diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati (qalbu). Secara sederhana, ilmu makrifat adalah untuk mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga qalbu bisa melihat Tuhan.
Sementara, dikutip dari situs resmi Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, Umat Pran Soeh memiliki dasar serta ajaran, yang meliputi:
- Percaya dan menyembah kepada satu sesembahan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
- Mengakui bahwa Romo Reso Pransoeh Sastrosoewignjo adalah utusan Rasul Allah menjadi panutan Umat Pran Soeh.
- Mengikuti kebenaran semua agama yang diakui secara resmi oleh negara.
- Percaya adanya alam ghoib, alam kubur, alam antoro, dan alam akhir.
- Percaya akan kebenaran hukum karma, hukum sebab akibat, hukum ‘ngunduh wohing pakarti’.
- Percaya dengan reinkarnasi, ‘urip tumimbal’.
- Mengakui bahwa manusia terdiri dari unsur raga, sukma, dan nyawa.
- Mengakui adanya dosa asal, dosa warisan, dan dosa diri sendiri.

Dalam menyebarluaskan ilmu kebatinan ini, RPS Sastrosoewingnjo, dulunya menggunakan media wayang kulit. Banyaknya nilai-nilai luhur di dalam ajaran Pran Soeh ini, membuat RPS Sastrosoewingnjo memiliki banyak murid atau pengikut yang disebut Kadang Golongan. Mereka jugalah yang akhirnya turut berkontribusi besar dalam menyebarkan ilmu ini kepada sebagian masyarakat Gunungkidul dan masih eksis sampai sekarang.
Palang Putih Nusantara
Penghayat kepercayaan yang masih eksis di Gunungkidul selanjutnya adalah Kejawen Urip Sejati atau lebih dikenal dengan nama Palang Putih Nusantara. Di Gunungkidul sendiri, penghayat kepercayaan ini paling banyak ditemukan di Kapanewon Girisubo.
Ajaran Urip Sejati ini diterima oleh Bandoro Pangeran Haryo Suryodiningrat melalui ilham dan menjadi tuntunan yang harus diamalkan penganutnya. Setidaknya ada tiga amalan yang harus dikerjakan oleh para penganut Palang Putih Nusantara, yaitu ‘Sangkan Paraning Dumadi‘, ‘Manunggaling Kawula Gusti‘, dan ‘Memayu Hayuning Bawono‘.
‘Sangkan Paraning Dumadi‘ sendiri memiliki arti awal dan akhir dari adanya penciptaan alam semesta. Ketika manusia sudah memahami makna ini, ia telah mencapai kesempurnaan kehidupan yang bermakna.
Adapun yang dimaksud dengan ‘Manunggaling Kawula Gusti‘ adalah upaya menghubungkan diri dengan sadar, mendekat, serta manunggal dengan Tuhan. Sebab, menurut kepercayaan ini, tujuan hidup manusia adalah bersatu dengan Tuhan.
Sementara itu, ‘Memayu Hayuning Bawana‘ adalah upaya menjaga serta menciptakan kesejahteraan dan keselamatan dunia. Sebagai seorang hamba, manusia memiliki tanggung jawab untuk terus merawat, menjaga, dan melestarikan hal-hal baik di bumi ini.
Sapta Darma

Sapta Darma menjadi salah satu penghayat kepercayaan di Gunungkidul yang masih lestari sampai sekarang. Penghayat kepercayaan ini sudah ada sejak tahun 1954, yang dicetuskan oleh Hardjosapoero. Di Indonesia sendiri, penganut kepercayaan ini tersebar di 13 provinsi, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta.
‘Sapta’ sendiri memiliki arti ‘tujuh’ dan ‘Darma‘ yang berarti ‘kewajiban suci’. Sederhananya, penganut ajaran Sapta Darma harus melakukan tujuh kewajiban suci. Adapun inti dari ketujuh ajaran tersebut adalah sebagai berikut:
- Setia dan tawakal kepada Pancasila Allah (lima sifat Allah, yaitu Allah Maha Agung, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Kuasa, dan Maha Kekal).
- Dengan jujur dan suci haru harus setia menjalankan Undang-Undang Negara.
- Turut setia menyingsingkan lengan baju menegakkan berdirinya Nusa dan Bangsa.
- Menolong kepada siapa saja, bila perlu tanpa pamrih melainkan berdasarkan cinta kasih.
- Berani hidup berdasarkan kekuatan diri sendiri.
- Sikapnya dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan, halus susila beserta halusnya budi pekerti, yang selalu memberikan jalan yang mengandung jasa memuaskan.
- Yakin bahwa dunia ini tidak abadi, melainkan selalu berubah-ubah.
Adapun tata cara ibadah Sapta Darma adalah dengan bersujud. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa kelompok penganut kepercayaan ini menyembah Semar. Padahal, Semar hanya gambaran roh suci manusia yang asalnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Ngudi Utomo

Ngudi Utomo merupakan penghayat kepercayaan di Gunungkidul yang menekankan pada pentingnya tuntunan budi pekerti luhur. Ajaran ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mampu memperbaiki kualitas martabat kemanusiaannya serta menjadikan manusia mandiri, baik secara lahir maupun batin.
Inti dari ajaran Ngudi Utomo sendiri, yaitu nilai kemanusiaan yang berbudi pekerti luhur. Sebab, hanya dengan budi pekerti yang luhur, manusia bisa mengubah nasib ke tingkat yang lebih baik.
Dikutip dari laman putrongudiutomo-martowiyono.id, berikut isi ajaran Ngudi Utomo, antara lain:
- Baik buruknya manusia tidak hanya dilihat dari ilmu dan agama yang dimilikinya. Namun, yang paling penting adalah setiap laku hidup harus dilandasi dengan budi pekerti luhur.
- Adanya hukum sebab akibat, yaitu bahwa segala perilaku yang dilakukan oleh manusia senantiasa akan dipakai orang yang bersangkutan. Jadi, tetaplah selalu berbuat kebaikan dan kebenaran.
- Adanya pengetahuan mengenai kesadaran diri untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan karena ini merupakan kekuatan positif untuk mengembangkan martabat manusia dalam lingkaran baik ber-Ketuhanan yang abadi.
Itulah beberapa penghayat kepercayaan yang eksis dan masih lestari di Gunungkidul. Adanya kelompok-kelompok ini tentu semakin mewarnai kehidupan sosial masyarakat yang hidup di Bumi Handayani. Banyaknya penghayat kepercayaan ini, tentu tidak membuat masyarakat Gunungkidul tercerai berai. Justru mereka bisa hidup berdampingan, bahu-membahu, gotong-royong, dan saling menghargai satu sama lain, tanpa membeda-bedakan latar belakang kepercayaan.
Sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai tepa salira, memang sudah seharusnya masyarakat Gunungkidul menghargai serta menghormati kelompok minoritas ini.
“Perbedaan itu fitrah. Dan harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal.”
-KH. Abdurrahman Wahid-