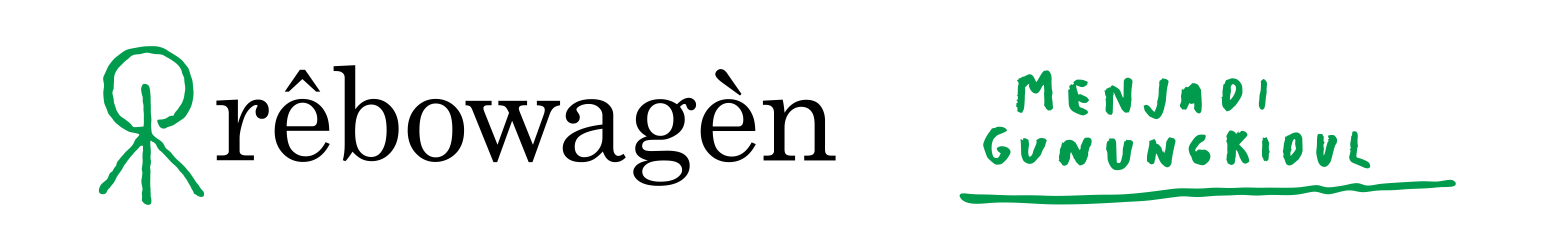Lingkungan(rebowagen.com)– Manusia Gunungkidul, hidup dan membangun peradabannya dalam kerasnya alam. Ungkapan ‘adoh ratu cêrak watu‘ memang sangat relevan. Geografis wilayah berupa bukit kapur yang mendominasi, menjadikan Kabupaten terluas di DIY ini identik sebagai daerah yang tandus dan kering. Marginal, miskin dan tertinggal adalah stigma yang lama tersandang.
Dibalik semuanya, Gunungkidul memiliki keunikan dan kekayaan geografis tak ternilai yang terkandung dalam buminya. Saat ini, Gunungkidul sedang berada dalam masa transisi menuju modernisasi. Zaman dan perubahan memang tidak dapat ditentang lajunya. Akan tetapi, euforia yang menyertainya membutuhkan sikap arif dalam menghadapi keadaan yang cepat sekali berubah ini. Pembangunan infrastruktur, serta eksploitasi tanpa pertimbangan kelestarian, tentu akan berpengaruh buruk terhadap keseimbangan ekosistem makro yang telah terbentuk selama jutaan tahun.
Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunung Sewu di Kabupaten Gunungkidul adalah bagian dari sebuah kawasan lindung geologi yang membentang dari Kabupatèn Bantul, Wonogiri sampai ke Kabupatèn Pacitan. Bentangan alam karst ini, sekilas memang hanya berupa batuan kapur berbentuk hamparan, bukit-bukit dan gua-gua. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kawasan karst adalah daerah yang terdiri dari batuan kapur yang berpori, sehingga air permukaan selalu merembes dan menghilang ke dalam tanah (permukaan tanah selalu gundul karena kurangnya vegetasi). Pemandangan ini memang identik dengan kawasan Pegunungan Seribu. Ada ribuan ‘punthuk‘ (bukit) yang ada di Gunungkidul bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Sesuai Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia nomer 3045 K/40/Men. 2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu sebagai kawasan lindung geologi. Luasan Kawasan Bentang Alam Karst Gunungkidul adalah 75.835,45 hektar. Pada tanggal 1 November 2022 lalu, Pemerintah Kabupatèn Gunungkidul mengadakan rapat koordinasi membahas peninjauan kembali tentang Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunung Sewu. Dalam rapat tersebut Pemerintah Gunungkidul memutuskan untuk mengajukan permohonan peninjauan ulang deliniasi KBAK kepada Menteri ESDM RI Cq. Kepala Badan Geologi untuk mengurangi luasan KBAK Gunung Sewu.
Pemerintah Gunungkidul mengusulkan untuk mengurangi kawasan KBAK seluas 37.018,06 hektar atau 51,19 persen dari luasan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pengurangan ini disebut untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yaitu pengembangan pariwisata, pembangunan infrastruktur dan industri.
Artinya, ketika pengajuan peninjauan ulang ini diterima, maka separuh lebih KBAK Gunung Sewu tak lagi menjadi kawasan lindung geologi lagi. Pembebasan bisa diartikan bahwa zona ini menjadi kawasan eksplorasi maupun eksploitasi ekonomi langsung dalam skala yang masif. Termasuk tentunya pembangunan infrastruktur ataupun pertambangan dalam skala besar.

Hal ini akhirnya memantik reaksi banyak pihak, ada yang mendukung, tapi banyak juga yang menentang. Beberapa pendapat mengkhawatirkan dampak negatif terutama faktor kelestarian ekosistem kawasan karst. Fungsi atau jasa ekologi karst untuk cadangan air tanah juga akan terancam. Badan PBB mencatat bahwa kebutuhan air bagi 25 persen penduduk dunia dipenuhi oleh fungsi ekologi sistem kawasan karst (ko. 1997- PIT- IGI 1999).
Karst juga mempunyai fungsi penyeimbang dari ancaman siklus karbon. Diketahui bahwa salah satu fungsi karst adalah sebagai penyerap karbon nomer satu selain pohon. Saat ini, Industri ekstraktif menyumbang 48 persen emisi karbon sebagai penyebab utama perubahan iklim global (Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca KLHK 2019).
Di sisi sosial dan perikehidupan masyarakat, segala perubahan ini dikhawatirkan akan membawa dampak pada tatanan sosial masyarakat Gunungkidul secara umum. Sementara pihak yang mendukung pengurangan kawasan karst mempunyai pemikiran bahwa potensi sumber daya alam Gunungkidul bisa dimaksimalkan untuk kemajuan ekonomi daerah.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) termasuk lembaga yang melakukan protes keras terhadap rencana ini. Himawan Kurniadi, aktivis WALHI Yogyakarta menyampaikan bahwa kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari Kawasan Karst Gunung Sewu, yang mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta), Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), dan Kabupaten Pacitan (Jawa timur).
“Sejak dulu, daerah karst memang identik sebagai kawasan kering, gersang, dan dilabeli stigma sebagai kawasan sulit air. Untuk sumber air permukaan memang iya, tapi sebetulnya, secara ekosistem, karst merupakan filter raksasa yang berfungsi untuk menyerap air hujan sebagai tampungan atau cadangan air bawah tanah yang sangat melimpah,” kata Adi .
Menurutnya, belajar dari proses advokasi yang selama ini sudah dilakukan, ada hal mendasar yang dibutuhkan agar Kawasan Karst Gunung Sewu terselamatkan dari praktik cara pandang eksploitatif dan menjadi praktik pengelolaan karst dengan memanfaatkan jasa ekologinya.
“Jasa atau fungsinya tentu sudah jelas, lahan karst sebagai kawasan pertanian, sebagai penyimpan cadangan air tanah, di isu perubahan iklim global, jasa ekologi karst itu ya sebagai penyerap karbon terbaik selain pohon. Bahkan jika ini soal wisata, banyak hal yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata tanpa harus merusak kawasan,”
imbuh Adi.
Terlepas dari semua itu, Adi menambahkan bahwa KBAK adalah kekayaan alam yang tak tergantikan. Proses pembentukan kawasan karst selama jutaan tahun adalah bagian dari sejarah geologi, jadi bukan hanya tentang manusia, tapi tentang sejarah bumi.
“Pemanfaatannya harus mempertimbangkan kelestariannya,” tegasnya.
Beberapa waktu lalu saya juga mengobrol dengan Bekti Wibowo Suptinarso, salah seorang aktivis penggerak Jaringan Petani Kawasan Karst Gunungkidul. Pria yang akrab disapa Bowo ini menyampaikan hal senada, bahwa Gunungkidul dan masyarakat yang terbangun di dalamnya sejak dulu identik dengan pertanian, terlepas bahwa lahan yang digarap termasuk lahan yang minus dan kurang subur.

“Saya tidak menentang pembangunan, karena pasti itu tujuannya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, tapi kelestarian dan keberlangsungan alam juga harus menjadi pertimbangan utama. Yang membutuhkan ruang hidup ideal itu kan tidak hanya kita yang hidup sekarang, tapi generasi anak cucu kita besok kan juga butuh,” kata Bowo.
Aktivis yang rumahnya sempat terkena pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ini menambahkan bahwa jika eksploitasi kawasan karst dilakukan dengan membabi buta, maka pengaruhnya tidak hanya pada sisi kelestarian lingkungan, tapi lebih jauh pada perubahan tatanan sosial masyarakat secara umum. Hilangnya budaya lokal terutama budaya agraris di masyarakat menurutnya pelan tapi pasti itu akan terjadi.
“Masyarakat akan kehilangan ikatan batin dengan ruang hidupnya, jadi akan sangat gampang untuk melepas milik mereka demi sebuah tren atau gaya hidup konsumtif sesaat,”
ungkap Bekti Wibowo Suptinarso.
Saat ini, menurutnya hal itu sudah banyak terjadi di Gunungkidul. Sisi negatif pariwisata misalnya, mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap gaya hidup warga desa
“Banyak yang mendapat uang kaget, entah dari ganti rugi atau menjual tanah. Lalu bingung karena uangnya terlalu banyak, akhirnya ya habis untuk membangun rumah bertingkat, beli kendaraan baru, setelah itu bingung lagi mau kerja apa, sementara lahan pertaniannya sudah dijual,” lanjutnya.
Terkait usulan pengurangan KBAK, Bowo menyatakan bahwa soal pemanfaatan karst memang sering menjadi dilema. Pada satu sisi, pemerintah ingin mengembangkan potensi daerah agar bisa mempunyai nilai tambah yang lebih. Tapi di sisi lain, eksploitasi kawasan karst memang dampaknya akan sangat berpengaruh terhadap kelestariannya. Menurutnya, ketersedian air tanah sebagai fungsi utama kawasan karst harus menjadi pertimbangan mendasar. Tentu hal ini terkait bahwa sumber air utama yang diambil PDAM Tirta Handayani Gunungkidul (Seropan, Bribin, Baron dll) berasal dari sumber air bawah permukaan yang berasal dari jasa dan fungsi ekologi kawasan karst.
“Sebetulnya tidak harus eksploitatif, pemanfaatan kawasan karst bisa lebih ke pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Dan jangan lupa, Gunungkidul juga punya potensi besar dalam bidang perikanan laut, tantangannya adalah bagaimana menjual hasil laut tidak dalam produk mentah, tapi produk olahan jadi, yang tentunya mempunyai nilai ekonomi yang lebih. Memang, untuk mewujudkan hal ini membutuhkan keseriusan banyak pihak,” imbuhnya.
Mengikuti perkembangan di sosial media tentang polemik usulan pengurangan kawasan perlindungan karst, saya tergelitik dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sudah seharusnya semua potensi alam di Gunungkidul dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kemajuan ekonomi. Ada benarnya memang, tapi tiba-tiba saya jadi teringat Almarhum Bapak pernah mengatakan bahwa dalam mencari rejeki itu harus dipikir dari cara mencari dan bagaimana memanfaatkan hasilnya
“Trima sak kêpêl cunthêl apa sak upa dawa?“
Kalimat itu tiba-tiba seperti terngiang kembali. Meski tentu dulu Almarhum Bapak mengatakan itu bukan dalam urusan soal kawasan karst. Sangat sederhana memang, namun jika saya pikir-pikir, kesederhanaannya mempunyai makna sebagai sebuah kearifan dari manajemen ekonomi sosial yang luar biasa.
Majas ‘sanèpan‘ petuah ini menggunakan perumpamaan nasi sebagai obyeknya. ‘Sak kêpêl cunthêl‘ (nasi satu kepal langsung habis), dan ‘sak upa dawa‘ (satu butir nasi tapi panjang/awet). Perumpamaan nasi ‘sak kêpêl cunthêl’ dimaknai sebagai suatu rejeki/anugerah/potensi yang berjumlah banyak, tapi karena digunakan secara boros maka langsung habis (cunthel). Sementara ‘sak upa dawa‘ dapat diartikan sebagai sebuah strategi manajemen pemanfaatan agar apa yang kita punyai bisa digunakan secara bijak, sehingga manfaatnya akan sustainable (berkelanjutan).
Pemaknaan petuah sederhana ini, jika kita pahami pada konteks pemanfaatan sumber daya alam, termasuk kawasan karst akan sangat relevan. Eksploitasi dalam skala besar, dalam satu kesempatan tentu mempunyai nilai ekonomi yang besar pula. Namun harus diingat, setelah itu akan habis/hilang (cunthêl). Sementara jika strategi pengelolaannya tepat, potensi kawasan karst tentu akan ‘sak upa dawa‘ (sustainable). Manfaatnya akan berkelanjutan bagi generasi selanjutnya.

Jika kita perhatikan, dampak dari kerusakan kawasan karst di Gunungkidul memang sudah tampak nyata saat ini. Bencana longsor dan banjir menjadi suatu hal yang umum terjadi. Gunungkidul yang sejak dulu dikenal dengan bencana kekeringan, saat ini menjadi langganan banjir. Sinyal-sinyal ini menunjukkan mulai ada ketimpangan yang terjadi pada siklus keseimbangan alamnya. Maraknya lahan perkebunan dengan tanaman monokultur skala luas, pertambangan, industri ekstraktif, industri pariwisata, yang tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah ancaman nyata bagi kawasan karst.
“Banyak alasan kawasan karst harus dilestarikan, daya dukung lingkungan harus diperhatikan demi keberlanjutan pencapaian keadilan sosial, ekonomi dan lingkungan,” (Ekosistem kawasan karst tak tergantikan, lipi.go.id 2017)
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” (UUD 1945 Pasal 33 ayat 3).
‘Sak kêpêl cunthêl sak upa dawa‘ adalah petuah arif dalam memaknai kebijaksanaan kita dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Sebuah pemahaman yang akan membawa pada pengertian bahwa alam bukan sekedar obyek untuk memenuhi kepentingan apalagi ego atau nafsu serakah manusia yang ujungnya adalah kerusakan.
Alam adalah ruang hidup bersama, semua komponen pembangun kehidupan di dalamnya adalah sistem ‘circular‘ yang masing-masing mempunyai fungsi dan manfaat untuk menjaga harmoni kehidupan secara umum. Tepat sekali sebuah petuah yang mengatakan bahwa
“Alam mampu mencukupi kebutuhan hidup seluruh manusia, tapi alam tidak akan mampu mencukupi nafsu serakah segelintir manusia”.