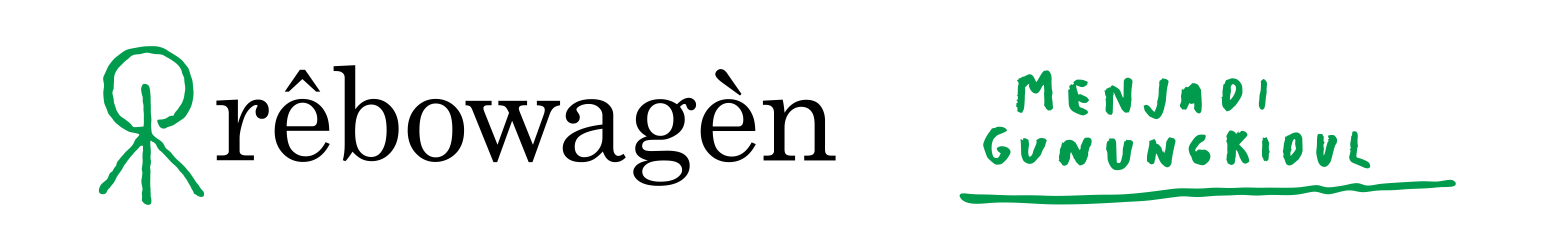Seni(rebowagen.com)-Dalam dua dekade terakhir ini, Gunungkidul mulai bertransformasi dari daerah marginal menuju modernitas. Daerah yang sejak dulu terstigma miring dengan keadaan tandus dan kering, namun ternyata menyimpan berjuta potensi. Beragam destinasi wisata alam booming beriring dengan kehadiran sosial media sebagai promosi gratis yang sangat efisien. Jutaan wisatawan membanjiri Gunungkidul setiap tahun. Hal ini akhirnya menarik banyak investor dan eskalasi pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata semakin marak.
Sisi positif dan negatif dari sebuah perubahan zaman ibarat dua sisi keping mata uang yang tak terpisahkan. Itu juga yang terjadi di Gunungkidul. Peningkatan ekonomi bagi masyarakat pelaku wisata melonjak tinggi. Begitupun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata meningkat dengan tajam. Nama Kabupaten Gunungkidul, juga semakin terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang menasional. Wacana Pemkab menjadikan Gunungkidul sebagai Bali kedua, harus disikapi tidak hanya dari sisi peningkatan ekonomi, tapi dari realitas bahwa mau tak mau, kita harus siap sebagai destinasi wisata global.
Pemodal yang mencium bau bisnis yang legit, kemudian berlomba-lomba untuk menginvestasikan uangnya untuk membeli properti di Gunungkidul. Membangun hotel, vila, restaurant hingga wahana wisata. Konon katanya, 90 persen pantai di Gunungkidul sekarang ini sudah bukan milik pribumi lagi. Privatisasi kawasan gejalanya semakin terlihat jelas. Hanya beberapa titik pantai yang saat ini masih dikelola langsung oleh warga lokal. Itupun mereka harus berjuang keras untuk bertahan dari segala ‘godaan‘, tawaran nominal yang seakan jumlahnya tak terbatas.

Sisi negatif yang lain adalah dampak sosial. Banyak yang menilai masyarakat Gunungkidul gagap dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat sekarang ini. Nilai-nilai lokal yang lama menjadi pondasi dan modal sosial masyarakat, lambat laun mulai tegerus dan pudar. Gunungkidul tak hanya bertransformasi secara fisik, tapi banyak hal yang terkait dengan nilai-nilai yang ada di masyarakatnya.
Perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat di segala sisi dan sendi kehidupan masyarakat akhirnya membawa banyak perubahan. Gesekan dan konflik sosial ataupun lahan penghidupan mulai sering terjadi seiring dengan simpul syaraf perputaran ekonomi yang menegang. ABDW Art Project, mencoba membaca gejala-gejala ini dan menyajikannya dalam sebuah event pameran seni rupa bertajuk ‘Pijat Refleksi‘. Pameran digelar 4 Februari sampai tanggal 28 Februari 2023 di Kedai Kopi 69, Wonosari, Gunungkidul.
“Tidak hanya pencapaian artistik yang ingin kami capai, tetapi ada misi-misi membaca keadaan sosial yang ada di Gunungkidul yang kami percaya akan semakin kota pada waktunya, dan akan sibuk dengan problem yang kompleks,”
kata Dwe Rahmanto, salah satu punggawa ABDW.
Komunitas ini terbentuk pada tahun 2018, berangkat dari para anggotanya rata-rata adalah seniman ‘lajon‘ (nglaju). Mereka bertempat tinggal di Gunungkidul, namun dalam proses berkeseniannya banyak berkiprah di Yogyakarta. Tak hanya para seniman yang ‘nglaju‘ untuk bekerja di Yogya, tapi banyak pekerja-pekerja lainnya. Solidaritas para ‘penglaju‘ ini akhirnya memunculkan istilah ‘sedulur lajon‘. Plat kendaraan bermotor Kabupaten Gunungkidul yakni AB …. DW, menjadi semacam tanda bagi para ‘penglaju‘ ketika bertemu dengan sesama ‘sedulur lajon‘ di jalan.

Plat nomor kendaraan inilah yang kemudian digunakan oleh para seniman untuk menandai komunitasnya. Tanda plat ini juga seakan menandaskan tentang asal mereka, yakni bumi Gunungkidul. Tentang ikatan batin dan rasa terhadap tanah kelahiran, dan kepedulian terhadap segala dinamikanya saat ini.
“Melewati usia lima tahun ini kami juga sepakat harus ada intropeksi terhadap kerja-kerja dan gagasan kami. Pertanyaan-pertanyaan secara internal, akan seperti apa kami kedepan, atau apakah kita sudah di jalur yang pas dengan gagasan-gagasan bersama. Di even ini, kami juga mencoba merefleksi kerja kolaborasi selama ini yang masih jauh dari sempurna dan butuh proses terus,” lanjut Dwe.
Pijat Refleksi adalah metode untuk meluruskan, merilekskan, membuat sesuatu yang tidak berjalan dengan baik menjadi lebih baik dan menjadi titik di mana simpul masalah menjadi solusi perbaikan. Dalam laku yang telah diwariskan nenek moyang turun temurun, kita mempunyai kebiasaan napak tilas sebagai sebuah ritual refleksi. Ritme ini bisa menjadi acuan dan mengasah ketajaman pikir, hal ini menjadi penting dilakukan dan diturunkan ke generasi selanjutnya. Refleksi ini menimbulkan rasa tenang, seperti meditasi bagi tubuh, melakukan relaksasi dan terapi diri.

Arahmayani Feisal, seniman dan juga penggiat lingkungan yang membuka pameran menyampaikan bahwa dalam dunia seni saat ini, banyak hal baru yang menarik untuk dicoba dan diekspresikan dalam karya.
“Seniman sebagai kreator, sangat penting menyampaikan ide-idenya untuk masyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Salah satunya tentang kepedulian dengan lingkungan hidup yang saat ini mengalami ancaman kerusakan yang sangat serius. Seniman kreatif harus peduli dengan hal ini,”
ujar aktivis perempuan yang biasa dipanggil Mbak Yani
Isu tentang lingkungan, menurutnya sudah menjadi permasalahan global. Seniman juga harus peka terhadap keadaan ini. Kerja-kerja kesenimanan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dalam bentuk pendekatan kreatif sangat dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat.
“Tidak hanya bentuk karya seni, tapi aksi langsung untuk mencari jalan pemecahannya. Seni bisa dimaknai dengan aksi, seorang seniman mempunyai pemikiran dan terobosan-terobosan yang kadang tidak dipikirkan oleh orang lain. Memunculkan gagasan untuk dikerjakan bersama, dan bisa dikerjakan lintas komunitas,” lanjutnya panjang lebar.

Mencoba menghubungkan keadaan Gunungkidul dengan tema pameran, Mbak Yani menyebut bahwa banyak hal yang berhubungan dengan budaya tradisi, kearifan lokal, lingkungan hidup, seni ataupun sosial, yang ditinggalkan para leluhur kita sudah mencapai titik pemahaman yang mendalam. Namun, di zaman modern ini kita sudah banyak yang lupa, acuh atau bahkan malah tidak tahu sama sekali.
“Warisan nilai-nilai kehidupan dari leluhur kita sudah sangat beradab dan manusiawi, dengan kreativitas daya cipta seni seniman masa kini, hal itu bisa kita tampilkan secara lebih elegant dan bisa diterima oleh banyak kalangan pada masa sekarang,” imbuhnya.
“Kedalam, refleksi ini adalah bentuk introspeksi secara pribadi, dan komunitas. Termasuk tentang kerja bareng, cara berjalannya enak tidak, acara-acara yang kita buat dalam bentuk kerja kolektif ketemu tidak, diharapkan dengan refleksi ini, ke depan bisa ketemu formulanya yang lebih pas. Untuk keluar, kita mencoba melihat kondisi Gunungkidul dengan dinamika sekarang yang berubah begitu cepat,” ujar Ismu Ismoyo, salah seorang peserta pameran, sekaligus penginisiasi ABDW Art Project
Ismu banyak menyoroti tentang perubahan Gunungkidul terkait pembangunan infrastruktur pariwisata dan proyek strategis nasional terutama pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Menurutnya, saat ini banyak terjadi perubahan pola-pola di masyarakat.

“Mau tidak mau, kita harus berpikir dan bersiap, karena akan banyak sekali yang berubah. Nah, bagaimana menjembatani perubahan ini sesudahnya, ini harus menjadi refleksi bersama. Posisi seni menjadi sangat penting untuk ditanyakan perannya. Seni kolektif berbasis daerah seperti ABDW, idealnya memang harus peka untuk mengangkat isu-isu lokal, karena hal itu menjadi penting untuk dibahas. Seni adalah kanal untuk ngomong tentang situasi saat ini. Kalau seniman tidak punya pijakan atau sikap terhadap hal besar tentang daerahnya sendiri ya repot,” ungkap Ismu panjang lebar.
Menurut Ismu, ada banyak hal yang ironis dalam proses pembangunan Gunungkidul. Ia mencontohkan, sering terjadi pembangunan infrastruktur bukan atas permintaan masyarakat, tapi kemauan (baca: program) dari pihak pemerintah. Ismu mengkhawatirkan tentang maksud program ini bukan sekedar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tapi demi suatu kepentingan lain.
“Idealnya, jika ada pembangunan skala besar, bukan hanya fisik yang dikejar, tapi kesiapan mental dari masyarakat juga harus diperhitungkan, terutama generasi muda agar siap untuk sebuah perubahan besar. Kerja-kerja seni, isu isu seni tidak hanya bergerak di studio, tapi memang harus ada gerakan aksi di tingkat bawah. Perubahan, pembangunan, kemajuan zaman tidak bisa ditentang, imbas dari hal ini yang harus disiapkan,” tandasnya.
Dalam sebuah karya, Ismu menggambarkan keadaan itu dengan visualisasi lukisan kuburan yang terbelah. Ia ingin mengatakan bahwa, selain tanah lahir, maka ada tanah mati. Permasalahan tanah di Gunungkidul adalah sesuatu yang pelik, satu sisi pemerintah punya andil, satu sisi yang lain masyarakat ingin mempertahankan, dan kadang itu tidak ketemu. Belum lagi sebagai bagian dari daerah istimewa DIY, di Gunungkidul memang banyak terdapat tanah Sultan Ground (SG) dan segala polemik pemanfaatannya.

Dalam lukisan ‘kuburan terbelah‘, Ismu menggunakan dua lembar kain yang digantung agak terpisah, sehingga terdapat celah sekitar 5 cm antar kain. Sekilas tampak lukisan itu terbelah di bagian tengah. Ismu menggambarkan sebuah ‘kijing‘ (batu nisan), di mana salah satu kepala nisan (maejan) diganti menjadi kerucut marka jalan (traffic cone). Sementara di bawahnya ada gambar sosok manusia telanjang yang sedang tertidur dengan muka berlubang.
“Orang akan bertanya ini metafor apa, kijing, maejan, ‘cone’ jalan, erat dengan pembangunan jalan atau kerja proyek. Saya mencoba mengatakan bahwa setiap ada sesuatu yang lahir (baru), tentu akan ada yang mati. Dengan kata lain, dalam perubahan dinamika zaman di Gunungkidul, ada banyak hal yang baru, tapi akan ada banyak yang tergusur, hilang atau mati, entah itu nilai, adat atau budaya masyarakatnya. Yang berupa fisik jelas, lahan pertanian, situs budaya, atau warisan alam, flora atau fauna,” terang Ismu.
Ia menekankan, bahwa ketika banyak terjadi ironi di tengah masyarakat sekarang, maka penggambaran dengan simbol-simbol benda mati akan lebih manusiawi daripada menggambarkan tentang manusianya sendiri. Ketika kita bisa membangunkan imajinasi seseorang dengan benda mati, maka karya seni mungkin akan lebih berfungsi.
“Narasi benda akan lebih mengena daripada narasi tentang manusia” pungkasnya
Guntur Susilo, seniman yang terkenal intens dalam memperjuangkan seni batik menambahkan, dalam tajuk Pijat Refleksi ini bisa dipahami sebagai sebuah instropeksi bersama. Ketika kita berintrospeksi pasti akan melihat ke dalam bukan melihat keluar dan pasti juga akan menunduk ke bawah bukan mendongak ke atas.

“Dan di saat menunduk tersebut visual yang kita lihat adalah kaki. Demikian pula dengan pijat refleksi tentu telapak kaki kita yang akan di pijat, karena pada telapak kaki sel-sel syaraf tubuh kita bertumpu,” kata Guntur
Sementara keseimbangan sel-sel dalam tubuh kita (jagat cilik) tersebut haruslah terus terjaga, sebab apabila terjadi ketidak seimbangan maka akan tumbuh sel-sel jahat yang akhirnya bisa menjadi tumor atau kanker. Begitu juga yang terjadi pada alam semesta (jagat gede), kita manusia adalah sel-sel alam semesta.
“Pilihan kembali kepada diri kita masing-masing, apakah ingin menjadi sel jahat yg menjadikan tumor atau kanker bagi alam semesta, ataukah tumbuh menjadi sel-sel baik untuk menjadi pelestari alam semesta ini,” lanjutnya.
Masih terkait dengan telapak kaki sebagai pusat tumpu syaraf manusia, Guntur menilai bahwa dengan modernitas dan kemajuan zaman semakin hari kecerdasan kita tanpa kita sadari sebenarnya semakin berkurang. Hal tersebut berkaitan erat dengan aktifitas kita sehari-hari yang dituntut untuk selalu menggunakan alas kaki (sandal/sepatu). Otomatis, hal ini akan mengurangi intensitas telapak kaki kita bersentuhan dengan tanah.

Sementara, tanah adalah salah satu unsur yang sangat mendominasi tubuh kita. Orang Jawa menganggap tanah sebagai ‘ibu‘, yang menghidupi manusia. Kita hidup diatas tanah, makan dari saripati tanah (padi dan semua jenis tanaman apapun yg kita makan tumbuh di tanah). Kita memakan daging ayam ataupun kambing pun mereka memakan tumbuhan yg hidup di tanah. Ketika intensitas kontak fisik tubuh kita dengan tanah berkurang, tanpa kita sadari hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan kita. Cerdas berbeda dengan pintar, Karena kadang pintar itu bisa untuk memintari orang lain. Namun ketika kita cerdas itu arahnya lebih kepada bijak (bijaksana). Bijak dalam menghadapi segala sesuatu, bijak dalam memperlakukan segala sesuatu.
“Bisa juga dikatakan, bahwa kita sekarang sudah mempunyai jarak dengan ‘ibu’ (tanah) tempat kita lahir. Rasa memiliki, menghormati dan menjaga tanah akan luntur teriring dengan semakin jauhnya jarak ikatan batin kita dengan alam. Keadaan di Gunungkidul sekarang, orang akan mudah menjual tanah, memperlakukan alam bukan atas pemikiran kelestarian, tapi dengan dasar nafsu dan ego kepentingan. Yang terjadi ya ketidak seimbangan yang berujung pada kerusakan,” jelasnya panjang lebar.
Guntur mencoba menterjemahkan segala pemikirannya ini dengan sebuah karya dua dimensi dalam dua lembar kain. Ia menggambar sepasang telapak kaki tentang simpul-simpul syaraf kehidupan masyarakat. Satu telapak kaki tergambar landscape alam Gunungkidul. Bukit-bukit karst, pohon, lahan pertanian, terasering batu dan ciri morfologi bentang alam Gunungkidul yang menjadi tumpuan hidup masyarakatnya selama ini. Sementara satu telapak kaki yang lain, tergambar keadaan modernitas zaman. Jalan yang lebar, alat berat, gedung dan segala keriuhan suasana kota. Ia lalu menghubungkan keduanya dengan simbol gambar sepasang mata, ruas tulang belakang dan otak manusia sebagi organ vital gerak laku fisik dan pemikiran masyarakat Gunungkidul.

Dalam pameran ini, selain Dwe, Ismu dan Guntur, banyak perupa muda Gunungkidul yang ikut memajang karya. Lembu, Endru Pragusta, Flea, Dilyan, Ghofur, Adi, Dela dan Almarhum Dodot. Juga ada performce art dari Cik Lin yang menampilkan keahliannya dalam hal pijat refleksi. Cik Lin lebih senang menyebut keahliannya buka dengan kata pijat, tapi ‘dadah‘, karena ‘dadah‘ adalah salah satu tekhnik relaksasi tubuh warisan leluhur yang masih dilestarikan sampai saat ini.
Gunungkidul memang harus bersiap di segala sisi menghadapi perubahan. Proses modernitas dengan segala kekuatan kapitalnya adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari karena itu adalah sebuah ‘ketentuan’ zaman. ‘Kali ilang kedhunge‘, ‘pasar ilang kumandange‘ adalah ungkapan-ungkapan leluhur sebagai sebuah ‘warning‘ tentang hal ini. ABDW merespon hal ini dengan sebuah karya bersama yang diberi tajuk ‘Rog Rog Asem‘, yang oleh para orang tua kita dulu ditambahi ucapan ‘ilang sarap sawane‘. Dua ungkapan itu adalah sebuah petuah bahwa apapun yang sekarang terjadi, adalah sebuah ketentuan (wis tekan jangkane). Dan kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar agar terhindar dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi.