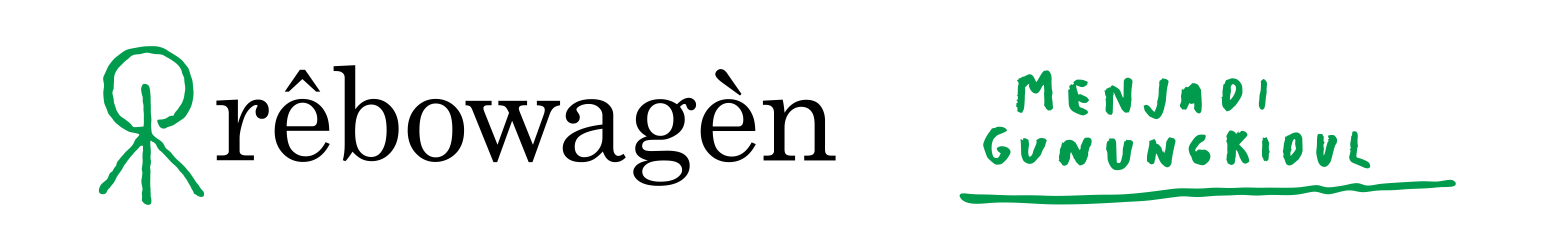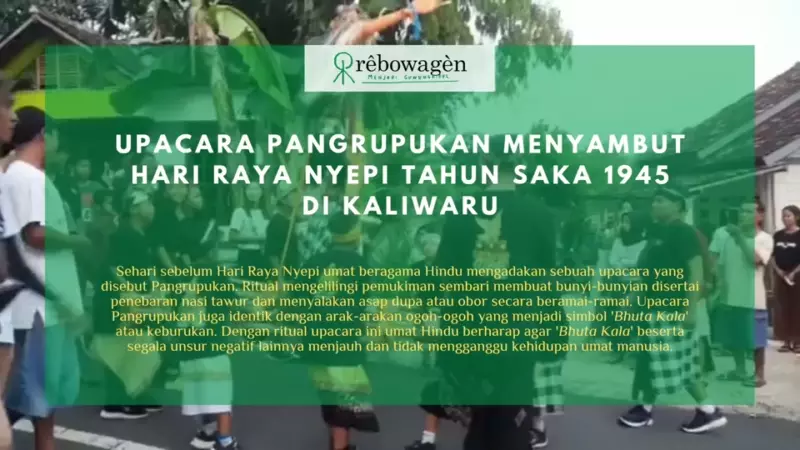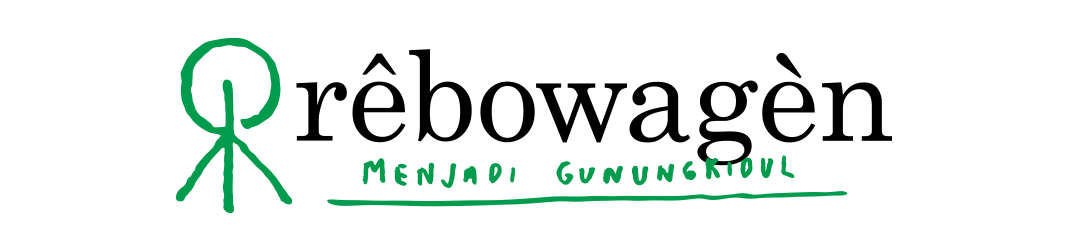Budaya(rebowagen.com)– Memasuki akhir Bulan Januari 2023, warga petani di Gunungkidul mulai melakukan musim panen padi. ‘Mbok Sri Sedana‘, demikian warga desa menyebut untuk komoditas utama pertanian penghasil beras ini. Masyarakat petani sangat memuliakan jenis tanaman padi karena nasi merupakan makanan pokok sehari-hari. Masyarakat Jawa menyebut padi sebagai pengejawantahan dari ‘Dewi Sri’. Pada bagian rumah petani dulu ada ruangan khusus untuk menyimpan ‘gabah‘ (hasil panen padi), yang disebut lumbung. Budaya lumbung ini akan sangat membantu cadangan makanan jika terjadi krisis pangan.
Pada beberapa desa, prosesi memulai panen padi masih menggunakan tradisi upacara ‘wiwitan‘. Perhitungan hari baik akan dipilih oleh ‘sesepuh‘ untuk menghormati Mbok Dewi Sri yang akan dipulangkan (dipanen). Setelah itu, warga akan beramai-ramai bergantian, saling membantu secara gotong royong memanen padi dari ladang dan sawah mereka. Budaya gotong royong ini di Gunungkidul disebut dengan istilah ‘sambatan‘. Berasal dari asal kata ‘sambat‘ (meminta tolong), ‘sambatan‘ diterjemahkan dalam kegiatan kerja bersama tanpa upah dengan dilakukan secara bergiliran dari satu warga ke warga yang lain.

“Liyane sambatan, nak mbiyen eneng cara neba karo derep”
(“selain sambatan, kalau dulu ada istilah ‘neba’ dan ‘derep'”)
cerita Mbah Jono, saat saya kebetulan ikut ‘sambatan‘ panen padi di tempat tetangga kemarin.
“Nek neba ki ya meh pada sambatan, ning biasane wis sak rombongan utawa kelompok dewe, dadi giliran sak anggota. Gek ora mesti ngarit pari, kadang neba uwur jagung, dele apa duduh suket (kalau ‘neba’ itu ya hampir sama dengan sambatan, tapi biasane sudah ada rombongan atau kelompok sendiri, jadi bergiliran antar anggota. Terus pekerjaannya tidak harus memanen padi, terkadang ‘neba’ menanam jagung, kedelai atau menyiangi rumput)” lanjut Mbah Jono bercerita di saat kami ‘wedangan’ di sela-sela ‘ngerek’ (merontokkan padi).
Kalau untuk ‘derep‘, Mbah Jono menjelaskan, kerja ini setengahnya memakai upah, tapi tidak dalam bentuk uang melainkan hasil panen itu sendiri. Jadi ada warga panen padi kebetulan lahannya luas, maka ada yang kerja ‘derep‘, dengan dikasih upah ‘gabah‘ oleh sang pemilik lahan.

Obrolan kami menjadi gayeng, saat tetangga-tetangga yang sudah lumayan ‘sepuh‘ ini dengan bersemangat menceritakan kebiasaan pertanian di waktu mereka muda. Rata-rata, yang ikut ‘sambatan‘ kali ini memang usianya sudah diatas 60 tahun.
“Penak jaman saiki, sambatan nek ingon lawuhe sega iwak, lha nak biyen ya gur sega pletik lawuh jangan”
(“enak zaman sekarang, sambatan kalau makan lauknya nasi ikan, lha kalau zaman dulu ya cuma thiwul campur nasi, lauknya cuma sayur”)
sahut Mbah Satikem yang mendengar obrolan kami.
Saat istirahat selepas makan siang, obrolan kami semakin ramai, bahkan sampai melebar ke tema pertanian sekarang di banding dengan zaman dulu. Cerita mereka, dulu petani belum mengenal padi unggul yang sekarang sudah lazim di tanam. Petani masih menggunakan jenis padi varietas lokal yang umurnya lebih panjang.

“Jenenge pari jero, umure eneng sing 5 sasi, 6 sasi, lha pari ondel ki ngasi 8 sasi lagi tua. Gek le manen dieneni nganggo ani-ani (namanya ‘pari jero’, umurnya ada yang 5 bulan, 6 bulan, lha jenis padi ‘ondel’ umurnya bisa sampai 8 bulan baru dipanen. Lalu panennya dengan cara ‘dieneni’ memakai alat ‘ani-ani’)” kata Mbah Ngatir ikut bernostalgia menerangkan dengan semangat.
Beberapa jenis padi lokal yang mereka sebut, sempat saya list, diantaranya Langsep Ondel, Serung, Mayangan (jenis padi berbulu), Gogo, Pari ketan dhuwur, Serang, Sentani, dan Puthu. Menurut mereka, rata-rata umur padi itu semuanya di atas 5 bulan. Beda dengan umur padi unggul sekarang yang rata-rata tiga bulan sudah bisa dipanen. Jenis padi lokal tadi, untuk saat ini hampir bisa dikatakan telah punah keberadaannya. Petani lebih memilih untuk menanam jenis padi unggulan, disamping umurnya lebih pendek, hasil panennya juga lebih banyak
“Nek rasane sega, pari saiki karo pari biyen, enak pari biyen, pulen, gek ora gampang sayup (kalau rasa nasinya, padi sekarang dengan padi dulu, enak padi dulu, pulen terus tidak gampang basi)” kata mereka saling menyahut.

Kembali ke tema ‘sambatan‘, para ‘sepuh‘ ini mengakui bahwa saat ini banyak budaya gotong royong di masyarakat yang mulai ditinggalkan. Secara tidak langsung mereka ingin mengatakan bahwa, zaman memang telah berubah. Saat ini, banyak hal dinilai dengan nominal uang, termasuk tenaga untuk membantu panen.
Beberapa hal memang saling mempengaruhi terhadap keadaan ini. Di antaranya, banyak petani yang sudah ‘sepuh‘ dan tidak kuat lagi untuk ‘sambatan‘. Jika tidak punya wakil (anak-anak mereka merantau dll), terpaksa mereka harus mengupah tenaga untuk memanen hasil pertanian mereka. Ada juga trend tenaga borongan. Biasanya, tenaga borongan ini mempunyai kelompok tersendiri untuk memborong pekerjaan panen dari seorang warga. Ketika harga borongan kerja disepakati, maka yang memborongkan akan menerima hasil panen mereka dalam keadaan bersih, diantar sampai ke rumah.
Perkembangan zaman memang banyak menggerus nilai-nilai kebersamaan di masyarakat. Kepraktisan disepakati sangat membantu memudahkan segala urusan. Meski tak bisa dipungkiri, ‘sambatan‘, ‘neba‘, ‘derep‘ pernah menjadi praktek sosial yang bisa mengikat individu-individu menjadi ikatan komunal, menumbuhkan rasa saling membutuhkan berdasar kebutuhan bersama.