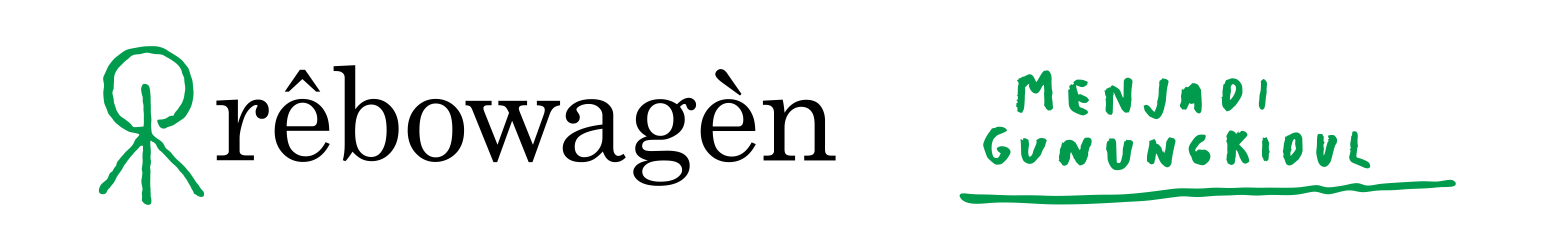Lingkungan(rebowagen.com)– Wilayah Gunungkidul telah lama mendapat stigma sebagai sebuah wilayah yang tandus. Bencana kekeringan seakan menjadi hal yang rutin saat memasuki musim kemarau. Secara geografis Gunungkidul dibagi menjadi tiga zona. Sebelah utara adalah Zona Batur Agung, Ledoksari pada bagian tengah dan Gunung Sewu (Pegunungan Seribu) pada bagian selatan. Pada setiap zona, ada beberapa perbedaan dalam hal siklus hidrologi.
Zona Utara sebagai daerah tangkapan air hujan utama, karakter air muncul dalam bentuk mata air dan sungai kecil yang beraliran deras. Pada Zona Ledoksari tengah, mata air juga banyak bermunculan dan sungai sungai besar beraliran lambat. Pada zona ini, masyarakat juga banyak membuat sumur untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari.
Sesuai sifat alami air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, pada zona selatan Gunung Sewu, air berada di bawah tanah. Banyak aliran sungai permukaan yang hilang ditelan bumi, kemudian menjadi sungai bawah tanah yang bermuara di laut (Bribin, Seropan, Kali Suci, Banyu Sumurup dll).
Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang membentang dari Gunungkidul hingga daerah Wonogiri dan Pacitan juga berperan penting untuk menjaga cadangan air tanah. Kawasan Karst mempunyai responbility atau daya serap air yang tinggi. Air hujan diserap kemudian ditampung dalam bentuk danau bawah tanah (danau subterain). Danau seperti ini, biasanya berhubungan dengan gua, aquifer atau mata air.

Pada bagian selatan ini, sumber air yang tampak di permukaan adalah telaga. Sebelum ada Perusahaan Air Minum (PAM) dan Penampung Air Hujan (PAH), sumber air utama di wilayah bagian selatan Gunungkidul adalah telaga. Keberadaanya hampir merata di wilayah pegunungan Seribu. Ratusan telaga ini selama berabad abad ikut mengiringi perikehidupan masyarakat. Menjadi tumpuan bagi mereka untuk mencukupi kebutuhan akan air, mulai dari minum, mandi, mencuci, maupun ‘ngguyang’ atau memandikan ternak ternak mereka.
Melansir kontan.co.id, data dari Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, mencatat ada 460 telaga di wilayah Bumi Handayani. Survey terakhir, dari jumlah itu ada 355 telaga yang segera mengering jika musim kemarau tiba. Saat musim penghujan, seluruh telaga mampu menampung air sebanyak 5.149.955 m3 (meter kubik). Saat musim kemarau menyusut menjadi 1.119.386 m3 (meter kubik).
Artinya, banyak telaga yang sudah kehilangan fungsinya sebagai penampung air. Bahkan tercatat, ada puluhan telaga yang sudah beralih fungsi sebagai lahan pertanian, lapangan, ataupun bangunan fasilitas umum.
Melansir dari kantor berita jogja.antaranews.com, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul menyatakan bahwa sebagian besar telaga di Gunungkidul memang mengalami kekeringan di musim kemarau. Berdasar survey lapangan dan klasifikasi data dari Tim Fakultas Geografi UGM, dari 281 telaga, hanya tersisa 71 telaga yang masih bisa dimanfaatkan airnya di musim kemarau. Sementara sisanya mengalami kekeringan total.
Peran dan fungsi telaga sebelum tahun 2000
Dulu, keberadaan telaga bagi seluruh masyarakat adalah utama. Setiap hari, banyak warga yang berkumpul di telaga, dengan berbagai aktivitas. Mandi, mencuci, mengambil air, memandikan ternak, memancing ikan, atau sekedar bersantai dan bercengkerama sambil ‘momong’ atau mengasuh anak anak mereka. Yang muda-mudi juga ada yang sengaja janjian, atau ketemuan di telaga sambil mandi atau mencuci.

“Masa kecil dan remaja seangkatan saya memang banyak beraktifitas di telaga. Kami sampai hafal siklus alami yang terjadi, mulai dari musim ‘mijah urang dan yuyu’, musim ikan mujaer dan yang lain. Telaga bagi kami adalah wahana alam untuk bermain dan belajar,”
kata Sigit Purnomo, seorang pemerhati telaga.
Sigit yang saat ini menjadi lurah Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan, memang mempunyai ikatan batin yang kuat dengan telaga. Rumahnya dekat dengan telaga Boromo di Padukuhan Trowono, Kalurahan Karangasem. Masa kecil hingga remaja ia habiskan bersama teman-temannya di telaga.
“Beranjak remaja, ada satu kegiatan yang menarik, yakni ‘ngindhik’ (mengintip) orang mandi di telaga. Atau janjian dengan yang di ‘sir’ (ditaksir) untuk sekedar bertemu di telaga,” lanjut Sigit bernostalgia.
Pada pagi atau sore hari, menurut Sigit, warga memang tumpah ruah di telaga dengan berbagai keperluan, atau sekedar ingin berkumpul dengan teman-temannya. Lokasi telaga memang umum dijumpai banyak pohon pohon besar perindang, entah itu beringin, klumpit, jambu klampok, winong, trembesi, bulu, kepuh atau jenis pohon besar yang lain. Suasana telaga yang asri dan nyaman, menjadikan lokasi telaga menjadi semacam ‘rest area‘ alami. Warga melepas lelah sambil mandi atau sekedar mengobrol setelah bekerja seharian di ladang-ladang mereka.

“Sehabis bermain, kami dulu biasa minum air telaga secara langsung, dari ‘nyegat’ orang yang ‘mikul jerigen’ atau mengambil air dari telaga. Tetapi tak ada ceritanya yang sakit perut,” lanjutnya.
Banyaknya interaksi sosial yang terjadi, akhirnya melahirkan banyak adat istiadat atau budaya masyarakat yang berkorelasi langsung dengan keberadaan dan fungsi air di telaga. Pada adat ‘besik telaga‘ atau ‘bersih dusun’ (rasulan), telaga dianggap sebagai suatu tempat yang penting. Upacara adat hingga kesenian rakyat dipentaskan di tepi telaga. ‘Ubarampe‘ sesaji juga banyak diletakkan di pohon-pohon besar di tepian telaga.
Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan zaman dan peradaban, lambat laun fungsi telaga ini semakin tergerus. Bersamaan dengan alih fungsi atau rusaknya lingkungan kawasan pendukung telaga, maka airnya banyak yang mulai mengering di musim kemarau. Maksud baik pemerintah dengan program revitalisasi telaga, dengan mengeruk dan memperdalam telaga justru membuat ekosistem telaga menjadi berubah. Telaga dikeruk dengan maksud agar debit airnya bertambah. Talud permanen yang dibuat mengelilinginya justru malah membuat telaga semakin cepat mengering, dan tidak lagi mampu menampung air hujan.
“Banyak faktor yang membuat telaga-telaga di Gunungkidul mengering airnya. Di samping rusaknya kawasan pendukung dengan kurangnya vegetasi tanaman yang berfungsi konservasi, biasanya faktor terbukanya “luweng” bisa menjadi penyebab utama. Tapi yang jelas, saat telaga dibangun permanen dapat dipastikan airnya akan cepat mengering,” imbuh Sigit.
Saat ini, Sigit aktif mengajak masyarakat untuk kembali ‘mendekat’ dengan telaga. Ia dan para generasi muda aktif melakukan edukasi dengan media sinema (film). Beberapa film tentang aset lokal telah diproduksi dengan bendera ‘Titik Balik Picture‘. Beberapa diantaranya yakni ‘Telaga’, ‘Radio’, ‘ Keris’ dan beberapa yang lain.
“Pemutaran film mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat, terutama yang tua-tua. Mereka merasa seperti diingatkan kembali terhadap kenangan masa mudanya tentang telaga. Harapan kami, warga akan kembali mempunyai rasa memiliki terhadap telaga, sehingga tentu nantinya kelestariannya akan terjaga,” pungkas Sigit.
Sidiq Asiyanta (43), seorang pemerhati telaga, warga Padukuhan Bulurejo, Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, menyatakan hal senada. Sidiq yang rumahnya dekat dengan Telaga Winong ini menyebut, banyaknya kasus keringnya telaga setelah dikeruk dan dibangun talud permanen, menurutnya terjadi karena hilangnya lapisan dasar telaga.
“Lapisan yang berupa membran kedap air ini terbentuk secara alami selama ratusan tahun yang berfungsi sebagai penahan air. Orang desa biasanya menyebut lapisan ini dengan istilah “lemi”, atau partikel partikel sangat lembut, menjadi semacam membran alami yang melapisi dasar telaga. Pada proses pembangunan telaga, ada alat berat yang masuk dan mengeruk tanah, sehingga lapisan ini rusak,” terang Sidiq.

Sidiq yang sehari hari bekerja sebagai pendamping Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) ini mencontohkan dua buah telaga dalam satu kawasan tetapi keadaanya saat ini berbeda, yaitu Telaga Winong dan Telaga Suci, yang terletak di Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari.
Telaga Winong adalah salah satu contoh telaga yang keadaanya relatif masih alami, puluhan pohon resan masih lestari, tumbuh di sekeliling telaga. Luas Telaga Winong mencapai kurang lebih 3 hektar, melintasi Kampung Winong di sisi timur, Kampung Gondang disisi barat, Kampung Ngepung disisi selatan dan disisi utara merupakan wilayah Padukuhan Tileng.
“Air Telaga Winong belum pernah kering, orang yang paling tua di desa kami juga mengatakan bahwa ia juga tidak tahu kapan Telaga Winong airnya mengering,” lanjutnya.
Saat ini, pemanfaatan air telaga Winong bagi masyarakat hanya untuk keperluan mandi dan mencuci. Itupun hanya terbatas pada warga dengan usia tertentu, diatas 50 tahun. Oleh karang taruna atau kelompok masyarakat, pada bulan tertentu telaga di tebar benih ikan untuk pemancingan.
“Telaga Winong termasuk telaga yang belum banyak dilakukan revitalisasi, hanya penguatan talud di beberapa pinggir telaga, sebagian besar talud masih alami berupa tatanan batu kosong dan batu utuh yang menyatu dengan akar akar pohon resan yang mengelilinginya,” lanjutnya.

Menurut Sidiq, fungsi telaga mulai berkurang sejak akhir tahun 1990. Hal ini disebabkan karena kondisi kualitas air yang semakin menurun. Air tidak jernih lagi dan mulai berkurang jenis jenis ikan, udang dan kepiting.
“Sekitar tahun 1993 saat terjadi kemarau panjang airnya mengalami penyusutan drastis dan mengalami perubahan warna menjadi kehijauan,” lanjut Sidiq lagi.
Faktor lain berkurangnya fungsi telaga menurut Sidiq, juga mulai masuknya program pemerintah melalui pembangunan Bak Penampung Air Hujan (PAH) yang masuk ke desanya sekitar tahun 1993. Teknologi sederhana PAH sampai saat ini masih aktual dan digunakan warga untuk memanen air hujan (rain harvesting).
“PAH dibangun baik secara komunal maupun individu sebagai tabungan air hujan. Tampungan ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan minum dan memasak, selanjutnya pelayanan air PDAM juga mulai masuk, sehingga warga kadang tidak perlu lagi ke telaga. Aktifitas memandikan ternak sapi yang sangat umum dilakukan oleh masyarakat petani dulu, lambat laun juga mulai ditinggalkan sejak awal tahun 2000 hingga saat ini,” imbuh Sidiq.
Sekitar jarak 500 meter terletak Telaga Suci yang konon cerita sejarahnya lebih tua keberadaanya jika dibanding telaga Winong. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah bukit atau cempluk. Saat kami sampai di sana, keadaan telaga memang betul betul telah kering, tanah dasar telaga tampak merekah atau ‘nelo’. Banyak warga yang memakai telaga kering ini untuk menjemur gaplek atau jengki (kulit singkong).

“Telaga Suci merupakan telaga tertua yang ada di wilayah kalurahan Kepek dan dulunya ukurannya sangat luas yaitu mencapai 11 ha melintasi 2 bukit (cempluk) terletak diantara dua bukit sepanjang kurang lebih 1500 meter memanjang melintasi kampung Galeng, Sawah dan Dukuh,” terang Siddiq.
Menurut cerita orang tua, pada sekitar tahun 1984, telaga Suci mengalami penyusutan air yang sangat drastis, diperkirakan terjadi karena ada kebocoran pada ‘luweng‘ telaga. Meskipun dilakukan perbaikan namun kondisi air semakin menurun kuantitasnya hingga pada tahun 1987 kondisi air benar benar menghilang.
Pada tahun 2008 pasca gempa bumi dilakukan pembangunan kembali telaga Suci namun hanya 1/3 dari luas telaga yang terletak di kampung Sawah padukuhan Wareng, sedangkan untuk sisi barat ke utara yang dulu masuk kawasan telaga, saat ini sudah menjadi tanah tegalan. Pembangunan meliputi pengerukan sedimen, penguatan talud serta penanaman pohon perindang di sepanjang pinggir telaga.
Setelah musim penghujan, air telaga hanya bertahan kira-kira 1 bulan selanjutnya pada musim kemarau menjadi mengering. Pada masanya dahulu telaga suci dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat kalurahan Kepek dan dari luar wilayah kalurahan yaitu Kalurahan Ngloro, Kanigoro dan Jetis.
“Konon cerita, Telaga Suci ini dulunya sangat elok seperti sungai yang mengitari dua bukit dengan pepohonan di sekeliling telaga yang rindang. Tapi sekarang semua hanya tinggal kenangan,” pungkas Sidiq.

Keberadaan telaga di Gunungkidul memang sangat khas. Ratusan ceruk batuan kapur berisi air ini masing-masing mempunyai cerita dan romantisme tersendiri bagi warga yang lahir dan besar di wilayah selatan pegunungan seribu. Saya jadi teringat cerita Jaka Tarub dan tujuh bidadari. Kisah percintaan manusia dengan bidadari ini berawal dari seting telaga.
Telaga memang identik dengan tempat yang indah seperti alam nirwana (surga). Penggambaran ini sangat kuat terasa di fragmen ‘suluk‘ seorang dalang dalam pementasan wayang kulit. Betapa dalam ‘suluk‘ ini, sang dalang menggambarkan keadaan telaga. Dalam bayangan ketenangan airnya diibaratkan bagaikan langit yang luas.
– Suluk Pathêt Manyura Jugag –
Yahni yahning talaga talaga kadi langit …
mambang tang pas wulan upama nika…
Wintang tulyan kusuma ya sumawur..
lumra pwêkang sari kadi jalada.Airnya bening, telaga luas bagai langit..
bulus (kura kura) yang mengambang bagaikan bulan…
bintang seperti bunga yang bertebaran…
tepung sari bunga berserakan bagaikan awan.