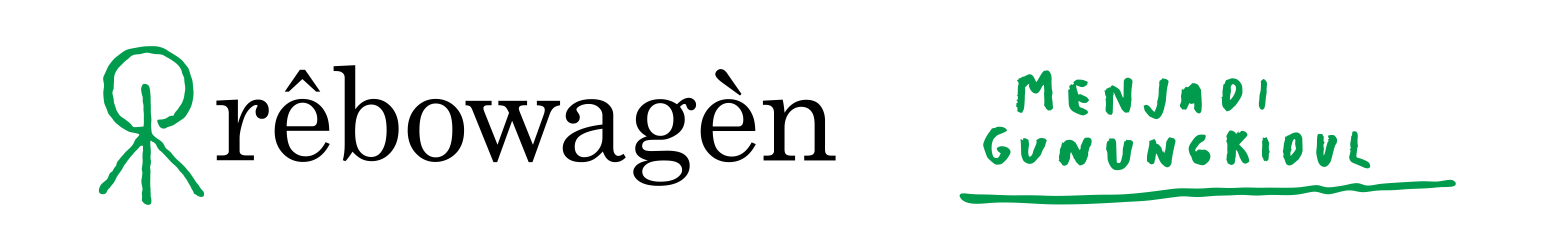Budaya(rebowagen.com)-Pawon dalam konteks masyarakat Jawa memiliki dua makna, ‘pawon’ sebagai dapur dan ‘pawon’ sebagai tempat perapian (tungku). Kalau orang Bali, biasa menyebutnya ‘paon‘. Pawon berasal dari kata ‘awu‘ atau abu. ‘Pa-awu-an‘, yang melebur menjadi pawon. Bisa juga diartikan sebagai tempat abu bersemayam (hasil pembakaran kayu, menjadi abu). Realitanya, pawon memang dijadikan tempat ‘abu’ bersemayam, hasil dari pembakaran kayu bakar untuk memasak. Karena berhubungan dengan abu, pawon kerap disebut sebagai ruang yang kotor. Ketika memasuki pawon, akan nampak angus (jelaga), abu, dan sawang (jaring sarang laba-laba) yang tampak bergelantungan dimana-mana.
Dalam skala yang lebih makro, bolehlah kita umpamakan ‘pawon‘ dengan dapur magma gunung berapi. Dalam siklus letusan, gunung akan mengeluarkan lahar dari dalam perutnya. Material letusan yang awalnya adalah lahar api yang panas, akan berubah menjadi abu yang akhirnya menyuburkan lahan para petani. Pawon adalah bentuk kecil dari gunung berapi, kayu yang dibakar habis menjadi abu. Abu ketika sudah penuh, akan dipindah oleh petani untuk memupuk tanamannya. Tanamannya pun menjadi subur, begitu seterusnya.
PAWON DALAM TATA RUANG
Pawon dalam konteks ruang kerap diklasifikasikan sebagai ruang yang ‘kotor‘. Hal ini menyebabkan desain tata ruang pawon sering didekatkan dengan kakus atau kamar mandi. Biasanya terletak di bagian rumah paling belakang. Ia memiliki ukuran ruang cukup luas, dan memiliki akses pintu masuk paling banyak. Di rumah simbah, yang bentuk rumahnya masih tradisional, pintu masuk menuju pawon ada empat. Dari ‘mburi omah‘ (belakang rumah), samping kanan, kiri, dan ‘ngarepan‘ (depan rumah). Bahkan ada juga yang memiliki 5 pintu atau lebih. Hal ini menjadi penanda bahwa ‘pawon‘, merupakan bagian rumah yang paling responsif. Menjadi ruang yang paling sering dikunjungi daripada bagian rumah yang lain.

Di Gunungkidul, perubahan bentuk bangunan rumah dari model tradisional (limasan, kampung) menjadi bentuk modern minimalis mulai merebak. Hal ini turut merubah tatanan bentuk tata ruang ‘pawon‘. Umumnya, desain rumah modern, mulai meninggalkan ‘pawon‘, beralih menjadi dapur (dengan kompor gas).
Dapur memiliki ruang yang lebih sempit dan lebih bersih (karena tidak ada jelaga dan abu bekas pembakaran kayu). Menariknya, walaupun sudah punya dapur, banyak masyarakat Gunungkidul yang tetap membuat pawon dadakan di samping-samping rumahnya. Biasanya berbentuk bangunan-bangunan semi permanen. Entah dari ‘gedhek‘ (anyaman bambu), atau dari triplek. Nyempil di sekitar rumah modernnya.
Fenomena ini bisa diartikan bahwa ikatan masyarakat Gunungkidul dengan ‘pawon‘, belum bisa terlepas. Walaupun sudah ada kompor gas elpiji yang konon lebih mudah dan bersih, ‘pawon‘ masih menjadi ruang yang dibutuhkan oleh masyarakat Gunungkidul. Memasak menggunakan ‘pawon‘, kayu bakar dan hal-hal organik lainnya, sebetulnya jauh lebih ekonomis daripada menggunakan kompor gas, walau memang terkesan tidak praktis. Dengan mempertahankan ‘pawon‘ warga tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli gas, cukup mencari kayu di sekitar rumah, kebonan (kebun) atau ladang. Adanya pawon, juga membuat warga Gunungkidul bisa meminimalisir kegaduhan isu kelangkaan gas elpiji yang kerap terjadi.
PAWON SEBAGAI RUANG KOMUNAL
Jika menilik rumah tradisional Gunungkidul, tidak ada desain ruang makan (dinning room) seperti di rumah-rumah tipe orang barat. Makan bersama (skala keluarga penghuni) biasanya dilakukan di ‘pawon‘, menggunakan dingklik (kursi kecil dari kayu). Kadang-kadang juga ngebrok (tidak menggunakan alas duduk). ‘Rolasan‘ sebutan yang sering digunakan warga Gunungkidul untuk menyebut aktivitas makan siang. Jika ada aktivitas atau pekerjaan di ‘ngalas‘ (sawah atau ladang), ‘rolasan‘ akan dilakukan di sana. “Simbok ngirim nang ngalas” (simbok membawa makanan ke ladang) dengan beragam makanan yang dimasak di ‘pawon‘ untuk dimakan bersama-sama.

Jika tidak ada aktivitas di sawah, rolasan biasanya dilakukan di ‘pawon‘. Saya jadi ingat momen-momen pulang sekolah, menunggu ‘jangan sem dhele‘ (sayur asem kedelai) yang dibuat simbah mateng, saya lantas bermain pasar-pasaran di ‘pawon‘. Jika waktu ‘rolasan‘ tiba dan makanan sudah mateng, simbah akan buru-buru mengajak makan. Proses makan pun dilakukan di ‘pawon‘, sambil bercerita ngalor-ngidul.
Kadang-kadang, ketika mendekati waktu ‘rolasan‘, ada tetangga yang berkunjung ke rumah, melalui pintu belakang. Tak jarang mereka membawa ‘lawuh‘ (lauk) dari rumahnya untuk ditukar dengan ‘jangan‘ (sayur) yang dimasak simbah. Proses bertukar makanan, dari ‘pawon‘ ke ‘pawon‘ ini sangat lumrah terjadi di Gunungkidul.
Para tetangga yang datang ke rumah, akan langsung menuju pawon, bukan ruang tamu. Proses pertukaran makanan yang terjadi di pawon, kadangkala tidak hanya sekedar ingin bertukar makanan. Terkadang ada misi tertentu yang dibawa si pembawa makanan, misalnya, ingin meminjam suatu barang yang kita miliki. Atau sebagai sarana menanyakan kabar, atau sekedar ingin ‘rasan-rasan‘ membahas suatu hal yang sedang hangat. Fenomena ini pernah masuk dalam segmen series Korea berjudul Reply 1988. Bagaimana dapur menjadi ruang komunal.

Selain merangkap ruang makan, ‘pawon‘ biasanya juga sebagai ruang keluarga. Beberapa hal penting dibahas di ‘pawon‘. Diskusi antara anak dengan orang tua, suami dengan istri, atau dengan kerabat keluarga dekat yang lain. Membeli hewan ternak, tanah, menjual kayu, bahkan sampai ‘rembugan wigati‘ menikahkan anak. Ruang ‘pawon‘ juga sering digunakan membahas persoalan keluarga besar, soal warisan, mendamaikan ‘padudon‘ (pertengkaran) antar kerabat dan lain-lain. Semua masalah skala keluarga, akan dilebur bersama ‘angus-angus‘ (jelaga) ‘pawon‘.
PAWON DAN PERALATANNYA
Berbicara ‘pawon‘ memang tidak terlepas dari segala peralatan di dalamnya. Salah satu alat yang menjadi identitas pawon adalah perapian/tungku yang menggunakan bahan-bahan organik seperti kayu, sepet (sabut kelapa), dan areng (arang). Jenis tungku tradisional yang ada di Gunungkidul yang masih mudah ditemui diantaranya ‘pawon‘, ‘keren‘ dan ‘anglo‘. Beberapa Jenis dan bentuknya beraneka ragam, beda kecamatan bisa beda bentuk dan nama, namun memiliki fungsi yang sama, maupun sebaliknya.

Salah satu contohnya adalah bentuk ‘pawon‘ di daerah Wonosari, Karangmojo, Playen, Paliyan, bentuk umumnya memanjang, posisi ‘bolongan luweng‘ (lubang tungku) berjajar ke belakang. Bisa dua atau tiga luweng, namun posisinya memanjang. Sedangkan di Kecamatan Rongkop, spesifik di Dusun Siyono, Petir, Rongkop bentuk bolongan pawon menyamping. Lubang kayu berada di tengah-tengah, bukan di ujung.
Selain tungku, ada beragam peralatan dapur lain yang juga sangat khas berada di pawon Gunungkidul. Ini adalah beberapa peralatan dapur yang umum ada di ruang ‘pawon‘ Gunungkidul.
-
Salang
Jika datang ke ‘pawon‘ tradisional Gunungkidul, salah satu peralatan dapur yang selalu ada adalah salang. Umumnya salang terbuat dari tali dadung (tali dari sabut kelapa), yang dibuat menjulur dan digantungkan pada tiang genteng atau ‘usuk‘ bangunan ‘pawon‘. Fungsi salang selain untuk menyimpan makanan agar tidak diambil kucing atau semut, ia juga berfungsi sebagai alat pengawet makanan.

Sebelum adanya kulkas, berbagai makanan yang mudah sayup (basi) seperti nasi, lauk pauk akan diletakkan di salang. Karena posisi salang berada di ketinggian, karena udara lebih bebas keluar masuk. Sehingga membuat beberapa makanan jadi lebih awet, karena lebih sejuk.
-
Genthong

Jangan bayangkan pawon tradisional ada wastafel atau pantry. Perihal perairan, pawon jaman dulu tidak menggunakan kran untuk mengambil air. Tapi masih menggunakan genthong. Genthong berfungsi sebagai tandon air (penyimpan air) yang umumnya terbuat dari tanah liat atau gerabah. Genthong biasanya dilengkapi dengan ‘siwur‘ (gayung) yang terbuat dari bathok kelapa dan kayu. Untuk genthong sendiri saat ini mulai banyak ditinggalkan, penyimpan air mulai beralih menggunakan ember plastik maupun langsung menggunakan kran. Padahal jika dibandingkan, air yang disimpan menggunakan gentong rasanya jauh lebih segar dan enak.
-
Babrakkan
Peralatan dapur lain yang sering nongkrong di pawon adalah ‘babrakan‘. Bentuk babrakan umumnya seperti ‘dipan‘ (seperti tempat tidur, tapi luas dan pendek). Ia terbuat dari percampuran kayu keras dengan bambu. Fungsi ‘babrakan‘, yang sejauh ini saya ketahui digunakan sebagai tempat berbagai ‘bumbon‘ (segala bumbu), dan sebagai tempat untuk meraciknya.

Selain itu juga sering digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan dapur yang ukurannya agak besar. Menurut saya, kenapa akhirnya dinamakan ‘babrakan‘ karena memang digunakan untuk menaruh berbagai ‘abrak-abrakan‘ (berbagai jenis barang). Baik bumbon, panci-panci dan yang lainnya. Bentuk babrakan juga ada yang dilengkapi dengan rak gelas dan piring di bagian sampingnya.
-
Pagan
Kalau dapur modern hari ini sedang tren beragam home dekor seperti rak-rak dan lemari yang memiliki fungsi khusus untuk menyimpan berbagai peralatan dapur. Pawon tradisional juga memiliki sistem penyimpanan peralatan khusus. Salah satunya adalah ‘pagan‘.

Pagan terbuat dari kayu yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai peralatan dapur yang berukuran besar. Seperti kukusan, dandang, soblok, dan alat-alat berukuran besar lainnya. Pagan biasanya dibuat dalam posisi agak tinggi dan mepet dengan dinding ‘gedhek‘.
-
Plakan

Selain pagan sebagai tempat berbagai peralatan yang berukuran besar, juga ada ‘plakan‘ yang berfungsi sebagai tempat wajan dan berbagai panci yang ukurannya lebih kecil.
-
Paga
Pawon selain berfungsi sebagai dapur, juga berfungsi sebagai ruang penyimpanan berbagai benih dan hasil tani. Sebelum ada toko pertanian dan toko benih, masyarakat Gunungkidul, memiliki manajemen penyimpanan benih sendiri di rumah. Salah satunya menggunakan paga, yang terletak di atas pawon (tungku perapian). Paga biasanya digunakan untuk menyimpan jagung, bawang merah, bawang putih, dll. Pawon akan nampak ‘pating crantel‘ (bergelantungan) dengan beragam hasil tani tersebut.

Penyimpanan hasil tani menggunakan paga adalah kearifan lokal yang saat ini pun mulai ditinggalkan. Memilih paga sebagai penyimpanan, bertujuan agar jagung atau hasil panen lain bisa lebih awet (tidak bubuken) karena kepulan asap rutin dari pawon yang menjaga paga terus kering dan aman dari berbagai hewan/serangga.
Perabotan lain yang berukuran lebih kecil selalu ada di pawon adalah munthu (ulekan), cowek (cobek), irus (alat untuk mengambil kuah), cething (tempat nasi), kendhi (wadah air minum), enthong (centong nasi), ketel (pemasak nasi), ceret (pemasak air), tampah, tenggok, sendok, sendok porok (garpu), dhingklik (kursi lantai), ladhing (pisau), pengot (pembelah kelapa), termos (tempat air panas), suthil (spatula), serok, lampin (lap) dll.
PAWON DAN PEREMPUAN
Dalam konteks lain masyarakat Jawa, pawon sering diidentikkan sebagai kawasan teritorial perempuan. Bahkan ada istilah ‘masak‘, ‘macak‘, ‘manak‘ (memasak, berdandan dan melahirkan) yang dilekatkan pada diri perempuan. Pada jaman sekarang, pernyataan ini kerapkali dianggap merendahkan dan meremehkan peran perempuan dalam rumah tangga. Seakan-akan wewenang perempuan hanyalah urusan domestik saja. Tidak ada peran lain atau kemampuan untuk suatu hal yang bersifat umum.
Padahal sebetulnya, seperti ulasan diatas, ruang teritori perempuan berupa ‘pawon‘ memiliki peranan sangat vital dalam tataran rumah tangga. Dapat dipahami bahwa, perempuan justru memegang peranan yang sangat penting dan mempunyai otoritas penuh atas teritorinya. Di Gunungkidul, ada istilah ‘cupar‘ (ora ilok) jika laki-laki berada di dapur, atau ikut campur urusan dapur. Munculnya ungkapan ‘cupar‘ bisa diartikan sebagai sebuah pagar pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Pemaknaan yang terlalu dangkal justru sering membuat kesan bahwa perempuan hanya berperan di ranah domestik atau remeh-temeh saja.

Realitas yang terjadi pada rumah tangga petani di Gunungkidul, mayoritas perempuan memang menguasai dari ladang hingga ‘pawon‘. Perempuan dalam kesehariannya, ikut berperan menggarap ladang, memasak untuk keluarga, mengurus anak, hingga mengurus hewan ternak. Sedangkan para laki-laki bertugas mencari uang dan melakukan pekerjaan yang berat secara fisik. Pembagian tugas seperti ini sudah menjadi pemandangan yang biasa terjadi di Gunungkidul.
Pekerjaan dari ladang ke pawon dan meja makan tentu saja bukan hal yang remeh-temeh. Ada banyak pengetahuan di dalamnya, dari mulai merawat tanah hingga mengolah hasilnya menjadi makanan. Pawon kerapkali menjelma menjadi laboratorium, mengolah beragam sumber daya menjadi beragam sumber gizi bagi keluarga.
Di zaman modern perihal ‘pawon‘ yang kerapkali menjadi alasan diskriminasi gender, seharusnya sudah ditinggalkan jauh-jauh. Subordinasi ‘pawon‘ sebagai sebatas ruang untuk ukuran membatasi peran perempuan seharusnya tak lagi relevan. ‘Pawon‘ dalam tatanan ruang adalah nadi dan jantung. “Sik penting pawone isa ngebul” menjadi ungkapan yang pas untuk menggambarkan krusialnya pawon dan ‘empunya teritori’.

Saya bersepakat bagian rumah yang paling dirindukan ketika pergi dari rumah adalah dapur. Ruang yang hangat karena perapiannya dan momen bersama ibu, di dalamnya. Gambaran terkait romantisme dapur dan ibu mengingatkan saya pada puisi Mas Aan Mansyur.
“Aku ingin pulang ke dapur ibuku,
Melihatnya sepanjang hari tidak berbicara,
Aku ingin menghirup seluruh kebahagiaannya yang menebal menjadi aroma yang selalu membuat anak kecil dalam diriku kelaparan.
Aku ingin diam dan hidup bersama ibuku.
Aku akan menyaksikan ia memetik sayur dalam kebun kecilnya”Sepenggal Puisi “Pulang Ke Dapur Ibu” oleh M. Aan Mansyur