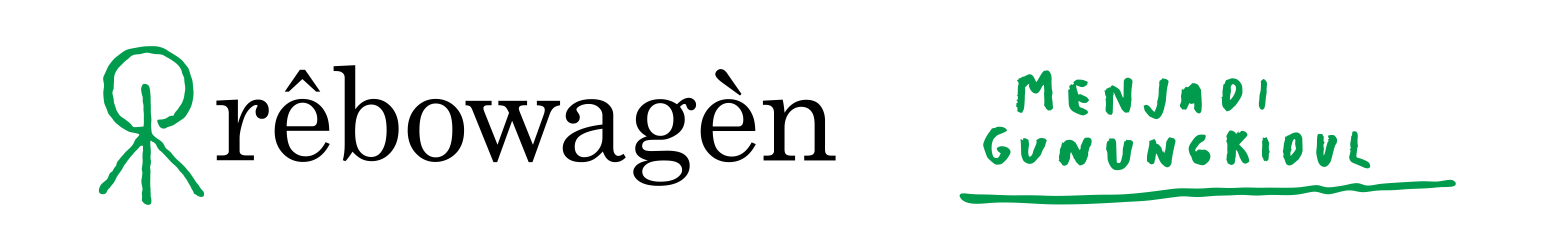Sejarah(rebowagen.com) — Hari beranjak siang. Terik matahari mulai sedikit terasa menyengat kulit. Saya masih duduk di lantai pendapa yang berada di atas tebing pantai Ngungap. Bekas pendapa lebih tepatnya. Bangunan ini hanya menyisakan sedikit atap, tiang dan lantai. Hampir seluruhnya telah rusak dimakan waktu Sisa kopi setelah subuh tadi tinggal menyisakan ampas. Meski begitu tetap saya seruput kembali kendati hanya sedikit air yang tersisa, tercampur butir-butir halus kopi yang rasanya telah hambar. Untuk kesekian kalinya saya kembali menyulut rokok. Tidak tahu lagi sudah berapa puluh batang aku bakar. Angan-angan tentang Junghuhn yang sempat saya rasakan tadi pagi masih berkelindan dalam benak saya.
Dua orang teman yang kebetulan ikut menemani, mengisi waktu dengan membersihkan pecahan-pecahan genting yang berserakan di lantai. Kami mengobrol ‘ngalor ngidul’ sambil menunggu teman-teman Karang Taruna dan Resan Gunungkidul yang hari ini mengagendakan penanaman pohon di tebing pantai Ngungap.
Sengaja kami datang lebih awal. Sempat kesasar, karena jalan-jalan sudah berubah akibat pembangunan JJLS. Sebelum subuh akhirnya kami bisa sampai di lokasi. Tepat ketika ufuk timur mulai semburat menguning.
Dari beberapa literasi dan gambaran yang saya tangkap tentang lukisan Junghuhn, saya simpulkan sendiri bahwa ia melukis tebing pantai Ngungap di waktu pagi hari. Momen ini yang ingin saya tangkap agar bisa ikut merasakan getaran alam Gunungkidul yang dirasakan Junghuhn 156 tahun yang lalu.

Friedrich Franz Wilhelm Junghuhn adalah seorang naturalis, doktor, botanikus, geolog dan pengarang berkebangsaan Jerman. Junghuhn melakukan ekspedisi penelitian di pulau Jawa dan Sumatera dari sudut pandang ilmu bumi, geologi, vulkanologi dan botani. Ilmuwan kelahiran Mansfeld, Jerman 26 Oktober 1809 ini banyak melakukan studi botani dan geologi di wilayah Hindia Belanda. Ia meninggal di Lembang, Bandung pada tanggal 26 April 1864. Delapan tahun setelah ia mengunjungi Gunungkidul pada 1856.
Hasil penelitian tentang alam pulau Jawa ia tuangkan dalam sebuah buku utama yakni Pulau Jawa – Bentuknya, Permukaanya dan Susunan Dalam. Buku ini terdiri dari tiga jilid yang ia tulis dalam rentang waktu tahun 1852-1854. Dan dilengkapi dengan peta pertama dari pulau Jawa yang cukup terperinci. Junghuhn juga menyusun sebuah Herbarium, singkatan utama ilmiahnya adalah Jungh. Herbarium ini dikenal sebagai sebuah upaya melestarikan pohon Cinchona (kina) sebagai bahan baku obat Kinina (anti malaria).
Tak banyak yang berubah dari lanskap pantai Ngungap saat ini dibanding lukisan Junghun satu setengah abad yang lalu. Ngungap adalah tebing pantai tanpa pasir putih. Garis daratan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia ini berupa tebing-tebing batu setinggi puluhan meter. Bongkahan batu-batu karang tajam tampak berada di bawah tebing. Sebagian menjadi batu mandi yang terus diukir oleh ombak yang terus berdebur sepanjang masa. Selepas mata memandang ke selatan, warna biru Samudera Hindia melengkung dengan garis horizon langit.
Pagi tadi, sebelum matahari muncul di ufuk timur, saya mencoba memposisikan diri di tempat kira-kira Junghuhn mengambil tempat untuk melukis. Pohon di lukisan yang sepertinya jenis beringin (karena ada akar sulurnya) memang sudah tidak ada. Tapi pohon pandan masih tersisa. Tebing batu tinggi disebelah kiri lukisan masih terbaca dengan jelas. Lanskap bukit-bukit sebelah timur juga tak banyak berubah. Yang paling mencolok adalah bukit lancip dan dataran rumput di belakangnya. Masih sangat mirip dengan lukisan Junghuhn. Fitur alam yang direkam tidak banyak berubah setelah lebih dari satu setengah abad.

Lama saya terdiam dan mencoba membayangkan aktivitas beberapa orang dalam lukisan. Ada potongan bambu dan tali yang juga terekam, tentu ini terkait dengan upaya memanen sarang burung walet. Terdapat empat sosok manusia di dalam lukisan. Dua berpakaian putih, memakai topi semacam ‘laken’ yang sangat identik dengan tuan Meneer Belanda. Dan dua lagi hanya memakai celana hitam tanpa baju, ini tentu pengiring warga pribumi yang menyertai Junghuhn. Salah satu pribumi tampak dalam posisi tengkurap. Kepalanya menjulur ke bawah tebing, mungkin dia sedang memberi aba-aba kepada beberapa orang lagi yang sudah berada di bawah.
Pagi itu sangat hening. Disela suara camar dan debur ombak yang terdengar jauh dan lirih, dalam benak saya seperti berkumandang kembali lagi suara-suara. Teriakan ataupun perintah dari sang Meneer kepada para pengunduh sarang walet yang tengah berjibaku mengambil liur burung yang dikenal sangat berharga. Atau dialog antar pengunduh yang saya bayangkan sedang bergelantungan di atas ombak dan batu karang tajam. Menyerahkan keselamatan nyawanya pada seutas tali.
Lipatan waktu dari masa satu setengah abad yang lalu tampaknya sedikit terbuka dan mengirimkan pesan-pesan itu dalam otak dan benak saya. Beberapa saat kemudian, saya bisa menyimpulkan bahwa momen dari sisi inilah yang direkam oleh Junghuhn lewat lukisan yang ia beri judul Sudkuste Ostwarts Von Rongkop.
Sarang Walet dan destinasi wisata
Tebing pantai Ngungap berada di wilayah Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo. Sebelum ada pemekaran kapanewon/kecamatan, pantai Ngungap berada di wilayah Kecamatan Rongkop. Dari cerita tutur masyarakat, asal nama ‘ngungap’ adalah ‘kembangan’ dari kata ‘ngungak’ atau melongok. Hal ini mungkin terkait dengan keadaan tebing pantai, dimana setiap orang yang ingin melihat ke bawah harus ‘melongok’.

Pantai Ngungap memang tergolong masih alami. Bangunan permanen hanya sebuah pendapa yang telah rusak parah. Pendapa ini dibangun oleh Pemkab Gunungkidul sebagai sarana upacara adat Nyadran/Sedekah Laut. Ritual adat ini erat kaitannya dengan acara memanen sarang burung Walet ( Aerodramus Maximus) yang dilaksanakan rutin dalam periode tertentu.
Saya teringat cerita seorang teman bernama Mbah Mahmudi. Ia adalah seorang veteran pengunduh sarang burung Walet di wilayah Gunungkidul. Mbah Mudi pernah bercerita bahwa dia dan teman-temannya pernah turun di tebing pantai Ngungap.
“Di dalam tebing ada semacam gua besar, sarang walet menempel di dinding-dinding gua. Untuk masuk ke dalam harus sangat hati hati. Waktunya harus pas karena berebutan dengan ombak yang datang,” cerita Mbah Mudi beberapa waktu lalu.
Sarang burung walet berasal dari air liur sang burung itu sendiri. Sarang dari liur ini bisa dikonsumsi dan dipercaya bermanfaat untuk kesehatan dan pengobatan. Tak heran harganya menjadi tinggi. Karena menjadi sebuah komoditas berharga, pengunduhan sarang yang seharusnya dilakukan dalam periode waktu tertentu menjadi tak terkendali. Banyak kasus pencurian sarang burung walet sehingga akhirnya berimbas pada kelestariannya.
“Sarang yang bisa diambil adalah sarang yang sudah tidak dipakai. Kalau masih dipakai bertelur atau menetas dipanen, maka anak-anak walet akan mati dan induknya akan pergi mencari tempat lain yang aman,” lanjut Mbah Mudi.
Lurah Kalurahan Pucung, Estu Dwiyono yang ikut agenda penanaman pohon mengakui bahwa pantai Ngungap saat ini memang masih sepi dan belum difungsikan sebagai destinasi wisata. Keberadaannya juga kalah tenar dengan pantai-pantai lain yang sudah lebih dulu bersolek di Gunungkidul.
“Pendapa ini dibangun oleh Pemkab Gunungkidul. Dahulu setiap periode waktu tertentu usaha panen walet yang dikelola pemerintah daerah masih sering dilakukan. Tapi selepas tahun 97/98 sudah semakin jarang dilakukan. Meski setelahnya sempat dilanjutkan orang-orang yang sempat ikut mengelola, tapi karena hasilnya minim maka sekarang sudah tidak lagi dilakukan,” terang dia.

Menurutnya, pihak desa belum lama ini telah melakukan upaya koordinasi dengan Pemkab terkait pemanfaatan pantai. Sebab dahulu memang tidak diperkenankan untuk kunjungan wisatawan karena digunakan untuk kegiatan usaha sarang burung walet.
Fajar Risdiyan, salah seorang tokoh Karang Taruna menyatakan harapan bahwa pantai Ngungap dan Gunung Gandul bisa dibuka menjadi destinasi wisata. Dalam bayangannya, upaya ini dilakukan oleh warga masyarakat bukan oleh investor. Ketika pelaku wisata adalah masyarakat, tentu nantinya akan berimbas pada kemajuan ekonomi warga lokal.
“Jangan sampai ketika investor yang mengembangkan, warga sekitar hanya jadi penonton atau pekerja kasar, kita hanya kebagian remah-remahnya,” kata Fajar.
Ia sendiri adalah warga Kalurahan Tileng. Sementara Pantai Ngungap masuk dalam wilayah Kalurahan Pucung. Tapi tebing pantai Gunung Gandul yang bersebelahan dengan Ngungap berada dalam wilayah Kalurahan Tileng.

“Tebing Gunung Gandul juga sangat indah, jika ada koordinasi antara dua desa, Tileng dan Pucung, tentu akan ada bentuk kerjasama pengelolaan, tapi sekali lagi ini harus melibatkan masyarakat lokal dua desa,” imbuh Fajar bersemangat.
Kekhawatiran Fajar memang sangat beralasan. Sangat mungkin hal ini juga mulai dirasakan masyarakat Gunungkidul secara umum. Gencarnya investor yang masuk ke Gunungkidul memang menjadi fenomena tersendiri saat ini. Jika dalam prosesnya tidak atau kurang mengakomodir warga lokal maka dapat dipastikan akan terjadi kesenjangan. Banyak contoh kawasan pantai saat ini yang arahnya sudah privatisasi. Banyak pula destinasi wisata favorit di Gunungkidul dimana warga lokal hanya kebagian pekerjaan yang remeh-temeh. Bahkan yang lebih parah hanya menjadi penonton kemacetan kendaraan wisatawan.
Apa yang dirasakan oleh Junghuhn lebih dari satu setengah abad yang lalu dan diabadikannya dalam karya Sudkuste Ostwarts Von Rongkop bisa menjadi sebuah gambaran. Bagaimana seseorang yang notabene bukan pribumi begitu sangat terkesan dengan alam Gunungkidul yang luar biasa.
Sambil menanam satu bibit pohon Nyamplung di tempat yang saya perkirakan sebagai lokasi pohon besar di lukisan Junghuhn, tiba-tiba dalam hati saya muncul sebuah pertanyaan. Saat ini, sebagai generasi modern Gunungkidul, bisakah kita mempertahankan surga Gunung Sewu? atau justru kita malah mulai kehilangan?