Sejarah(rebowagen.com)– Di Kapanewon Ponjong, setidaknya ada tiga Tugu Jumenengan yang saat ini masih berdiri kokoh. Yakni di pertigaan Pasar Ponjong, Padukuhan Kerjo I, dan di Padukuhan Kerjo II, Kalurahan Genjahan atau sebelah barat Proliman Ponjong. Dari ketiga tugu tersebut, tugu yang ada di sebelah barat Proliman Ponjong yang pertama kali dibangun dan sampai saat ini bentuknya masih asli atau belum dilakukan pemugaran.
Tugu Jumenengan adalah tugu ‘pengetan‘ (peringatan) yang dibangun di Gunungkidul sebagai tanda sejarah saat penobatan Sri Sultan Hamengkubuwana IX. Pangeran yang mempunyai nama kecil Gusti Raden Mas Dorodjatun ini naik tahta menjadi raja di Kasultanan Yogyakarta.
Penobatan GRM Dorodjatun dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1940. Bagi masyarakat, pembangunan Tugu Jumenengan ini, tidak hanya sebagai penanda atau pengingat dikukuhkannya Sri Sultan HB IX sebagai raja. Tetapi tugu ini juga sebagai simbol kebahagiaan masyarakat DIY menyambut pemimpin baru mereka.

Di balik kokoh dan gagahnya Tugu Jumenengan di Kapanewon Ponjong, menyimpan makna penting bagi masyarakat Gunungkidul. Untuk itu, Senin (01/08/2022), saya memutuskan untuk bertemu dengan salah seorang sesepuh di Padukuhan Kerjo II sekaligus mantan carik Kelurahan Genjahan, Sukar (90). Dengan didampingi Kepala Dukuh Pati, Haryadi (51), motor saya melaju pelan menuju rumah pria yang akrab disapa Mbah Sukar tersebut.
Mengenal masa kecil hingga remaja GRM Dorodjatun
Dibahas di awal, Tugu Jumenengan yang ada di Kapanewon Ponjong tersebut tidak lepas dari sejarah penobatan Sri Sultan HB IX. Menurut penuturan Mbah Sukar, tugu tersebut dibangun oleh pihak keraton dan dibantu oleh warga sekitar.
“Iya, pembangunan tugu itu sebagai penanda atau peringatan saat Gusti Raden Mas Dorodjatun atau Sultan HB IX naik tahta sebagai raja di Kasultanan Yogyakarta. Tugu itu dibangun pihak keraton dan dibantu warga sekitar,” tutur Mbah Sukar.

Melansir dari kratonjogja.id, Sultan HB IX memiliki nama kecil Gusti Raden Mas (GRM) Dorodjatun. Lahir pada tanggal 12 April 1912 dan wafat pada tanggal 2 Oktober 1988 pada usia 76 tahun. GRM Dorodjatun adalah anak ke-9 Sri Sultan Hamengkubuwana VIII dari istri kelimanya, Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Ratu Alit.
Sejak kecil, GRM Dorodjatun dititipkan di rumah seorang kepala sekolah Neuteale Hollands Javanesche Jongen School (NHJJS) asal Belanda bernama Mulder. Sultan VIII berpesan kepada kepala sekolah NHJJS ini agar anaknya dididik layaknya masyarakat biasa. Selain itu, Sultan VIII juga meminta agar anaknya bisa hidup mandiri tanpa didampingi pengasuh.
GRM Dorodjatun menjalani masa-masa sekolah di Yogyakarta, mulai dari Frobel School (taman kanak-kanak), lalu ke Earste Europe Lagere School B, lalu pindah ke Neutrale Europese Lagere School. Setelah lulus dari pendidikan dasar, Dorodjatun melanjutkan pendidikan ke Hogere Burgerschool (HBS) di Bandung dan Semarang.
Belum selesai sekolah di HBS, Dorojatun diminta oleh ayahnya untuk pergi ke Belanda di rumah saudaranya. Di Belanda, ia menyelesaikan Gymnasium, kemudian melanjutkan sekolah di Rijkunversitet di Leiden. Di tempat ini, ia banyak belajar tentang hukum tata negara serta aktif mengikuti klub debat yang dipimpin oleh Profesor Schrieke.
Saat Gusti Raden Mas Dorodjatun sedang menempuh pendidikan di Belanda, tiba-tiba ayahnya, Sri Sultan HB VIII, pada tahun 1939 meminta agar ia pulang ke tanah air. Tak pelak, Dorodjatun beserta saudaranya yang ada di Belanda pun kaget. Sebab, ia tengah giat belajar tentang hukum tata negara dan aktif di klub debat.
Rupanya, Sri Sultan VIII meminta anaknya untuk segara pulang ke tanah air lantaran saat itu Perang Dunia II meletus. Hal ini yang kemudian membuatnya merasa khawatir akan kondisi anaknya. Mengingat situasi cukup gawat, akhirnya Dorodjatun memenuhi keinginan ayahnya dan kembali ke tanah air.
GRM Dorodjatun naik tahta
Dalam buku Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, Mohammad Roem mengungkapkan, bahwa Sri Sultan VIII memang merasakan firasat bahwa hidupnya tidak lama lagi.

Benar saja, saat itu Sri Sultan VIII jatuh sakit dan meminta anggota keluarganya, termasuk Dorodjatun, hadir di kamarnya. Setelah itu, Sri Sultan VIII menyerahkan keris pusaka “Kyai Jaka Piturun” sebagai tanda sang raja menginginkan anaknya untuk menggantikannya.
Tak lama setelah menyerahkan keris pusaka tersebut, tepat pada 22 Oktober 1939, Sri Sultan VIII wafat. Saat itu, Dorodjatun menjadi salah seorang calon penerus yang kuat sebagai raja Yogyakarta. Namun, menyadari kemampuannya tentang Yogyakarta yang masih terbatas, Dorojatun mengumpulkan sanak saudara dari keluarga Sultan HB VII dan HB IX.
Pembangunan dan Makna Tugu Jumenengan di Ponjong
Upacara penobatan Sri Sultan Hamengkubuwana IXj menjadi raja di Kasultanan Yogyakarta pada 18 Maret 1940 dihadiri oleh para bangsawan dan juga pejabat keraton. Keesokan harinya, diadakan kirab agung mengelilingi kota yang diikuti oleh prajurit keraton beserta para abdi dalem. Sementara itu, di luar keraton juga banyak masyarakat Yogyakarta yang menyaksikan prosesi kirab agung ini.

Banyaknya masyarakat yang melihat kirab agung ini juga sebagai tanda bahwa warga Yogyakarta menyambut dengan sukacita atas penobatan Sri Sultan Hamengkubuwana IX. Rasa sukacita ini juga diungkapkan oleh masyarakat Yogyakarta, khususnya Gunungkidul, dengan pembangunan Tugu Jumenengan.
“Tugu ini dibangun oleh pihak keraton yang dibantu warga sekitar sebagai ‘pengetan’ (peringatan) serta ungkapan sukacita atas pengangkatan Sri Sultan HB IX sebagai raja Kesultanan Yogyakarta. Pembangunan tugu ini juga dilakukan di beberapa wilayah di DIY, salah satunya di sini (Padukuhan Kerjo II),” terang Mbah Sukar.
“Dulu, pihak keraton memerintahkan untuk membuat Tugu Jumenengan di antara Gunung Merapi dan laut selatan. Mungkin, titik tengah di wilayah Gunungkidul di tempat ini,”
imbuhnya lagi.
Di beberapa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memang terdapat Tugu Jumenengan dengan bentuk yang berbeda-beda. Di Gunungkidul sendiri, tugu berwarna putih ini memiliki tinggi bangunan sekitar 3,1 meter dengan lebar 1 meter. Tugu ini memiliki beberapa trap dan di bagian tengah terdapat tulisan huruf Jawa serta huruf balok dengan bahasa Jawa. Yang mana satu sisi tertulis sengkalan “Tanwinarno Troestaning Para Kawoela 1940” dan sisi yang lain “Sri Narendra Soeka Basoeki Kawoela 1871”.
Tulisan yang ada di Tugu Jumenengan ini disebut sebagai sengkalan. Dikutip dari budaya.jogjaprov.go.id, sengkalan merupakan kata berupa kalimat atau bukan kalimat yang mengandung angka tahun. Disusun dengan menyebut lebih dahulu angka satuan, puluhan, ratusan, kemudian ribuan. Selain sebagai simbol, angka tahun juga merupakan sebuah konsep magis tradisional dalam kepercayaan masyarakat.

Dalam bahasa Jawa, sengkalan dibaca dari belakang. Sebagai contoh, Sri Narendra/ratu (1), Soeka/bahagia (7), Basuki/selamat (8), Kawula/rakyat (1). Sengkalan tugu ini berfungsi sebagai tetenger (penanda) penobatan Sri Sultan HB IX naik tahta. Selain itu, angka tersebut memiliki makna kegembiraan rakyat atas penobatan Sri Sultan HB IX menjadi raja di Kasultanan Yogyakarta.
Sementara, di bagian puncak tugu, terdapat sebuah mahkota berwarna kuning emas. Mahkota ini sebagai simbol kekuasaan Sri Sultan HB IX yang memimpin warga Yogyakarta dan selalu bercermin di kalbu rakyat. Selain itu, mahkota ini juga sebagai penanda bahwa sang raja berdiri kokoh untuk mengayomi rakyatnya.

Melihat arti pentingnya tanda sejarah ini, Tugu Jumenengan di Gunungkidul adalah sebuah warisan budaya yang harus tetap dijaga dan dipelihara. Sebab, di balik kokohnya tugu ini menyimpan nilai-nilai sejarah panjang Kabupaten Gunungkidul yang menjadi bagian dari wilayah Kasultanan Yogyakarta.
Maka dari itu, sudah sepantasnya masyarakat Yogyakarta, khususnya warga Gunungkidul untuk selalu belajar dari sejarah masa lalu sebagai bekal untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Hal sebagaimana sabda Sri Sultan HB IX,
“sak dhuwur-dhuwure sinau kudune dewe tetep wong Jawa, di umpamakne kacang kang ora ninggalke lanjaran, marang bumi sing nglahirke dewe tansah kelingan.”
Sabda ini bisa diterjemahkan “Setinggi-tingginya kita belajar, kita tetaplah orang Jawa. Kita adalah generasi harapan yang akan meneruskan perjuangan leluhur. Dan bumi yang menjadi saksi atas kelahiran kita”.
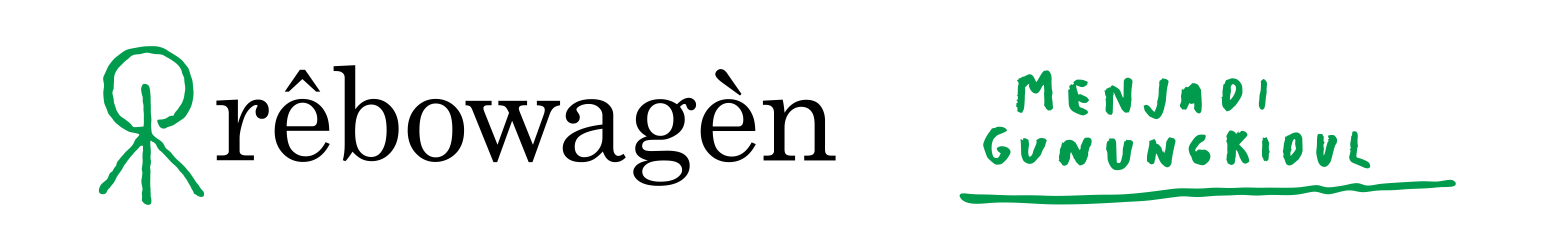
















































Terimakasih ya rebowagen,, akhirnya nemu bacaan informatif dan edukatif ttg sejarah gunungkidul,dan byk lagi yg berkaitan dg nilai-nilai budaya di bumi handayani tercinta.. smoga semakin maju,,dan terus memberikan informasi dan edukasi pd masyarakat…