Budaya(rebowagen.com)– “Semua masalah akan selesai dengan wedangan” begitu kira-kira kalimat Mas Gudel, saat menjadi pembawa acara di Pekan Climen Rebowagen di Sinambi Farm bulan Oktober tahun 2022 lalu.
Sebagai warga Gunungkidul, istilah ‘wedangan‘ sudah menjadi kosakata obrolan sehari-hari. Ajakan wedangan seringkali saya temui saat lewat depan rumah tetangga yang kebetulan berpapasan, atau saat bertemu dengan seseorang yang tengah melakukan wedangan di sawah, teras, ataupun tempat lainnya. Benar bahwa ‘kirata basa‘ ‘wedang’ adalah ‘ngawe kadang‘. Ajakan “ayo wedangan” sering juga hadir lewat undangan antar teman di chat pribadi Ponsel maupun di media sosial.
Saya kira wedangan memang sudah ‘menubuh’ dengan kebiasaan sehari-hari orang Gunungkidul. Bahkan muncul istilah ‘nggathok‘ atau setara dengan kecanduan. “Nek ora wedangan, mumet sirahe” (kalau tidak wedangan, pusing kepala). Mengapa demikian, karena ‘wedangan‘ memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Sudah menjadi budaya turun-temurun yang masih lestari sampai hari ini. Wedangan biasa dilakukan pagi hari sebelum beraktivitas, siang hari, sore hari usai aktivitas atau bahkan malam hari saat berkumpul di gardu ronda atau rumah tetangga.

Wedangan tak hanya berarti ‘ngombe wedang’ atau minum dalam arti sebenarnya. Wedangan yang saya pahami, juga berarti jeda atau leren (istirahat) sejenak dari aktivitas utama. Seperti ‘nyawah‘, ‘negal‘, ‘sambatan‘, ‘rewang‘, dan aktivitas lainnya. Selain itu wedangan juga dimaknai sebagai ajakan untuk ngobrol atau diskusi. Sebuah strategi ajakan yang lebih santai walaupun topik obrolannya berat.
“Wedangan itu cuma bahasa alus aja, ngajak orang bertukar ide, bertukar cerita atau masalah. Masalah minumnya kopi, jus atau susu sekalipun ngga masalah”
ujar Mas Gudel, seorang pemuda domisili Playen, yang kerap mengajak anak-anak muda melestarikan budaya wedangan.
Membicarakan soal wedangan jadi mengingatkan saya pada satu kultur baru hari ini yaitu ‘ngopi’ (ngopi single origin, bukan sachet). Seingat saya dulu, jarang sekali ada istilah ‘ngopi’ di Gunungkidul. Apalagi jumlah warung kopinya, bisa dihitung jari. Kultur ngopi mulai berkembang pesat usai naiknya film Filosofi Kopi sekitar tahun 2015. Pergeseran makna dari ngopi yang hanya minum kopi, menjadi sesuatu yang keren dan berkelas hingga menarik banyak anak muda untuk berprofesi sebagai barista (peracik kopi).
Saya melihat istilah ngopi yang menjamur di masyarakat urban, tidak serta merta masuk ke Gunungkidul dengan mudah. Walaupun hari ini sosial media sangat masif, konten-konten tentang kopi dan coffe shop membanjiri timeline. Namun nampaknya trend istilah ‘ngopi’ di Gunungkidul memang kalah dengan kultur wedangan yang memang sudah menubuh sedari dulu bahkan di kawula muda sekalipun. Saya mengamati, popularitas coffe shop di Gunungkidul masih kalah jauh dengan spot-spot wedangan. Padahal secara estetika (tempat keren hari ini) jelas kalah dengan coffe shop.
Bahkan hari ini saya malah menemukan beberapa kawula muda yang membangun usaha wedangan. Bukan coffe shop, cafe atau pun sejenisnya yang nampak keren. Salah satu yang saya temui adalah Sinambi Wedangan yang diiinisiasi oleh beberapa kawula muda Gunungkidul. Anak-anak muda yang tahun lahirnya bersamaan dengan trend HP Nokia seri 3310, atau sekitar tahun 2000an.

“Wedangan lebih bisa masuk ke semua kalangan” ujar Alif Budiman, salah satu inisiator Sinambi Wedangan.
Sinambi Wedangan terletak di Dusun Sumbermulya, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari. Seluruh pengelolanya adalah anak-anak muda. Saya kerap memperhatikan pelanggan yang berkunjung ke Sinambi Wedangan, mayoritas memang anak-anak muda.
“Aku sendiri lebih nyaman neng tempat wedangan sih mbak daripada coffe shop. Soale lebih nyaman, dan nama menunnya lebih gampang, luwih hangatlah” ujar Alif lagi sambil membetulkan posisi topinya.
Teko blirik, cangkir dan gula batu adalah formasi wedangan pada umumnya. Saya perhatikan ada beberapa merek teh yang familiar digunakan oleh orang Gunungkidul. Ada Teh Wangi Jawa Biru, Jawa Kuning, Goro-goro, Pecut, atau Srimpi. Prosesnya dibacem di teko blirik, selama kurang lebih lima menitan lalu dituang ke dalam cangkir-cangkir kecil yang berisi gula batu. Tingkat kekentalan teh akan disesuaikan dengan selera masing-masing. Ada memang yang menyukai ‘nasgitel‘ (panas, legi, kenthel) biar ada sensasi ‘makpyar‘. Ada juga yang memilih untuk tidak terlalu kental atau rasa tawar saja.

Cara wedangan di Gunungkidul, memiliki beberapa pergeseran. Kalau hari ini menggunakan gula batu atau gula pasir yang dimasukkan ke dalam gelas. Sebelumnya proses wedangan malah menggunakan gula jawa yang digigit terpisah.
“Jaman nom-nomanku wedangan ki nganggo gula jawa. Gula jawane seka daerah Plembutan sak mengidul kana. Gek carane ngombe, disruput sik gek lagi nyokot gula. Segere jan ngejo (zaman saya muda, wedangan itu memakai gula jawa dari daerah Plembutan ke selatan sana. Lalu caranya, setelah menyeruput teh baru menggigit gula jawa, segar rasanya)”
ujar Mbah Ngatiman tetangga saya.
Wedangan bisa lebih lengkap ketika dinikmati dengan ‘pacitan‘, baik bakwan, cemplon, lemet, puli tempe dan lainnya. Tapi kalau pun tidak ada, bukan suatu masalah. Di Gunungkidul ada konsep wedangan ‘kendel‘ atau wedangan tanpa ‘pacitan‘. ‘Kendel‘ adalah kata bahasa Jawa yang memiliki arti berani. Wedangan ‘kendel‘ biasanya dijadikan bahan guyonan “mampir wedangan, ning ya gur wedangan kendel”.

Saya jadi teringat pagi hari sebelum simbah beraktivitas. Tiap pagi selalu ‘godhog banyu‘ (menjerang air) di atas tungku kayu. Menggunakan ceret hitam penuh ‘angus‘. Kontras dengan warna dalam ceret yang putih pekat karena kapur yang menempel. Tak jarang kapur menggumpal mengeras hingga membatu akhirnya menyumpal jalur keluar masuk air dalam ceret. Ini hal yang sangat lumrah terjadi di Gunungkidul. Air bercampur kapur, setelah air ‘kemrengseng‘ dan ‘umub‘ (mendidih), simbah akan buru-buru memasukkannya ke dalam termos. Sisanya, dimasukan ke dalam teko blirik hijau, yang di dalamnya berisi teh. Tak lupa, simbah mengeluarkan beberapa makanan camilan seperti tempe koro bacem atau puli tempe, dan ritual wedangan pun dimulai.
Wedangan, akhirnya seakan menjadi ‘trademark‘ Gunungkidul saat ini. Meski dulu wedangan identik dengan kebiasaan orang-orang tua, saat ini, anak-anak muda tak akan malu mengajak teman-temannya untuk wedangan. Bahkan, untuk pertemuan bisnis atau membahas hal-hal yang penting, wedangan menjadi salah satu alternatif pertemuan non-formal yang mempunyai sensasi berbeda. ‘Kirata basa, ngawe kadang‘, akhirnya menjadikan tradisi wedangan adalah sebuah wahana untuk komunikasi dan negoisasi yang lebih santai dan cair.
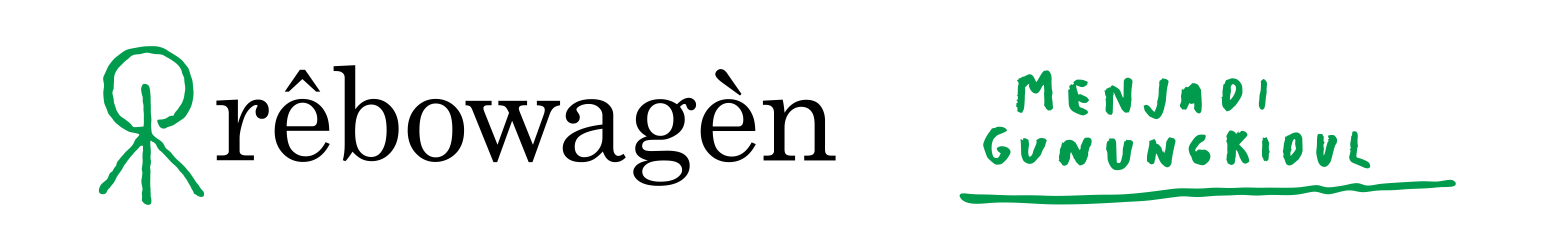













































Welldug, salim seko adoh minnnn🙌🏼