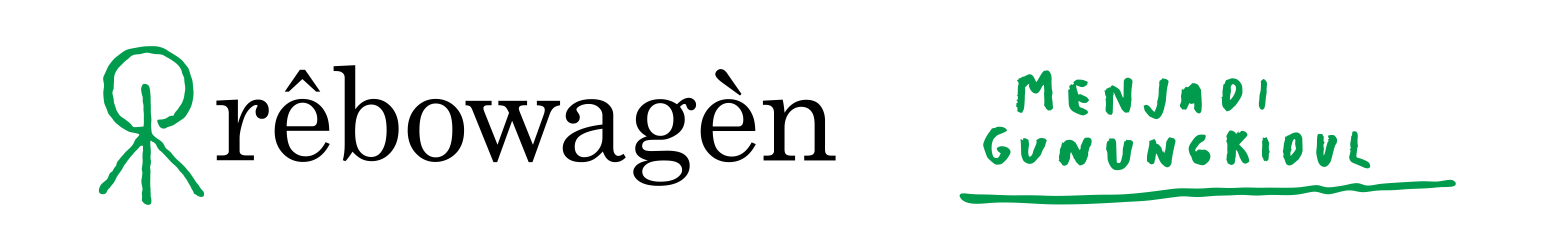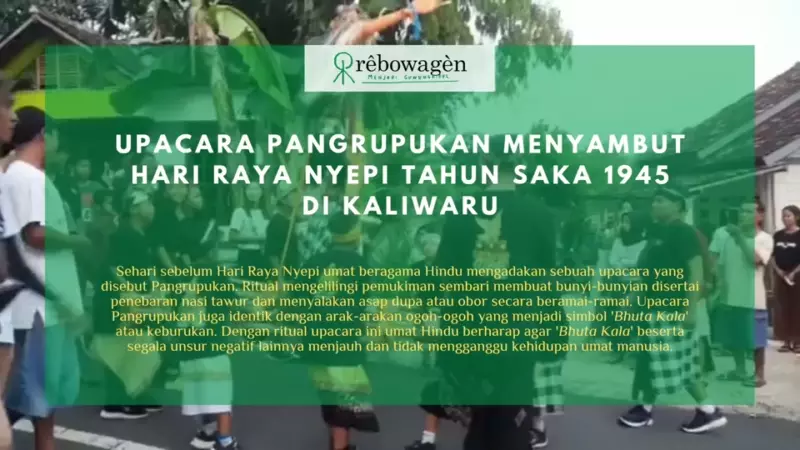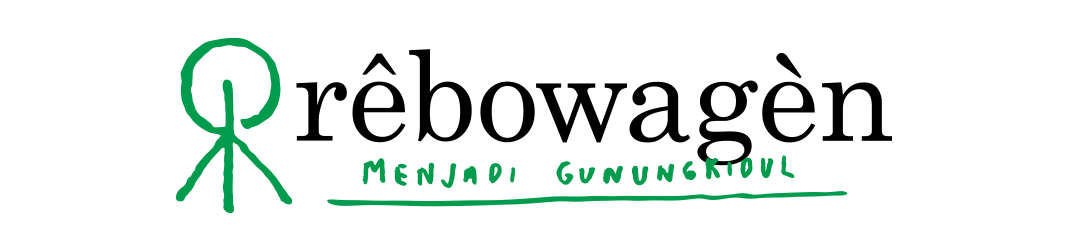Kuliner(rebowagen.com)– Lamtoro atau petai cina (Leucaena leucocephala), orang Gunungkidul lebih sering menyebutnya manding/mlanding. Tumbuhan ini adalah sejenis perdu yang masuk dalam suku kacang-kacangan. Menurut Wikipedia.com manding merupakan tanaman yang berasal dari Amerika tropis. Manding sudah tumbuh di Indonesia sejak ratusan tahun lalu untuk kepentingan pertanian.
Sekilas manding memang mirip dengan pete/petai, hanya saja ukurannya lebih kecil dan lebih tipis. Pohonnya pun lebih rendah daripada pohon petai. Di Gunungkidul, manding banyak di tanam di pekarangan rumah. Biasanya dijadikan tanaman pagar bersama tali kacu/tayuman.

Manding dan daunnya juga digunakan untuk makanan hewan ternak para petani. Kalau zaman saya kecil, manding yang buahnya tidak terlalu tinggi akan habis digunakan untuk ‘pasaran’. Buahnya ‘dideplok‘ (ditumbuk) bersama daun jati muda, yang akan mengeluarkan warna merah alami.
Buah manding yang masih muda sering dijadikan lalapan. Biji buah yang masih hijau segar dijadikan salah satu campuran dari ‘trancam‘, bersama kacang panjang dipotong kecil-kecil, cabai dan kecambah. ‘Trancam‘ biasanya dijadikan lauk untuk nasi ‘wudhuk‘ dan ‘ingkung‘.
Biji buah manding yang sudah tua berwarna kecoklatan digunakan sebagai bahan pembuatan tempe. Di Gunungkidul, tempe manding masih bisa dijumpai di beberapa pasar-pasar tradisional. Di antaranya Pasar Argosari, Wonosari ada di lantai 2 pintu selatan dan Pasar Mulo ada di los bagian tengah.

Dari kedua penjual tempe manding yang saya temui, keduanya menerangkan, bahwa mereka sama-sama mengambil tempe dari daerah Semanu. Penasaran dengan kuliner yang sudah terbilang langka ini, saya kemudian mencari informasi tentang warga Gunungkidul yang masih memproduksi tempe manding.
Berbekal sedikit informasi, pada suatu siang yang panas, saya menuju Dusun Dengok Ngampo, Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Gunungkidul. Mengandalkan GPS dan bertanya 2 kali kepada warga sekitar, akhirnya sampai juga ke tempat yang saya tuju. Sebuah rumah semi modern dengan cat merah muda kombinasi biru.
Setelah mengetuk pintu dan ‘kulanuwun‘, tak menunggu lama keluar seorang ibu-ibu kisaran umur 50 tahunan. Beliau adalah Ibu Marni, sosok di balik pembuat tempe manding yang masih bertahan hingga hari ini. Basa-basi sebentar, akhirnya obrolan kami langsung menjadi akrab. Keramahan tulus warga desa di Gunungkidul dalam menyambut tamu adalah salah satu hal yang khas dan asli.

Bu Mar, begitu saya kemudian memanggilnya. Beliau merupakan generasi ke 3 dari keluarganya yang masih setia membuat tempe manding ditengah gerusan produksi tempe kedelai sekarang ini.
“Ndamel tempe manding niku luwih angel tinimbang tempe dele mbak, prosese luwih dawa. Ning arepa luwih angel, kula tetep seneng gawe tempe manding, wong iki tinggalane wong tuwa”
(“Membuat tempe manding itu lebih susah daripada tempe kedelai mbak, prosesnya lebih panjang. Tapi walaupun lebih rumit, saya tetap senang membuat tempe manding, karena ini ilmu peninggalan orang tua”)
Ujar Bu Mar dengan logat Jawa yang khas.
Bu Mar mengisahkan, proses pembuatan tempe manding membutuhkan waktu 2 hari, untuk akhirnya menjadi tempe yang siap dijual. Ada 4 proses yang harus dilalui dalam pengolahannya.

Pertama adalah ‘godhok’ (merebus) selama beberapa jam, kedua ‘ngidhak’ (menginjak-injak) menggunakan ‘tholok’ sebuah wadah dari anyaman bambu yang bentuknya hampir mirip dengan ‘tenggok’. Proses ‘ngidhak’ bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di buah manding. Proses yang ketiga ‘dikum’ (direndam) semalaman, keempat ‘adhang’ (dikukus), sebelum akhirnya akhirnya difermentasi dengan menggunakan ragi agar jadi tempe manding.
Proses fermentasi yang dilakukan oleh Bu Mar tidak menggunakan ragi instan yang saat ini tersedia di pasaran. Menurut beliau, ragi instan malah membuat tempe jadi kurang bagus. Bu Mar memilih menggunakan ‘laru’ (ragi) tinggalan dari simbah, yakni ragi yang masih menempel di daun-daun jati bekas bungkus tempe sebelumnya.
Proses fermentasi dimulai dari tempe yang sudah dikukus, mulai dibungkus kecil-kecil lalu di ‘oser-oser’ (digosok) menggunakan laru yang menempel di daun jati. Setelahnya tinggal dibungkus dan ditunggu sampai tempenya mengeras, berkat kerja-kerja jamur yang ada di laru daun jati. Semua proses yang dilakukan oleh Bu Mar masih alami, dari mulai laru yang digunakan hingga bungkus tempe yang masih menggunakan daun jati hasil memetik di pekarangan.

“Mbiyen neng desa iki, hampir kabeh wargane gawe tempe mbak, ya tempe manding, tempe benguk. Lha nek jaman saiki ya sapa ta mbak sik mangan tempe manding, wis ora umum mangan tempe manding, mending tempe dele. (Dulu di desa ini, hampir semua warganya membuat tempe mbak, ya tempe manding, tempe benguk. Kalau zaman sekarang, siapa yang makan tempe manding? Sudah tidak familiar makan tempe manding, mending tempe kedelai)” Ujar Bu Mar sambil menuangkan teh ke dalam gelas.
Produksi tempe manding Bu Mar memang sudah lama menurun, menurut ceritanya, dulu beliau dan orangtuanya hampir setiap hari membuat tempe manding. Namun saat ini peminat tempe manding berkurang drastis. Hal ini dibarengi dengan sulitnya mencari bahan baku pembuatan tempe manding.

“Manding niku saiki angel golek-golekane mbak, rata-rata wis nggo pakan wedhus. Nek jamanku mbiyen isih okeh turut ngalas, gek sok tak opeki dinggo simbokku gawe tempe, tapi nek saiki ya badhag, manding saiki malah golek-golekane neng pasar ora neng kebon” (manding itu sekarang susah mencarinya mbak, rata-rata sudah digunakan untuk memberi makan kambing. Kalau jamanku dulu manding masih banyak di sawah, sering saya ambil untuk ibukku membuat tempe, tapi sekarang sudah tidak ada, manding sekarang banyaknya malah di pasar bukan di kebon) Ujar Bu Mar dengan semangat.

Tempe manding oleh orang Gunungkidul biasanya diolah menjadi tempe bacem atau dibuat besengek (tempe yang dibumbui santan). Rasanya tak kalah enak dengan kedelai, hanya saja tekstur tempe manding agak lebih keras daripada tempe kedelai. Selain itu tempe manding memiliki bau yang sangat khas, yaitu bau manding itu sendiri.
Sembari menikmati teh dan peyek bikinan Bu Mar, dari arah lain muncul seorang bapak-bapak lanjut usia yang turut bergabung dalam obrolan. Beliau adalah Mbah Bardi, kakak dari Bu Mar yang baru selesai ‘ngarit’ (mencari pakan ternak). Mbah Bardi bercerita panjang lebar tentang keluarganya yang masih senantiasa membuat tempe manding hingga saat ini.

Ia juga menceritakan pengalaman masa lalunya, sebelum masuk program revolusi hijau. Makanan sehari-harinya adalah thiwul dan aneka tempe. Dulu tempe itu tidak hanya kedelai dan manding, tapi juga ada orok-orok, koro pedang, gude, benguk, dan kacang ijo.
“Jaman riyen niku ten mriki napa-napa didamel tempe mbak, jan rekasa tenan nek jaman riyen ki. Arep mangan ndadak golek-golek, mboten kados sakniki panganan nganti diguwang-guwang. Tapi ya nek jare biyungku mbiyen nek ora gelem rekasa ya ora mambu lenga, paribasane ngono kui”
(zaman dulu itu di sini apa-apa dibuat tempe mbak. Sulit sekali lalau zaman dulu itu. Mau makan harus cari-cari, tidak seperti sekarang makanan sampai dibuang-buang. Tapi kata orang tuaku dulu, kalau tidak mau kerja keras ya tidak bisa makan),
Ujar Mbah Bardi sambil menyalakan rokok linthingannya.
Setelah menghabiskan teh, saya pamit pulang. Di perjalanan pulang pikiran saya masih terbawa dengan cerita Bu Mar dan Mbah Bardi. Kondisi alam Gunungkidul yang berbentuk karst, dan dikenal sebagai kawasan yang gersang, justru malah melahirkan beragam pengetahuan yang kaya. Beragam siasat dilakukan untuk bertahan hidup mulai dari pertaniannya hingga ke pengolahan pangan. Tempe manding mungkin baru secuil dari banyaknya kuliner lain di Gunungkidul yang unik dan memiliki cerita panjang.