Lingkungan(rebowagen.com) — Stigma Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah kering dan kekurangan air memang telah tersandang lama. Meski sebetulnya, stigma itu tidak bisa digeneralisasi. Banyak wilayah di Gunungkidul yang sebenarnya mempunyai potensi sumber air yang sangat besar. Entah itu sungai permukaan, sungai bawah tanah ataupun sumber sumber air yang muncul.
Secara geografis, Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi tiga zona yang mempunyai karakter air tanah yang berbeda. Pertama adalah Zona Batur Agung Utara, membentang di wilayah utara Gunungkidul meliputi Kapanewon Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen dan sebagian Kapanewon Semin. Di tengah ada Zona Ledoksari, meliputi Kapanewon Ponjong, Karangmojo, Semanu, Wonosari dan Playen. Lalu di sebelah selatan terbentang Zona Pegunungan Seribu, yakni Kapanewon Purwosari, Panggang, Paliyan, Tanjungsari, Saptosari, Tepus, Rongkop dan Girisubo.


Dari tiga zona diatas, zona utara dan tengah memiliki beberapa kesamaan karakter air tanah. Keduanya berperan menjadi kawasan penangkap air hujan (cheachment area). Air resapan kemudian muncul dalam bentuk mata air permukaan (tuk, sendang, beji, sumur) atau sungai-sungai. Sungai Oya adalah yang terbesar dan terpanjang melintasi. Aliran sungai yang berhulu di Kabupaten Wonogiri dan bermuara di Kabupaten Bantul ini melintasi wilayah Gunungkidul sepanjang 177 kilometer.
Sementara untuk wilayah Pegunungan Seribu bagian selatan, sumber air permukaan adalah telaga (situ) dan sungai-sungai bawah tanah yang bermuara atau muncul di pantai atau lepas pantai Gunungkidul.
Penampung Air Hujan (PAH)
Cerita tentang telaga adalah cerita asik nan klasik bagi masyarakat Pegunungan Seribu. Hampir semua desa memiliki telaga. Dari data Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Gunungkidul, tercatat ada 460 telaga di seluruh wilayah Gunungkidul. Jumlah itu sebagian besar berada di wilayah selatan. Meski di tengah dan utara kita juga bisa menemukan keberadaan beberapa telaga. Selain telaga, ada satu bangunan buatan tempat menampung air hujan yang lazim sebut sebagai bak Penampung Air Hujan (PAH).
Bangunan berbentuk setengah tabung ini sangat umum ditemui di samping rumah-rumah warga. Khususnya di wilayah Gunungkidul zona selatan dan di dua kapanewon yang berada di zona utara yakni Patuk dan Gedangsari.
Dari berbagai sumber, didapat keterangan bahwa Penampung Air Hujan (PAH) di Gunungkidul mulai masif dibangun sekitar tahun 1984. Pembangunan ini gencar dilaksanakan saat masa Orde Baru melalui Program PKAK. Program ini adalah sebuah aplikasi dari teknologi terapan untuk tekhnologi memanen air hujan (rainwater harvesting). Dengan kemudahan perawatan dan keawetannya, PAH terbukti sangat efektif dan mudah diterapkan di wilayah-wilayah kekurangan air di Gunungkidul. Dan pada akhirnya, sejak dibangun hampir 40 tahun yang lalu, PAH menjadi bagian tak terpisahkan dari perikehidupan warga Gunungkidul.
Secara struktur, bentuk bangunan PAH menyerupai tabung separuh yang berdiri di samping rumah atau dapur warga. Posisinya tepat berada di bawah talang air rumah. Fungsi PAH memang untuk menampung air hujan dari genting yang dikumpulkan dengan talang. Tinggi rata-rata PAH dua meter, garis tengahnya 3 meter. PAH menggunakan bahan dasar semen dan mampu menampung sekitar 10.000 liter air.
Beberapa waktu lalu, saya sempat bermain ke rumah seorang teman lama di Padukuhan Bacak, Kalurahan Monggol, Kapanewon Saptosari. Kebetulan di rumah ini juga mempunyai sebuah bak PAH. Saya sempat ngobrol dengan beberapa warga yang kebetulan sedang kerja bakti. Dari obrolan dengan beberapa warga yang sudah ‘sepuh’, banyak cerita tentang PAH dan telaga saya dapatkan.
“Riyen rangka bak menika awale saking sigaran pring, wonten ugi ingkang dibangun ngagem tatanan watu (dulu rangka bak ini awalnya dari bilahan bambu, juga ada yang dibangun dengan tatanan batu),” tutur Mbah Rajiyo, salah satu warga yang ikut kerja bakti.
“Niku kawiwitan rikala jaman pak Harto (itu dimulai ketika zaman Pak Harto (presiden Suharto),” Mbah Barjo yang sedang melinting tembakau ikut menimpali.
Kendati secara struktur bangunan bisa dibilang sangat sederhana, namun mereka menyebut bahwa bak PAH ini, setelah 35 tahun lebih bangunannya tetap awet. Jika ada kerusakan-kerusakan kecil, paling ya retak sedikit dan bisa ditambal.
Simbah-simbah ini kemudian banyak bercerita tentang kenangan sebelum PAH ini dibangun. Telaga Bacak atau Blumbang Sari yang terletak di pinggir desa menjadi sumber air utama bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Mandi, mencuci, memasak ataupun ‘ngguyang’ (memandikan) sapi.
Sebelum ada PAH, warga 5 dusun di Kalurahan Monggol, yakni Bacak, Pulebener, Baros, Pucung dan Dusun Nangsri sangat mengandalkan air Telaga Blumbang Sari. Simbah-simbah ini bercerita bahwa mereka biasannya memikul air dari telaga sampai rumah menggunakan ‘gembreng’ (kotak kaleng bekas minyak).
“Saking wana nggih njujuke tlaga riyen, adus kalih sekalian ngombe. Ning nggih jaman riyen mboten enten critane kelaran weteng (dari ladang ya langsung ke telaga, mandi sambil sekalian minum. Tapi ya jaman dulu itu tidak ada ceritanya sakit perut),” Mbah Tomo ikut menimpali perbincangan gayeng kami. Di antara mereka, Mbah Tomo ini memang sudah tampak paling ‘sepuh’. Rambut dan alisnya sudah memutih semua. Namun saya melihat, rata-rata fisik mereka tampak tetap sehat walau tak bisa dipungkiri faktor umur membuat kulit dan otot liat mereka tampak semakin kendur.
Dulu, telaga memang menjadi tempat utama seluruh warga untuk saling berinteraksi. Mulai dari orang tua, pemuda maupun anak-anak pada pagi, dan sore hari berkumpul di telaga untuk berbagai keperluan.
Menurut cerita mereka, Telaga Blumbang Sari memang tidak pernah kering walau di musim kemarau. Namun pada tahun 1982 telaga ini kering. Waktu itu diadakan ritual besik telaga, dengan diberi tumbal kepala kerbau.
“Nggih percaya kenging, mboten nggih mangga, sak sampunipun ditumbali ndas kebo dugi sak menika mboten nate asat malih (ya percaya boleh, tidak ya silahkan, sehabis di kasih syarat kepala kerbau sampai sekarang tidak lagi kering),” tutur Mbah Tomo.
Hingga sekarang, ritual ‘Besik Telaga’ masih dilestarikan. Setahun sekali pada hari Jumat Legi, warga kerja bakti membersihkan telaga. Kemudian dilanjutkan dengan kenduri sebagai bentuk tata cara menghormati telaga dan sarana permohonan kepada Tuhan agar seluruh warga selalu diberi keselamatan dan hasil panen yang cukup.

Kembali ke cerita tentang PAH. Perkembangan zaman, membuat fungsi telaga sudah tidak pokok seperti dulu lagi. Namun hingga saat ini, meski jaringan PAM telah terpasang di rumah-rumah warga, mereka tetap mengakui keberadaan PAH masih menjadi sarana utama. Ketika musim kemarau telah tiba, otomatis suplai air hujan ke PAH sudah terhenti. Dan fungsi PAH akhirnya digunakan untuk menampung air dari PAM ataupun tangki droping air. Distribusi air PAM memang tidak selalu lancar. Bahkan masih banyak warga terpaksa membeli tangki air.
“Menawi ketiga, toya udan sampun telas, bak saget kangge nampung toya PAM menawi pas medal banter, nak mboten nggih kangge nampung toya saking tengki (saat kemarau, air hujan sudah habis. Bak bisa untuk menampung air PAM saat keluar, atau menampung air dari tangki),” imbuh Mbah Barjo.
PAM yang mengalir ke Padukuhan Bacak, airnya berasal dari sumber air di sekitaran Pantai Ngrenehan. Menurut mereka, air mengalir kadang juga tidak begitu lancar, apalagi saat hari Minggu. Beberapa warga terpaksa masih membeli air dari tangki. Padahal menurut hitung-hitungan biaya rekening PAM kata para warga lebih irit dibanding membeli air tangki. Satu musim kemarau rata-rata mereka membeli 4 sampai 5 kali, dengan harga 120 ribu per tangki. Tergantung jumlah anggota keluarga dan penggunaannya.
“Ingkang baken, toya udan saking PAH menika nek dingge damel wedang teh rasane seger sanget, benten kalih toya PAM utawi tangki (yang jelas, air hujan dari PAH itu jika untuk membuat air minum teh rasanya sangat segar, beda dengan air PAM atau tangki),” ujar Mbah Tomo yang langsung diamini oleh seluruh yang hadir.
Menurut mereka, air PAM dan air tangki kalau direbus terlalu banyak kapurnya dan harus disaring, sehingga rasa teh menjadi berbeda. Sangat beda dengan air hujan yang katanya membuat rasa teh justru menjadi lebih nikmat.
“Nek mboten pitados, mangga diunjuk benterane, gek njenengan rasakke bedane (kalau tidak percaya, silahkan diminum tehnya, dan rasakan bedanya),” kata Mbah Rajiyo sambil mempersilahkan saya minum. Dan setelah beberapa sruputan teh panas dari gelas, saya langsung menganggukkan kepala tanda setuju. Rasa dan aroma teh memang lebih murni tak terganggu aroma kaporit ataupun kapur.
Keberadaan dan fungsi PAH bagi warga yang masih sangat dibutuhkan membuat mereka punya harapan agar program pengadaan PAH bisa dilakukan lagi oleh pemerintah.
“Sokur wonten bantuan kalih napa tiga bak malih saben griya, estu saget migunani kagem masyarakat (sokur ada bantuan dua atau tiga bak lagi setiap rumah, tentu lebih bermanfaat buat masyarakat),” harap mereka.
Tekhnologi terapan yang bisa dibilang sederhana dari ‘rain water harvesting’ atau memanen air hujan berbentuk bak PAH memang dirasa lebih tepat-guna. Tepat dan efisien dibanding PAM atau tangki air yang notabene harus membeli dan lebih mahal. Harapan para warga di Zona Pegunungan Seribu tentang program pengadaan PAH baru dan pelestarian PAH lama bisa dilakukan sebagai usaha yang tepat dalam rangka konservasi air, yaitu pengoptimalan cara memanen air hujan.
Sepintas PAH memang kelihatan ketinggalan jaman, kalah dengan PAM berbayar yang tinggal memutar keran untuk memakainya. Namun demikian, eksistensi PAH yang sudah hampir 40 tahun menemani warga Gunungkidul tentu tidak bisa dikesampingkan.
PAH telah terbukti sebagai teknologi tradisional yang sederhana, murah, tepat dan efektif, serta berdaya guna bagi warga Gunungkidul sebagai salah satu solusi masalah kekurangan air.
“Toya jawah menika, menawi digodok kagem damel wedang, estu benten, luwih seger lan krasa (air hujan itu jika direbus untuk untuk membuat minuman, sungguh beda, lebih segar dan terasa),” kata mereka, dan kalimat itu beberapa kali diulang.
Membahas tentang air di Gunungkidul, saya tiba-tiba ingat obrolan dengan teman saya Irsyad Mathias. Ia adalah seorang dosen Universitas Brawijaya Malang. Selama lebih dari satu tahun, Irsyad melakukan penelitian untuk meraih gelar doktor. Kebetulan project desertasinya adalah tentang “Aksesbilitas air bagi masyarakat di Gunungkidul”.
“Air adalah suatu kebutuhan yang bersifat primanit. Menjadi kewajiban negara untuk menjamin kecukupan air bagi rakyatnya,” kata Irsyad beberapa waktu lalu.
Menurutnya, potensi sumber air di Gunungkidul sebenarnya sangat besar dan mencukupi. Dari hasil analisisnya, masalah kesulitan air yang selalu menjadi suatu hal yang laten di Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan sumber daya air dan pendistribusiannya.
“PDAM sebagai perusahaan resmi daerah sudah bekerja maksimal, tapi karena lembaga ini bersifat ‘profit oriented’ akhirnya mereka selalu rugi. ‘Cost’ atau biaya operasionalnya sangat besar, konon untuk bayar listrik bulanan saja sekitar 2 milyar. Ini tentu menjadi suatu hal yang sangat berat. Salah satu solusinya adalah efektivitas sistem pengelolaan sumber daya air. Termasuk penerapan tekhnologi Rain Water Harvesting (memanen air hujan) yang murah, dan tepat guna, bisa lebih dimaksimalkan,” kata Irsyad.
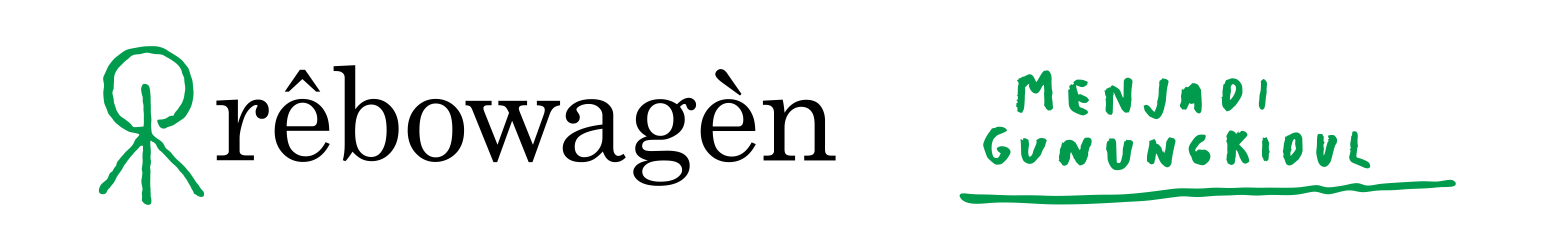












































Menambah wawasan