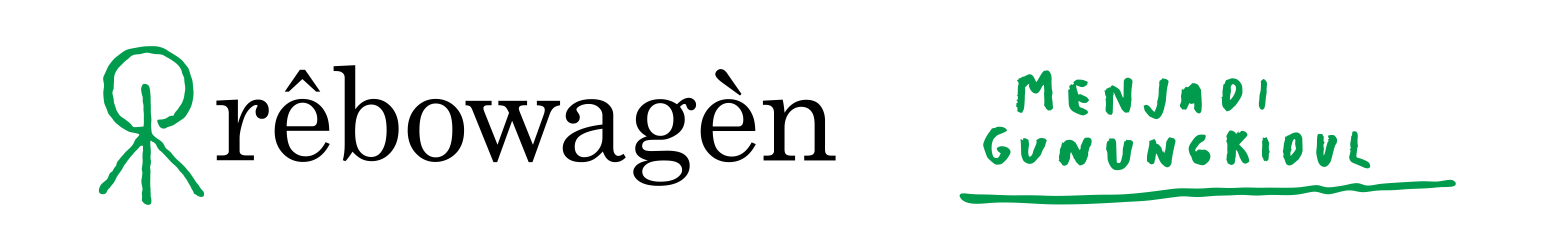Budaya(rebowagen.com)– “Nek pas tekan wetonmu, nek isa gawe among-among, apik meneh nek karo dipasani nduk” “(Kalau waktu ‘weton’ atau hitungan hari lahir, kalau bisa bikin selamatan, lebih bagus lagi sama ditambah berpuasa nduk),”. Ungkapan Siwo Duplak, disela-sela obrolan kami di dapur sambil membuat pisang goreng. Siwo (kakak dari ibu) ini memang banyak memberikan ‘wejangan‘ atau nasehat kiat-kiat hidup tentram berdasarkan apa yang beliau jalani selama ini. Salah satunya adalah rajin berpuasa dan membuat ‘mong-mong‘ (pada beberapa daerah disebut ‘among-among‘) minimal waktu hari lahirnya sendiri.
Sejak kecil, saya tidak asing dengan istilah ‘mong-mong weton‘. Apalagi saat simbah masih sehat, biasanya beliau yang rutin mengingatkan anak dan cucunya untuk selalu membuat ‘mong-mong‘ di hari weton masing-masing. Kadang ketika salah satu dari anak dan cucunya terlupa, simbah sendiri yang akan membuatkan ‘mong-mong‘ tersebut.
Walapun sudah tidak asing dengan tradisi ini, namun pemahaman soal ‘mong-mong weton‘ itu sendiri kurang terdistribusi dengan baik kepada generasi muda seperti saya. Sehingga banyak yang akhirnya mulai meninggalkan tradisi tersebut, karena dirasa kurang memiliki manfaat dan cenderung tabu di zaman seperti hari ini.

‘Mong-mong weton‘ memang bagian dari ‘folklore‘ setengah lisan, maksud dari setengah lisan adalah tradisi yang memiliki perpaduan antara lisan dan bukan lisan. Dalam tradisi ini, unsur bukan lisannya adalah ‘uba rampe’ yang tersaji dalam ‘mong-mong‘. Sedangkan lisannya berupa makna dan fungsi dalam doa-doa yang dipanjatkan saat ‘pasrah’. Folklore yang berbentuk lisan memang mulai tergerus oleh zaman, apalagi yang belum tertulis biasanya akan mudah dilupakan. Ditambah dengan distraksi modernitas yang makin menggerus, menggeser pola pikir bahwasannya sesuatu yang tidak ‘real’ tidak kelihatan mata, hanyalah sebatas cerita, mitos atau dongeng.
Beberapa waktu lalu, saya mengobrol dengan Sigit Nurwanto, seorang pemerhati budaya dan dalang muda asal Padukuhan Seneng, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul. Beliau memaparkan bahwasannya ‘mong-mong‘ atau ‘pamomong‘ sangat berkaitan dengan asal muasal lahirnya manusia. Proses kelahiran dan hari lahir oleh masyarakat Jawa dianggap menjadi peristiwa yang sangat sakral. Dari proses kelahiran, akhirnya melahirkan beragam perkembangan berbagai pakem-pakem Jawa.
“Leluhur kita punya semacam strategi untuk mengingatkan kita pada jasa bapak ibu, para leluhur, serta energi-energi yang membantu kita lahir ke dunia. Hal ini sangat terkait dengan pemahaman ‘kakang kawah adi ari-ari sedulur papat kalima pancer”
Ujar Sigit Nurwanto.
‘Kakang kawah‘ atau air ketuban disebut sebagai ‘kakang‘ (kakak). Fungsi dari ketuban dalam rahim ibu yakni menjadi pelindung bayi dari segala guncangan yang terjadi. Walaupun air ketuban akhirnya pecah ketika melahirkan, namun secara metafisik ‘kakang kawah‘ ini dianggap masih terus melindungi bayi di kehidupan dunia.
‘Adi ari-ari‘ atau plasenta disebut sebagai adi (adik). Fungsi plasenta adalah menjadi jalur makanan bayi di dalam kandungan. Dalam proses kelahiran, ‘ari-ari‘ dipotong usai bayi keluar dari kandungan. Prosesnya terjadi setelah ‘kakang kawah‘ pecah, bayi lahir, barulah ‘ari-ari‘ akan dipotong. Peran ‘ari-ari‘ yang sangat vital bagi kehidupan bayi dalam kandungan ini, akhirnya dianggap sebagai ‘adi‘ (adik).
Selanjutnya adalah ‘getih‘ (darah) dan ‘puser‘ (pusar) aspek penting dalam diri manusia yang turut lahir dan menyatu dengan tubuh.
‘Pancer‘ (pusat), disebut sebagai ‘wadah‘ alias tubuh bayi atau manusia itu sendiri.
“Ketika bayi bertumbuh dan menjadi dewasa, sejatinya ia tidak sendirian. Manusia akan tetap bersama dengan keempat saudaranya yang telah berwujud metafisik. Orang Jawa percaya bahwasannya ‘kiblat papat’ disebut juga sebagai pamomong (pengasuh) yang bertugas menjadi pembimbing bagi yang ‘dimong’ (manusia) untuk selalu berada di jalan yang benar,” lanjut Sigit.

Sakralnya proses kelahiran sang ‘jabang bayi‘, membuat masyarakat Jawa menjadi sangat menghormati hari lahir. ‘Lakon‘ yang dilakukan orang Jawa sebagai bentuk penghormatan hari lahir mewujud menjadi sebuah tradisi ‘mong-mong weton‘. Sebuah tradisi wujud syukur kepada Tuhan dan ungkapan terimakasih kepada ‘pamomong‘ manusia.
Perayaan hari lahir antara masyarakat Jawa dengan barat sangat berbeda. Kita mengenal perayaan hari lahir orang barat yang sering disebut sebagai ulang tahun atau ‘birthday’. Perayaan ini cenderung ke sebuah pesta, berisi hal-hal suka cita, traktiran, atau kejutan-kejutan untuk orang yang berulang tahun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, perayaan hari lahir cenderung ke hal-hal yang berbau spiritual, berpuasa atau bertapa di hari kelahiran.
“Puasa kui ngelih, ngelih kui lara. Paribasane ora ana mulya tanpa nglakoni papa cintraka. Nek neng kisah pewayangan, yen pandawa ingin menggapai kemuliaan atas tanah leluhurnya, yakni Negara Hastina, maka perang adalah jalan yang harus dilewati. Nah, ibarate nek pingin mulya ya perango karo napsumu dewe” (puasa itu menahan lapar, dan itu sakit, ibaratnya tidak ada hal mulia yang bisa dicapai tanpa laku perjuangan. Kalau di kisah pewayangan, Pandawa yang ingin menggapai kemuliaan atas tanah leluhurnya, yakni Negara Hastina, maka perang adalah jalan yang harus dilewati. Nah, kalau ingin mulia hidupnya, ya harus berani memerangi hawa nafsu kita), jelas Sigit panjang lebar.

Perayaan hari kelahiran bagi orang Jawa bukan hanya setahun sekali, melainkan dilakukan ‘selapan pisan’ atau 35 hari sekali. Weton di masyarakat Jawa juga sering disebut sebagai ‘neptu‘ (‘netu’) atau ‘pasaran’. Dalam buku Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang Meraba Masa Depan karya Romo RDS Ranoewidjojo, ‘weton‘ adalah gabungan siklus kalender matahari (senin, selasa, rabu, dst) dengan sistem penanggalan Jawa yang terdiri dari 5 hari dalam setiap siklus (pon, wage, kliwon, legi, pahing).
Menurut Sigit, ‘mong-mong weton‘ bertujuan untuk ‘ngopahi sing momong’ (memberi penghormatan kepada yang mengasuh), yaitu 4 saudara metafisik yang tetap menjaga ‘jabang bayi‘ hingga dewasa. ‘Sedulur papat kelimo pancer‘ menjadi suatu teknologi pengingat dari nenek moyang untuk selalu hati-hati dan mawas diri.
Konon ketika ‘pamomong‘ tidak di ‘mong-mongi‘ atau diabaikan keadaannya, ‘Sang Pamong‘ bisa meninggalkan manusia. Akibatnya hidup akan carut-marut, penuh kesialan dan diselimuti angkara murka.
“‘Pamong’ dan ‘jabang bayi’ merupakan energi yang saling tarik menarik. Pamong menurut orang jawa menggerakkan ‘kareping rahsa’ mengajak ke hal-hal yang baik dan positif. Sedangkan ‘yang dimong’ atau jabang bayi menggerakkan ‘rahsaning karep’ atau nafsu, yang identik dengan hal-hal negatif,”
imbuh Sigit.
Menurut pemahaman Saya, pamong ini seperti hati nurani. Di beberapa momen terutama momen-momen genting hati nurani sering diungkapkan dengan kalimat ‘dengarkan hati nuranimu’. Pengalaman mendengarkan ‘hati nurani’ sulit dibuktikan secara fisik. Tapi proses mendengarkan hati nurani merupakan proses konklusi dari pengalaman batin dengan diri sendiri yang terjadi secara berulang-ulang.

Dalam pelaksanaan ‘mong-mong weton‘ perlu membuat ‘uba rampe‘. Menurut Sigit, ‘uba rampe‘ bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Paling sederhana adalah membuat nasi tumpeng, ‘gudangan‘ (aneka sayuran yang direbus; kacang panjang, bayem, tauge, kangkung, wortel, kubis, kenikir), telur rebus, lalu diletakkan di ‘layah‘ (cobek). Setelah itu didoakan oleh orang tua, biasanya bapak ibu, atau simbah. Meminta perlindungan serta keselamatan kepada Tuhan, setelah itu baru dimakan bersama-sama.
Usai memahami percakapan dengan Sigit, Saya berefleksi bahwasannya tradisi Jawa yang diturunkan oleh nenek moyang sangat arif. Tindakan yang visioner, mampu merumuskan semacam taktik mitigasi kekacauan hidup melalui teknologi ‘pengeling-eling’ seperti ‘mong-mong weton‘. Sayangnya, teknologi hari ini hanya dimaknai sebatas kecanggihan mesin dan robot yang berasal dari ciptaan manusia. Tak banyak orang yang menganggap bahwa ‘Pengeling-eling’ yang dirumuskan oleh para sesepuh Jawa, juga sebuah teknologi yang super canggih dalam mengurangi kerusakan yang terjadi akibat kerakusan manusia.