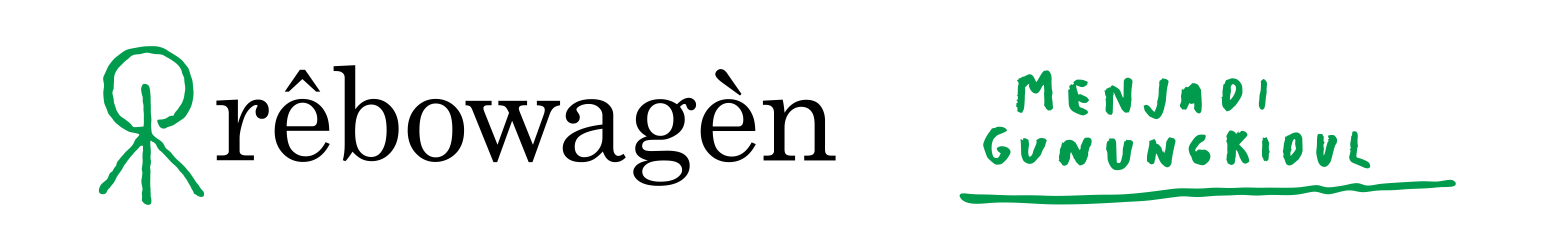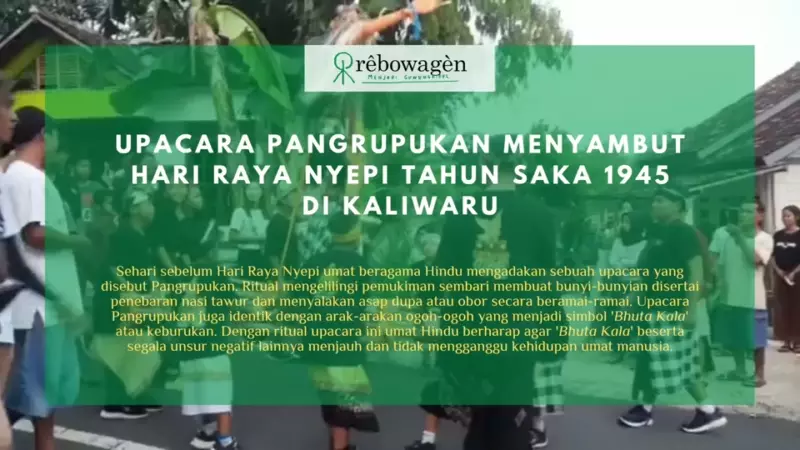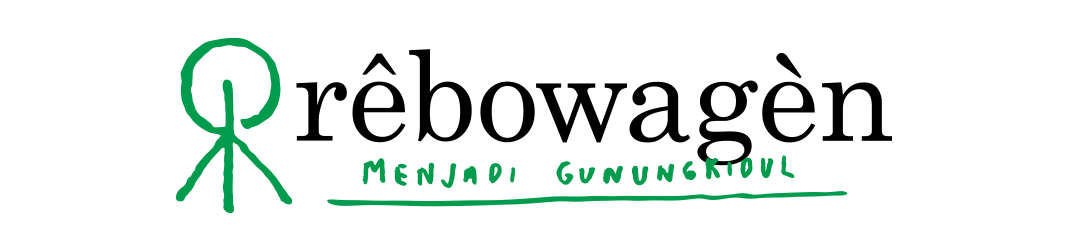Budaya(rebowagen.com)– Rumah adalah suatu hal yang pokok bagi manusia. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah berupaya untuk menempati rumah sebagai tempat hidupnya. Mereka memilih gua atau bagian alam yang dinilai aman dan ideal untuk berlindung dan beranak-pinak. Dengan perkembangan peradaban, setiap daerah akhirnya mempunyai bentuk rumah dengan ciri khas tertentu. Berbagai jenis model rumah ini sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis, iklim, dan kebiasaan hidup atau budaya masing-masing.
Sampai saat ini, belum diketahui secara pasti bentuk asli yang tepat dari rumah adat Jawa pada awal mulanya. Literasi atau keterangan yang menjelaskan tentang hal ini memang sangat minim. Salah satu yang bisa dijadikan acuan adalah relief di beberapa candi yang berasal dari abad ke 9.
Dalam relief ini terpahat rumah orang Jawa yang berciri sama dengan pola dasar bentuk arsitektur ‘austronesia‘. Hal ini bisa dilihat dari ciri umum berupa pondasi bertumpuk, atap memuncak dan bubungan rumah yang memanjang. Dari referensi itu, kuat dugaan bahwa rumah adat Jawa, pada awalnya masih mempunyai ciri yang sama dengan rumah tradisional dari berbagai daerah nusantara yang lain. Budaya ‘austronesia‘ menjadi hal yang sangat mempengaruhi pola dan bentuk arsitekturnya.
Seiring perjalanan waktu, rumah adat Jawa akhirnya berkembang menjadi bentuk yang bervariasi. Namun, ada tiga model rumah yang umum dan digunakan oleh masyarakat sampai saat ini. Ketiganya adalah rumah model Joglo, Limasan dan Kampung. Ketiganya memiliki ciri khas tersendiri, termasuk simbol-simbol dari strata sosial dari sang penghuni/pemilik rumah.

Dalam budaya masyarakat Jawa, rumah menunjukkan lambang atau status sosial dari pemiliknya. Derajat, pangkat serta tingkatan ekonomi seseorang dapat dilihat dari rumah yang ditempatinya.
‘Omah limasan‘ bisa dikategorikan mempunyai status menengah. Di bawahnya ada ‘omah kampung‘ yang menjadi model rumah orang biasa. Rumah model Joglo mempunyai status tertinggi, karena khusus ditempati oleh kalangan bangsawan atau orang yang mempunyai pangkat.
Rumah, bagi orang Jawa sebetulnya bukan sekedar tempat berteduh (fungsi praktis). Secara simbolis, rumah adalah bentuk manifestasi dari cita-cita dan pandangan hidupnya, ini yang disebut sebagai fungsi simbolik. Rumah juga bisa dianggap sebagai bagian dari budaya, yang mengandung arti sejarah keluarga. Banyak ditemui di Gunungkidul, rumah turun temurun yang sudah berusia ratusan tahun.
Secara umum, rumah adat Jawa tersusun dari tiga bagian, yakni ‘bantalan‘ (tanah tempat mendirikan yang biasanya ditinggikan), ‘saka‘ (tiang penyangga bangunan) dan ‘empyak‘ (atap). Ketiga hal ini, mempunyai filosofi tentang kepercayaan spritual dari orang Jawa. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa setiap tingkatan memiliki nilai spritual ‘kamadatu‘, ‘rupadatu‘ dan ‘arupadatu‘.
Trend ‘urbanisasi’ rumah tradisional
Model rumah tradisional, baik Joglo, Limasan maupun Kampung sangat umum digunakan sebagai rumah huni bagi masyarakat Gunungkidul. Namun saat ini, keberadaanya mulai berkurang karena dijual. Ini akibat trend model hunian tradisional marak disukai oleh masyarakat perkotaan. Masyarakat kota yang mempunyai finansial lebih, menjadikan rumah tradisional sebagai tempat usaha, baik rumah makan, kafe, ataupun hotel yang bernuansa etnik.
Sering juga rumah diboyong untuk dijadikan ‘pendapa‘ sebagai simbol pencapaian ekonominya. Untuk peruntukan yang terakhir biasanya adalah perantau dari desa yang sukses dan ingin memboyong kenangan masa kecilnya ke kota.
Menjadi ironis memang, ketika orang desa ingin mempunyai rumah permanen gaya modern. Sedang orang-orang kota yang kepingin nuansa hunian lain, beramai-ramai memboyong rumah tradisional ke kota-kota. Pada akhirnya, saat ini sudah banyak rumah-rumah kayu tradisional Gunungkidul yang dijual oleh pemiliknya, kemudian uangnya dibuat untuk membangun rumah model permanen yang modern.

Rumah yang dijual ini, banyak yang termasuk rumah dengan material kayu jati kuna. Sangat disayangkan memang, ketika rumah kayu warisan turun temurun dijual untuk membangun rumah permanen yang tidak bisa diboyong (dipindah) ke lain lokasi.
Budaya masyarakat Gunungkidul memang mentradisikan bahwa warisan tidak hanya berupa tanah, namun sering orang tua mewariskan rumah bagi anak-anaknya sebagai modal awal membangun rumah tangganya sendiri.
Omah Limasan
Pada tulisan ini, saya akan sedikit mengulik tentang ‘Omah Limasan‘. Selain model Omah Kampung, Omah Limasan termasuk mendominasi dibangun oleh masyarakat pedesaan. Untuk model Joglo memang terbilang jarang, karena status sosial Omah Joglo memang harus dari golongan tertentu.
Omah Limasan mempunyai ciri khas atap yang seakan membentuk bangun ruang limas. Di bagian atas terdapat empat sisi atap yang berbentuk trapesium dan segitiga sama kaki. Rumah limasan rata rata juga mempunyai atap ‘emperan‘ (teras) yang memanjang.

Pagi itu, kebetulan ada tetangga yang sedang ‘sambatan‘ (bergotong royong) mendirikan rumah. Dan kebetulan, bentuk rumah yang dibangun adalah Omah Limasan.
Di sela bekerja saya ngobrol dengan Lik Timbul dan Lik Wario, dua orang tukang kayu yang menjadi ‘arsitek’ dari proyek ‘sambatan‘ ini. Menurut mereka, Omah Limasan strukturnya memang lebih rumit daripada model Omah Kampung. Namun, masih kalah rumit dengan model Omah Joglo.
“Bagian pokok Omah Limasan adalah cagak jumlahnya 8, pengeret 4, blandar 2, dudur 4, suwunan 1 dan sundhuk olor 4 batang,”
terang Lik Timbul
Selain itu, lanjutnya ada bagian pendukung, yakni ‘blandar‘ dan ‘cagak emper‘ (tiang teras) rumah. Serta tentunya ‘usuk‘ dan ‘reng‘ sebagai struktur atap untuk meletakkan genting rumah. Untuk dinding, biasanya menggunakan ‘gedhek‘ (anyaman bambu), atau papan kayu.

“Untuk saat ini, dinding Omah Limasan sudah banyak yang menggunakan batu bata atau batako permanen,” imbuh Lik Wario.
Secara spritual, bagian paling penting dari rumah Jawa adalah ‘suwunan‘. Ini adalah kayu yang terletak pada bagian paling atas. Kendati diameter kayu tidak terlalu besar, dibanding bagian yang lain, namun komponen ini adalah simbol dari suatu harapan dan do’a dalam membangun rumah.
“Suwunan itu adalah ‘penyuwunan’ (permohonan) kepada Yang Maha Kuasa, agar keluarga yang menempati rumah selalu dalam lindunganNya, murah rezeki dan selalu diberi kesehatan dan kelancaran,” lanjut Lik Wario.
Biasanya, kalau orang zaman dulu, ‘natah‘ (melubangi) kayu ‘suwunan‘ harus dengan hitung-hitungan tertentu, termasuk hari dan ‘pasaran‘ baik. Dan orang yang biasa ‘natah‘ atau memasang ‘suwunan‘ juga orang yang dianggap ‘tetua‘ dan disertai dengan do’a do’a khusus.

Setelah ‘suwunan‘, maka komponen yang lain adalah ‘cagak‘ atau ‘saka‘ (tiang). Pada Omah Limasan, ukuran besar dan tinggi tiang akan menentukan kelas dari bangunan keseluruhan rumah. Semakin besar diameter tiang, maka rumah akan semakin berkelas. Biasanya, rumah zaman dulu terbuat dari kayu jati. Semakin tua kayu jati yang digunakan (nggalih), maka kualitas rumah akan semakin baik.
“Sudah tiangnya besar, kayu jatinya tua, harga rumah bisa jadi sangat mahal,”
terang Lik Wario.
Trend ‘urbanisasi‘ rumah tradisional ke kota-kota, akhirnya memang membuat harga rumah kayu saat ini melejit tinggi. Hal inilah yang menggoda masyarakat desa rela menjual rumahnya agar bisa membangun rumah permanen.
Jika hal ini terus berlanjut, maka bisa jadi nanti kita akan sangat jarang menemui rumah tradisional di desa. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang memprihatinkan. Mengingat bahwa rumah tradisional tidak sekedar sebagai tempat berteduh, tapi mempunyai nilai histori dan identitas budaya masyarakat Rumah tradisional warisan turun temurun juga menyimpan sejarah keluarga, dan jika berpindah ke kota, maka tentu semua itu akan tinggal menyisakan cerita.