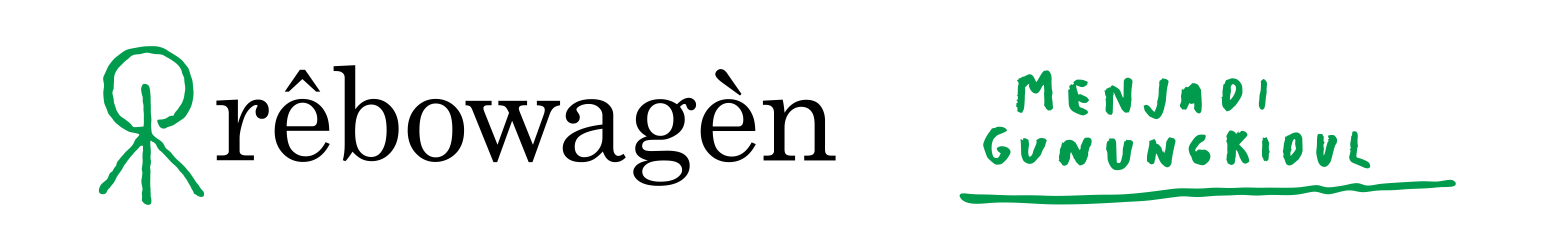Lingkungan(rebowagen.com)– Ndert… ndert… ndert… ponsel saya bergetar berkali-kali menandakan ada beberapa pesan masuk. Pesan datang dari sedulur Resan mengabarkan bahwa seminggu ke depan, tepatnya tanggal 20-27 Oktober 2022 bertempat di Sinambi Farm akan digelar ‘Pekan Climen Rebowagen’. Sebuah festival sederhana lintas komunitas yang mengambil tagline “Belajar Menjadi Gunungkidul”.
Tidak berapa lama tangan saya segera membuka flyer yang berisi agenda kegiatan Pekan Climen Rebowagen. Satu-satu flyer saya buka ada pameran seni, workshop membuat kerajinan berbahan dasar sampah dan daun kelapa, workshop membuat bungkusan makanan berbahan dasar daun, workshop pertanian organic, workshop batik, workshop pengenalan potensi dan pemanfaatan tanaman herbal hingga pementasan wayang.
“Belajar Menjadi Gunungkidul” adalah tagline yang diambil dalam ‘Pekan Climen Rebowagen’ ini. Tagline ini sempat membuat saya bertanda tanya memang kenapa harus belajar menjadi Gunungkidul? Ada apa dengan Gunungkidul?
Sepekan kemudian kembali datang pesan singkat dari sedulur Resan yang berisi sebuah link. Tulisan dengan judul ‘Situganda, Lakon dan Pementasan Pertama Wayang Resan untuk Kampanye Lingkungan’ segera muncul di layar kaca ponsel saya ketika meng-klik link tersebut. Pelan-pelan saya membaca tulisan tersebut. Dari sinilah saya kemudian mendapat jawaban mengapa “Belajar Menjadi Gunungkidul”’ penting dijadikan tagline acara ‘Pekan Climen Rebowagen’.

Bagi teman-teman pembaca yang belum mengenalnya, Resan Gunungkidul adalah sebuah komunitas yang menaruh kepedulian pada keberlangsungan lingkungan. Hampir tiap minggu mereka melakukan pembersihan sumber-sumber mata air, ‘nglangse‘ atau melindungi pohon-pohon yang memiliki fungsi menjaga sumber air dan melakukan penanaman pohon di tempat-tempat yang tersebar di seluruh wilayah Gunungkidul.
Menarik memang lakon yang diangkat kali ini dalam pementasan wayang yaitu sosok Jaka Pangreksa murid dari Ki Ajar Bedhah Sela. Jaka Pangreksa sedang melaksanakan lelaku mencari air suci ditemani dua punakawan yaitu Kanil dan Pungkring. Dalam pencarian air suci tersebut ketiganya harus berhadapan dengan Canthaka Birawa, Mina Pranjala dan raseksi bernama Puspa Girang.
Cerita wayang Situganda yang dimainkan oleh Dalang Sigit Nurwanto ini mengangkat beberapa tokoh yang tidak familiar ditemukan dalam pewayangan. Sejak lahir dan dibesarkan dalam budaya Jawa, wayang mainstream yang selama ini saya tonton tidak pernah lepas dari tokoh pandawa seperti Yudistira, Bimasena atau Werkudara, Arjuna, Nakula dan Sadewa yang memiliki peran protagonis. Sementara tokoh-tokoh antagonisnya digambarkan dalam diri Duryudana, Sengkuni ataupun Kurawa.
Setiap cerita wayang ini juga dilengkapi tokoh ‘punakawan‘ sebagai pelayan, pengawal raja atau bangsawan. Abdi pengiring yang biasanya menyertai tokoh pewayangan kemanapun mereka pergi. Punakawan dalam wayang mainstream terwujud dalam diri Semar, Gareng Petruk dan Bagong. Bahkan di beberapa pewayangan muncul juga tokoh seperti Togog, Bilung maupun Cepot untuk wayang Sunda.

Namun dalam wayang Situganda ini tokoh pewayangan direpresentasikan dalam diri Jaka Pangreksa yang ditemani Kanil dan Pungkring harus melawan penunggu sumber air suci raseksi Puspa Girang yang ditemani oleh Canthaka Birawa dan Mina Pranjala. Tentu saja ada tujuan tertentu mengapa Dalang Sigit Nurwanto menggunakan tokoh-tokoh tersebut dalam Wayang Situganda.
Belakangan dalam cerita terbukalah jatidiri tokoh-tokoh tersebut. Jaka Pangreksa ternyata adalah ikan sidat, Kanil adalah cacing, Pungkring adalah tonggeret atau ‘garengpung’, Cantaka Birawa adalah kodok dan Mina Pranjala adalah ikan lele. Dari sekian hewan yang kita kenal, kenapa pilihannya adalah sidat. lele, kodok dan cacing? Kenapa bukan kambing, sapi, ikan mas, ikan mujair atau ular misalnya. Di sinilah letak menariknya cerita Wayang Resan.
Pagelaran wayang ini memang ditujukan untuk kampanye lingkungan. Cara untuk menggugah kesadaran bersama akan pentingnya menjaga lingkungan dituturkan melalui pagelaran wayang.

Jaka Pangreksa yang tidak lain adalah ikan Sidhat atau lebih dikenal dengan kata pelus sering dianggap sebagai hewan keramat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keramat diartikan suci, dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia. Kedudukan sidat ini memang penting dalam menjaga keseimbangan alam. Naluri alamiahnya, yakni masuk ke dalam urat mata air membuat jalan air terbuka dan lancar. Jadi fungsi sidat adalah untuk membantu menjaga agar rembesan mata air tidak tersumbat (Sukardi, 2021 – Kabarhandayani.com). Sidat dititahkan oleh Sang Pencipta memiliki misi suci untuk menjaga agar sumber mata air lancar mengalir hingga ke urat-urat mata air.

Begitu juga dengan ikan lele (Mina Pranjala). Lele adalah binatang yang masuk dalam golongan omnivora atau pemakan segala. Tidak jarang lele sengaja dipelihara untuk menjaga kualitas air yang tercemar karena lele bisa menghilangkan kotoran (Ciri Khusus Lele dan Fungsinya, 2017 – Websitependidikan.com). Bahkan seringkali ditemukan tempat bagi hajat buang air besar milik warga sengaja ditaruh di atas kolam lele. Memiliki organ arborescent atau insang tambahan membuat lele mampu bertahan hidup di air atau lumpur dengan kadar oksigen yang terbatas. Seringkali kita dapati lele masih bisa bergerak dan bertahan hidup meski dia telah dipindahkan dari air ke daratan. Fungsi lele selain bisa dikonsumsi juga membantu menjaga kualitas air dan membersihkan dari kotoran.

Lantas kenapa cacing (Kanil) penting juga diangkat dalam lakon pewayangan kali ini. Cacing dikenal sebagai hewan pengurai. Menariknya cacing tidak saja mampu mengurai jasad atau hewan dan manusia yang telah mati. Daun yang berjatuhan maupun akar pohon yang telah mati, tetapi cacing juga mampu mengurai batu kapur. Keberadaan cacing ini juga sering digunakan sebagai penanda bahwa tanah di daerah tersebut subur. Cacing membawa manfaat untuk menurunkan PH tanah.
Dengan jalan memakan berbagai bahan organik di tanah dan membawanya ke dalam tanah, cacing secara tidak langsung berfungsi untuk membajak tanah dan memperbaiki aerasi tanah serta menyediakan pori-pori bagi air dan udara. Berbagai bahan organik yang telah dimakan cacing kemudian dikeluarkan dalam bentuk fosfor, kalsium, nitrogen dan magnesiun yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman (Mengapa Cacing Bisa Menyuburkan Tanah?, 2020 – agrotek.id). Cacing ini berfungsi layaknya natural enginer yang mampu mengolah sesuatu yang ada di tanah untuk dilepaskan kembali dalam bentuk zat yang bermanfaat bagi tanah.

Cantaka Birawa atau kodok yang diangkat oleh Dalang Sigit Nurwanto ternyata memiliki fungsi sebagai bio-indikator kerusakan lingkungan (Ular dan Katak, Apa Pentingnya untuk Kita?, 2017 – lipi.go.id). Mengutip penuturan Mirza D Kusrini dari Kelompok Kerja Konservasi Amfibi dan Reptil (K3AR) Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), kodok bernafas tidak hanya dengan paru-paru tetapi juga dengan kulitnya, sehingga hewan ini sangat sensitif terhadap penggunaan pestisida. Keberadaannya yang terus menurun bisa digunakan sebagai indikator bahwa ada kemungkinan wilayah tersebut sudah penat dengan penggunaan pestisida. Kulit kodok ini seperti spons indikator lingkungan yang mampu dijadikan sebagai bio-indikator kerusakan lingkungan atau penggunaan pestisida.

Lantas apa fungsi dari Pungkring atau ‘garengpung’ atau tonggeret. Selain berfungsi sebagai penanda akhir musim penghujan, ternyata keberadaan ‘garengpung’ atau tonggeret ini adalah sebagai bio-indikator juga. Hanya yang membedakan dengan kodok adalah ketika kodok berfungsi sebagai spons indikator maka tonggeret ini sebagai indikator bagi pohon-pohon yang memiliki usia lebih dari 17 tahun.
Binatang ini melangsungkan hidupnya dengan jalan kawin, bertelor dan menciptakan larva baru. Ketahanan hidup larva yang dihasilkan dari perkawinan binatang ini bisa bertahan hingga 17 tahun di dalam tanah seperti generasi-generasi sebelumnya (Tonggeret atau Kinjeng Tangis serta Fakta Ilmiah dan Mitosnya, – Hewanpedia.com). Jika saat ini kita semakin sulit menemukan keberadaan ‘garengpung’ atau tonggeret disebabkan karena jumlah pohon-pohon yang memiliki usia hingga 17 tahun semakin sulit ditemukan.
Data ini semakin menguatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dimiliki DIY tahun 2020 yang masih berada di angka 61,60 atau bernilai cukup. Nilai ini masih berada di bawah target RPJMD DIY sebesar 62,44. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini juga disokong oleh perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang memiliki nilai 58,32 jauh di bawah angka yang ditargetkan oleh DIY sebesar 60,86 (DLHK DIY, 2020).
Dari sinilah saya akhirnya mampu memahami mengapa teman-teman mengangkat tagline “Belajar Menjadi Gunungkidul” dalam ‘Pekan Climen Rebowagen’ kali ini. Lewat tutur pagelarang wayang, teman-teman Resan Gunungkidul berusaha menularkan pengetahuan tentang pentingnya fungsi dari masing-masing binatang tersebut terutama dalam hubungannya dengan kelestarian lingkungan. Gunungkidul yang dikenal tandus, kering dan didominasi oleh batu kapur bukan sebagai penghalang bagi teman-teman Resan untuk menyerah.
Kondisi geografis ini justru menjadi pemantik bagi kegiatan teman-teman Resan Gunungkidul untuk mencari alternatif solusi agar kondisi ini bisa dimitigasi dengan baik dengan jalan menjaga pohon-pohon resan yang berfungsi menjaga sumber mata air, menanam kembali pohon-pohon yang mampu menjadi tangkapan air serta merevitalisasi sumber-sumber mata air yang tersebar di seluruh Gunungkidul. Pelepasan lele beberapa waktu lalu di daerah Sumberan adalah bagian dari kepedulian teman-teman Resan terhadap keberlangsungan sumber mata air di daerah tersebut.
“Belajar Menjadi Gunungkidul” adalah belajar untuk tidak menyerah, belajar untuk bisa menggali potensi yang ada di wilayah Gunungkidul, belajar untuk tidak hanya bisa pasrah tetapi harus terus bergerak meskipun dengan modal yang terbatas. Belajar untuk selalu menjaga apa yang telah Tuhan berikan, belajar untuk tidak lari dari kenyataan dan terus berusaha mempertahankan keyakinan bahwa selama kita masih peduli dan menjaga alam maka alam akan menjaga kita.
SALAM LESTARI!!!