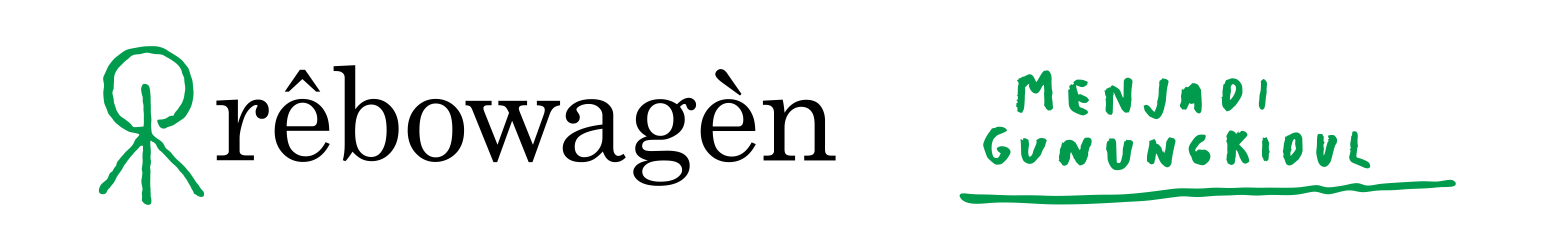Sosial(rebowagen.com)– Suatu malam sekitar tahun 95-an, persisnya saat saya masih SD. Tiba-tiba terdengar gemuruh warga yang berteriak. Saya menguntit kemana simbok melangkah. Ke ruang tengah, ke dapur dan ke halaman saya terus buntuti simbok. Diantara yang berteriak, dari kejauhan ada yang memekik keras, “puluuuuuung…” bersamaan, bersahutan, riuh bergantian.
Keadaan waktu itu teramat mencekam. Simbok rupanya juga panik. Saya semakin gelisah dan takut. Teriakan “pulung” terdengar berulang tak hanya oleh satu orang. Mungkin belasan hingga puluhan. Disela gemuruh orang berteriak, suara ‘cethen’ (cemeti) dipukulkan terdengar berulang-ulang. Sayup-sayup suara lesung penumbuk padi menyusul ditabuh.
Saya benar-benar dalam ketakutan. Kupeluk pinggang simbok kuat-kuat, saat langkah beberapa orang dewasa berikut percakapan mereka terdengar mendekat ke rumah.
Mbah Rejo, yang sedikit lebih tua dari bapak berteriak memanggil. Simbok bergegas keluar rumah. Sejurus saya pun mengikuti.
“Kene iki sing dijaga ditamati (di sini yang dijaga dan dilihat),” imbau Wo Rejo sembari menyorotkan lampu baterai ke atas pohon nangka persis di depan rumah.
Kami semakin takut. Perintah Wo Rejo, sosok yang dikenal ‘bernyali’ semacam ‘negasi’ bahwa Pulung Gantung sedang berkeliaran mencari korban lagi.
Ya, belum lama ada peristiwa orang yang tinggal di tetangga dusun bunuh diri secara gantung diri. Saat itu banyak warga yang percaya, peristiwa kematian gantung diri itu akibat ulah si makhluk gaib (supernatural) bernama Pulung Gantung.
Setelahnya, orang-orang dewasa riuh bercerita, semalam ada yang melihat dan mengejar (baca: mengusir) Pulung Gantung. Baik membunyikan cemeti maupun lesung, juga punya maksud yang sama, yakni mengusir si Pulung Gantung. Makhluk gaib yang digambarkan seperti bola api berekor yang terbang dan berpijar.
Konon, pasca ada orang bunuh diri, si Pulung Gantung masih berkeliaran mencari korban baru. Yang paling diwaspadai, kemana arah pelaku gantung diri menghadap. Ke arah itulah calon korban baru yang kemudian akan gantung diri. Selain was-was dengan arah pelaku menghadap, warga masyarakat juga takut jika pulung gantung jatuh di komplek mereka tinggal. Karena diyakini, warga yang tinggal di mana Pulung Gantung jatuh, akan ada korban baru di wilayah itu. Kelak, meski terkikis, hingga saya dewasa ‘keyakinan’ semacam itu masih membekas.
Ternyata ‘kepercayaan’ yang sama telah ada sejak lama. Saya pernah menemui sesepuh berusia 80-an tahun. Saat ia muda, sebagian masyarakat pun diakui ‘percaya’ bahwa Pulung Gantung sebagai musabab orang bunuh diri.
Teror sepenggal malam mencekam yang saya ceritakan tadi memang tak pernah bisa saya lupakan. Pada momentum tertentu sesekali masih melintas di benak. Saya pun memendam penasaran cukup lama. Setidaknya ada dua pertanyaan yang amat mengganjal bertahun-tahun. Barangkali juga menjadi pertanyaan banyak orang. Pertama: Benarkah pulung gantung ada? dan kedua: Benarkah pulung gantung menjadi penyebab bunuh diri di Gunungkidul?
Silang pendapat selalu terjadi pada berbagai ruang dan forum diskusi dengan pokok pertanyaan di atas. Bertele-tele dan menguras energi. Orang dengan latar belakang dan cara pandang berbeda tak pernah bertemu mufakat. Masing-masing punya argumentasi.
Pulung Gantung
Dalam kamus Jawa-Kawi yang disusun oleh Winters dan Ranggawarsita, istilah pulung sering disepadankan dengan wahyu. Secara etimologis, pulung atau wahyu berarti isyarat, bahwa Tuhan atau leluhur memberi restu pada seseorang untuk menjadi pemimpin atau penguasa. Orang Jawa mengenalnya sebagai wahyu keprabon. Dalam pemahaman orang Jawa, pulung juga dianggap sinonim dengan hal yang berbau kemuliaan, kebahagiaan, berkah dan anugerah. Namun lain ceritanya jika di belakang kata pulung ada kata gantung sehingga menjadi istilah pulung gantung. Sebab, makna pulung gantung kontradiktif dengan pulung. Singkatnya, kejatuhan pulung gantung akan membuat seseorang mengalami malapetaka. Demikian kenyataan keyakinan yang ada.
Mengutip disertasi I Wayan Suwena, Program Pasca sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM), yang disusun tahun 2016 berjudul “Bunuh Diri: Sesat Penandaan Pulung Gantung di Gunungkidul”. Mitos pulung gantung merupakan salah satu wujud intersignes unik yang terdapat pada masyarakat Gunungkidul, yang sebetulnya berwujud tanda alam berupa cahaya. Menurut Badone (2004: 66-67) intersignes adalah tanda-tanda supernatural yang ditafsirkan sebagai isyarat atau peringatan (memorates) akan ada orang meninggal dunia. Dalam narasi intersignes, penampakan kekuatan supernatural mengekspresikan diri melalui fenomena alam, seperti perilaku burung, perilaku anjing, perilaku kuda, mendengar suara-suara tertentu di malam hari dan fenomena alam lainnya. Kemudian, dalam konteks Gunungkidul, tanda alam berupa cahaya melalui proses signifikansi diubah menjadi bahasa atau cerita yang mempunyai marka atau acuan yaitu tindakan bunuh diri.
Teori simbol Raymond Firth (1973: 20-21) merumuskan, manusia dalam hidupnya menata dan menginterpretasikan realitas yang dihadapinya dengan simbol, serta merekonstruksi realitas itu dengan simbol pula. Sebuah simbol dapat pula memenuhi suatu fungsi yang lebih bersifat pribadi dalam hidup manusia. Mengacu teori itu, realitas dapat ditemukan dalam berbagai asas kebudayaan yaitu nilai mistis, cita-cita, keyakinan dan simbol ekspresif yang melekat pada mitos pulung gantung. Simbol ekspresif dimaksud adalah simbol mengesankan yang mengkomunikasikan emosi.
Roland Barthes (2007: 295) juga punya pandangan, bahwa mitos merupakan suatu sistem komunikasi sebagai penyampaian pesan. Artinya, mitos sebagai wahana untuk menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Maka, mitos pulung gantung di Gunungkidul merupakan simbol ekspresif mengandung nilai mistis, dan dari setiap penampakannya dimaknai akan ada orang bunuh diri, yang umumnya dengan cara gantung diri.
Disertasi I Wayan Suwena pun menyimpulkan, tindakan bunuh diri di Gunungkidul hakikatnya merupakan tindakan simbolik dari suatu proses komunikasi. Pelaku sekaligus korban bunuh diri ingin mengatakan sesuatu kepada yang masih hidup, tetapi tidak lagi mampu mengakses bahasa atau media untuk mengatakannya. Maka, tanda alam berupa sinar atau cahaya yang kemudian disebut-sebut pulung gantung, lalu menyebabkan orang bunuh diri, merupakan kekeliruan penandaan oleh sebagian orang di Gunungkidul. Entah sejak kapan, kemudian mewaris ke anak cucu hingga kini. Sampai detik ini pun tak ditemukan bukti empiris bahwa tindakan bunuh diri itu disebabkan karena pulung gantung.
Dalam buku ‘Nglalu’ karya Ida Rochmawati, banyak dikulik tentang bunuh diri dari aspek medis. Psikiater satu-satunya di Gunungkidul ini menyebut peristiwa bunuh diri merupakan cry for help (jeritan minta tolong). Sesungguhnya pelaku ingin berkomunikasi (meminta bantuan) dengan orang di sekelilingnya atas beban berat atau persoalan yang dialami. Namun hal itu tak mampu dilakukan karena berbagai faktor.
Selama puluhan tahun bertugas di Gunungkidul, dokter ahli jiwa ini juga mengamati fenomena bunuh diri di Gunungkidul. Keprihatinannya kemudian timbul. Sesuai sudut pandang keilmuan yang ia miliki, menurutnya keyakinan terhadap Pulung Gantung akhirnya menjadi sebuah belenggu. Menjadi barier atau pembatas bagi masyarakat agar terbuka dengan pandangan lain selain Pulung Gantung serta hal mistis lainnya. Berkenaan dengan bunuh diri, Ida sebagai seorang psikiater, tentunya menilai ini dari aspek kesehatan mental.
Pertanyaan besar ada apa di balik bunuh diri menjadi kabur. Sebab, kematian karena bunuh diri dianggap sebagai kematian “biasa” sehingga aspek pembelajaran kenapa kasus tersebut dapat terjadi kurang mendapat perhatian. Dengan pemahaman bahwa Pulung Gantung sebagai ‘tersangka’ yang utama, akhirnya menjadikan inti permasalahan yang sebenarnya kurang tergali. Kajian dari berbagai sisi seperti faktor biologi, psikologi dan sosial akhirnya tidak menjadi sebuah perhatian.
Namun diakui oleh Ida, keyakinan terhadap pulung gantung bagi keluarga dan lingkungan sekitar lokasi bunuh diri memang menimbulkan kepasrahan dan “nrima”. Sebab, ‘ketiban’ (kejatuhan) pulung gantung itu dianggap sebagai sebuah takdir yang harus dialami.
Bunuh Diri di Gunungkidul
Dalam berbagai kesempatan, Ida Rochmawati menyebut, bunuh diri dilatarbelakangi oleh faktor risiko biologi, psikologi, sosial, budaya dan faktor resiko lainnya. Hal ini dipicu oleh suatu peristiwa yang bermakna. Dia meyakini sesungguhnya tak ada orang yang benar-benar ingin mati.
Peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia tiap 10 September telah ditetapkan oleh IASP (International Association for Suicide Prevention). Penetapan tersebut menjadi bukti persoalan bunuh diri merupakan masalah global yang menjadi perhatian penting. Melalui lama resmi IMAJI (Imaji.or.id), merilis, World Suicide Prevention Day (WSPD) menjadi pengingat sekaligus pesan agar kita menyatukan pandangan dan bergerak melangkah melakukan penanggulangan. Semua pihak sesuai kapasitas masing-masing bersedia ‘sangkul-sinangkul ing bot-repot’ (bahu membahu) mengambil bagian dalam upaya penanggulangan dan pencegahan bunuh diri.
Data yang diolah Yayasan Imaji, sebuah yayasan yang bergerak di bidang kesehatan jiwa di Gunungkidul ini penting untuk disimak.
—Grafik data—
Tabel 1:
Data Bunuh Diri di Gunungkidul 2001-Oktober 2017
Sumber data: Polres Gunungkidul, Diolah IMAJI
Selama kurun waktu 16 tahun, angka bunuh diri di Gunungkidul tak banyak berubah. Rata-ratanya antara 25 hingga 30 kejadian dalam setiap tahun. Jika diolah berdasar faktor risiko, depresi tercatat sebagai faktor risiko tertinggi. Simak data berikut:

—Grafik data—
Tabel2
Ket: Faktor Risiko Bunuh Diri di Gunungkidul 2015-Oktober 2017
Sumber data: Polres Gunungkidul, Diolah IMAJI

Depresi menduduki peringkat pertama sebagai faktor risiko bunuh diri di Gunungkidul sebesar 43 %. Kemudian diikuti sakit fisik menahun sebesar 26 %. 16 % diantaranya tidak ditemukan gejala atau keterangan, lantas 6 % diantaranya tercatat karena faktor risiko gangguan jiwa berat, dan seterusnya. Perlu diketahui, informasi mengenai berbagai faktor risiko tersebut secara umum didata oleh petugas kepolisian Polres Gunungkidul. Di Gunungkidul belum ada petugas khusus dari lembaga tertentu yang menggali secara mendalam perihal faktor risiko dari tiap kasus. Hal ini menggambarkan penanganan persoalan bunuh diri belum berjalan optimal. Payung hukum berupa Perbup Penanggulangan Bunuh Diri yang diterbitkan Pemkab Gunungkidul pada awal 2019 kiranya ditunggu-tunggu implementasinya oleh masyarakat.
Dengan mencermati fakta data yang ada, melihat statistik kejadian bunuh diri meliputi sebaran kejadian, pola geografis, dan pola kejadian semestinya dapat menjadi pemahaman bahwa kejadian bunuh diri adalah permasalahan sosial. Peristiwa bunuh diri adalah masalah kemanusiaan bersama, bukan masalah pribadi, dan juga bukan masalah yang perlu dipandang sebagai hal misterius.
Maka, semestinya hasil riset sosial, ekonomi, antropologi, psikologi, psikiatri, serta penelitian-penelitian lain diantaranya dari WHO, serta bagaimana rekomendasi-rekomendasinya dapat jadi acuan. Harapannya banyak pihak juga membuka diri dengan pandangan ini, bahwa bunuh diri bisa dicegah dengan menekan faktor risikonya.
Nilai nilai kelokalan juga perlu dikelola sebagai salah satu upaya pencegahan bunuh diri. Arisan, ronda atau gugur gunung adalah bentuk kohesi sosial yang bisa digunakan sebagai deteksi dini kasus bunuh diri. Karena tindakan bunuh diri dilakukan bukan serta merta. Akan tetapi, seseorang yang berpotensi bunuh diri sebelumnya akan menunjukkan gejala-gejala. Yang paling sering terjadi adalah ketika tiba tiba menjadi pendiam, menutup diri, atau mengucapkan keinginan untuk ‘lebih baik mati’. Ini adalah sinyal kuat bahwa dia sudah merasa beban yang ia tanggung sudah terlalu berat.
Ketika keluarga dan lingkungan peka terhadap keadaan ini (deteksi dini), maka bisa ditempuh langkah-langkah untuk pencegahan. Salah satu yang bisa ditempuh adalah silaturahmi, ‘ngaruhke’ (menyambangi) sekedar mengajak ngobrol dan menyemangati. Dengan adanya pihak yang mau mendengarkan, paling tidak akan terkurangi bebannya. Bentuk kepedulian ini bisa membuat psikis orang tersebut mengalami tren yang positif. Mengutip kembali pernyataan Dokter Ida, bahwa kejadian bunuh diri adalah “cry for help” atau jeritan minta tolong yang tak terdengar, maka dengan kepedulian kita, dia akan merasa tidak sendiri menghadapi persoalan yang melilitnya. Paling tidak ada support positif yang akan menguatkannya. Dia akan merasa dan berpikir bahwa hidupnya masih berarti bagi keluarga atau lingkungannya. Tentu hal ini akan meminimalisir pikiran bahwa hidup yang dia jalani sudah tidak berarti. Dengan ini diharapkan akan ada pemikiran ulang untuk melakukan bunuh diri.