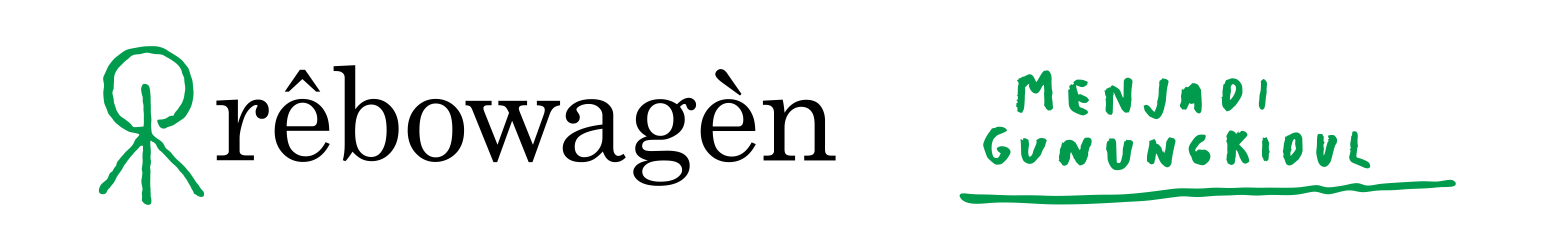Sosial(rebowagen.com)– Sinar matahari pertengahan musim penghujan betul-betul menyengat kulit kurasakan siang ini. Segerombol awan hitam yang sempat menutupinya, dengan cepat berarak menyibak tertiup angin yang berhembus kencang. Cuaca panas di musim penghujan memang terasa sangat menyiksa. Uap air dari tanah yang kalau orang dulu disebut ‘endog amun-amun‘ menambah ‘sumuk‘ (gerah) keadaan. Menyusuri jalan beraspal yang rusak, lalu masuk jalan berbatu di area kehutanan sangat terasa jika ban motorku terlalu keras anginnya. Bundaran hitam berbahan karet yang mengantarku kemana-mana setiap hari itu memang sudah mulai tipis dan gundul. Tadi sebelum berangkat ban ku pompa terlalu keras, untuk antisipasi agar tidak ‘kebanan‘ (bocor) seperti kemarin. Hasilnya sekarang aku nikmati suspensi keras yang membuat tangan terasa sakit.
Panas dan gerah langsung hilang saat saya tiba di air terjun Watu Layah yang berada di Padukuhan Gubukrubuh, Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Gunungkidul. Teduhnya pohon jati di lahan Perhutani dan suara air terjun langsung mengademkan suasana. Siang yang lengang, tak ada seorangpun kulihat. Hanya ku jumpai satu sepeda motor terparkir, mungkin milik petani yang sedang ke ladang, atau pemancing yang turun ke Sungai Oya di bawah. Sisanya adalah sepi dan suara alam yang menguasai.

Obyek wisata yang pada masanya pernah ramai pengunjung ini keadaannya sekarang sungguh memprihatinkan. Beberapa bangunan dari kayu sudah mulai rusak. Tepat di atas air terjun, sebuah gazebo rubuh karena patah tiang penyangganya. Atap gazebo yang berbentuk bundar lancip tampak seperti jamur raksasa tanpa batang. Tempat duduk dari kayu dan bambu rontok dimakan rayap. Bangunan toilet permanen sekaligus ruang ganti pakaian tak kalah memprihatinkan, separo atapnya lapuk, pintunya jebol dan setengah terbuka memperlihatkan kloset yang kotor menghitam.
Tak beda jauh dengan bangunan Mushola, mukena lusuh yang entah sudah berapa lama tak terpakai tersampir di dinding kayu. Ada dua sajadah tergelar setengah melipat pada lantai kayu beralas karpet plastik, daun-daun kering bercampur kotoran cicak dan tokek berserakan di atasnya.
“Kami mulai merintis wisata Watu Tumpeng dan Watu Layah sekitar awal tahun 2016, berbareng dengan booming wisata Gunungkidul yang waktu itu sedang marak,”
kata Tri Wahyudi, Ketua Pokdarwis Teman Gundul (Tempat Main Gunungkidul) yang mengelola Obwis Watu Tumpeng, Watu Layah
Pria berkacamata ini saya jumpai di rumahnya, Padukuhan Gembuk, Kalurahan Getas, Kapanewon Playen. Menurutnya, pengelola dan masyarakat sempat menikmati masa-masa indah dengan ramainya dua tempat wisata ini. Terutama pada akhir pekan ataupun musim liburan.
Obyek wisata Watu Tumpeng berada di bawah jembatan Getas yang melintasi Sungai Oya, perbatasan Gunungkidul dengan Bantul di bagian barat. Watu Tumpeng sebagai pintu masuk wisatawan menawarkan paket ‘rafting‘ menyusuri Sungai Oya untuk kemudian berhenti di air terjun Watu Layah menikmati kuliner tradisional dan indahnya pemandangan persawahan dan suasana pedesaan yang asri.

Keadaan Watu Tumpeng tak kalah memprihatinkan. Start awal paket ‘rafting‘ sekaligus sekretariat Teman Gundul keadaan sekarang terbengkelai tak terurus. Bangunannya juga sudah lapuk dan mulai ambruk. Sekretariat sekaligus gudang yang terbuat dari papan kayu, pintu depannya terkunci. Saat saya melongok ke belakang, dindingnya sudah terlepas, didalamnya teronggok puluhan ban bekas alat ‘rafting‘ yang sudah tak terpakai. Sebuah pelampung kumal penuh jamur berwarna oranye tergantung diam di dinding kayu pada sebuah paku yang sudah berkarat
“Dulu, kalau ramai, ya sehari bisa ada pemasukan 3 sampai 4 juta,” lanjut Tri Wahyudi sambil mengenang masa jaya Obwis yang ia kelola bersama kelompoknya.
Ia melanjutkan, keadaan berubah saat Badai Cempaka melanda Gunungkidul di akhir tahun 2017. Badai yang menyebabkan banjir terbesar sepanjang sejarah (mungkin) di Gunungkidul ini menyebabkan Sungai Oya meluap. Kantor dan sekretariat Pokdarwis Teman Gundul ikut terkena dampaknya. Peralatan yang dipakai untuk paket ‘rafting‘ banyak yang hilang terbawa banjir, demikian juga dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya.
“Bisa dikatakan, kami bangkrut saat terjadi bencana itu. Keuntungan pengelolaan dari wisata sebagian besar kami belanjakan untuk melengkapi fasilitas, dan semuanya hilang dalam sekejap. Akhirnya setelah banjir aktivitas wisata berhenti total” lanjut Tri Wahyudi lagi.

Saat bencana berlalu, butuh waktu agak panjang untuk Pokdarwis Teman Gundul berupaya bangkit kembali. Memang tak mudah untuk mengulang semangat seperti awal merintis. Kembang kempis pengelolaan baru kembali berjalan pelan, badai Pandemi Covid-19 datang mendera.
Aturan PPKM dalam upaya menekan laju penularan Covid membuat dunia ekonomi secara umum sangat terdampak, begitupun dunia pariwisata. Pukulan yang kedua ini, betul-betul membuat Obwis Watu Tumpeng Watu Layah sekarat hingga sekarang. Keadaan serupa yang juga terjadi pada puluhan obyek-obyek wisata baru ‘korban‘ booming wisata Gunungkidul.
Supancar, Kaur Ulu-Ulu Kalurahan Getas juga menyampaikan hal senada. Kebetulan ia dulu adalah salah seorang perintis Pokdarwis Teman Gundul.
“Permasalahannya sekarang adalah, bagaimana menumbuhkan semangat kembali teman-teman pengelola, setelah dua kali mengalami pukulan berat kemarin. Dulu, kami secara sukarela hampir tiap hari ‘gugur gunung’ (kerja bakti) mempersiapkan Watu Tumpeng, Watu Layah agar bisa jadi tempat wisata. Bahkan, untuk modal awal, kami sempat iuran untuk membangun fasilitas dan peralatan rafting. Tapi sekarang, untuk sukarela warga kerja bakti tiap hari lagi seperti dulu kayaknya sudah sangat berat,” kata Supancar.
Meski begitu, ia menyatakan beberapa kali berupaya untuk menginisiasi kembali wisata di desanya. Saat ini, pemerintah desa sedang mengupayakan rintisan tempat wisata baru di Kelurahan Getas, yakni Gua Sengok. Saat saya bertanya, bagaimana nanti jika nasibnya sama dengan Watu Tumpeng Watu Layah, Supancar langsung menyahut bahwa konsep rintisan ini nantinya akan bersambung dengan menggabungkan Obwis yang dulu sudah pernah ada, yakni Watu Tumpeng Watu Layah.

“Secara sederhana, jujur kami butuh stimulan program bantuan dari pemerintah, untuk menggugah kembali semangat warga untuk membangun kembali wisata ini. Tanpa itu, terus-terang kami merasa kesulitan. Kalau awal dulu iya, tanpa kenal lelah kami tiap hari kerja bakti dan swadaya, sekarang kok rasanya pesimis mengulang semangat itu kembali,” imbuh Tri Wahyudi kembali.
Booming wisata Gunungkidul memang pernah memunculkan ‘euforia‘ membuat tempat wisata sangat menjanjikan bagi banyak desa di Gunungkidul. Program pemerintah tentang pembangunan wisata yang beranggaran besar akhirnya menjadikan setiap wilayah berlomba-lomba membuat tempat wisata. Kadang hal itu menjadi sangat naif, di mana masyarakat beranggapan seolah membuat suatu tempat wisata itu adalah hal yang dianggap mudah dan instant.
Pengertian tentang bagaimana membangun wisata sendiri di tingkat basis masih sangat terbatas. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) akhirnya sering tidak mempunyai konsep pembangunan wisata yang jelas dan berkelanjutan. Mereka cenderung ‘latah’, dan terkadang memaksakan sebuah konsep yang tidak berdasar pada potensi wilayahnya.

Kasus sekaratnya Watu Tumpeng – Watu Layah menjadi satu hal yang menarik, meski sebetulnya, dua obyek wisata ini mempunyai potensi wisata alam yang cukup menjual. Di Gunungkidul, saat ini ada puluhan rintisan tempat wisata yang mangkrak menyisakan lunturnya impian warga untuk ikut bisa merasakan ‘gula-gula‘ booming wisata Gunungkidul.
“Pariwisata itu adalah sekelumit cerita dari ruang-ruang yang lalu diabaikan,”
kata Rucitarahma Ristiawan, Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Gajah Mada (UGM)
Kebetulan, beberapa waktu lalu saya berkesempatan ngobrol dengan dosen muda yang akrab disapa Awang ini. Sekarang, ia sedang melakukan riset penelitian tentang pengaruh wisata terhadap alih fungsi lahan, sebagai bahan desertasi S3 nya. Salah satu obyek penelitiannya adalah tentang pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Berikut beberapa catatan awal dari riset yang ia lakukan di Gunungkidul.
Menurut Awang, pembangunan pariwisata kerap dianggap sebagai yang mampu untuk memberikan keuntungan berlipat bagi masyarakat secara ekonomi, sosial maupun penguatan aspek kebudayaan. Kenyataannya, asumsi tersebut hadir dan diproduksi secara hegemonik sebagai visi dari modernitas kawasan, yang cenderung hadir dalam ruang-ruang teknokratik pemerintahan.

Visi pembangunan tersebut selalu diikuti dengan ketergesaan-ketergesaan lain dalam aktivitas pembangunan fisik kawasan, termasuk pembangunan objek wisata. Harapannya, semakin cepat pembangunan fisik kawasan semakin cepat pula pembangunan dapat dirasakan dampak baiknya, setidaknya nalar tersebut mendasari upaya pembangunan pariwisata saat ini.
Yang disebut sebagai upaya pembangunan ini hadir sebagai praktik komodifikasi ruang melalui pariwisata. Ruang tak jarang hanya dimaknai sebagai komoditas, yang keberadaannya hanya dihargai berdasarkan seberapa banyak keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan dari pembangunan di dalamnya. Dalam logika seperti ini, ruang sengaja diciptakan, dikreasikan dan diatur sedemikian rupa berdasarkan nalar untung rugi.
Pariwisata tentu saja mengakomodasi nalar seperti ini. Bisa dilihat dari seberapa banyak ruang yang ditransformasikan untuk kepentingan pariwisata, menjadi kawasan wisata, objek wisata, ataupun atraksi wisata. Proses transformasi ruang tersebut tentu saja dibekali dengan harapan untuk meraup keuntungan ekonomi secara cepat.
“Celakanya, harapan tersebut berkelindan dengan kegagalan kita untuk membaca ruang secara relasional, terhubung dengan ruang-ruang kehidupan lainnya, yang menjadikan kita berpikir bahwa pariwisata merupakan satu-satunya ruang absolut yang harus diperjuangkan keberadaannya,” jelas Awang panjang lebar.

Nilai dari ruang–ruang sebagai komoditas pariwisata selalu dikaitkan dengan kemampuan ruang-ruang tersebut untuk memproduksi pengalaman wisatawan. Dengan kata lain, ruang tersebut telah menjadi lokasi pameran, eksebisi dari dirinya sendiri yang dikurasi oleh kepentingan-kepentingan beberapa pihak untuk mendapatkan profit dari bisnis dan investasi yang ditempatkan di ruang pameran tersebut. Profit tersebut baru bisa direalisasikan apabila ada transaksi pembelian komoditas yang dilakukan oleh wisatawan.
Di satu sisi, pemerintah secara langsung akan mendapatkan keuntungan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mayoritas berasal dari pajak usaha pariwisata seperti usaha penginapan dan restoran. Di sisi lain, pengusaha jasa pariwisata, seperti pengusaha penginapan dan property, restoran, agen perjalanan wisata juga secara langsung mendapatkan keuntungan melalui pembelian produk mereka oleh wisatawan. Semuanya berasal dari visi terhadap pariwisata sebagai lokomotif pembanguan suatu area yang menjadi stimulan adanya proyeksi terkait keuntungan ekonomi dari suatu kawasan.
“Akan tetapi, pariwisata juga harus dipahami sebagai industri yang sebenarnya rentan, rapuh dan mudah krisis. Kerentanan ini disebabkan oleh tergantung nya pariwisata terhadap hukum pasar. Pengusaha akan mendapatkan untung ketika ada yang membeli produknya. Ketika tidak ada yang membeli produknya, ya tidak untung. Akibatnya, logika permintaan dan penawaran dalam pembangunan pariwisata ini berujung pada krisis yang dialami oleh banyak objek wisata di Gunungkidul sekarang,”
lanjut Awang.

Awang mencontohkan, pada saat pandemi Covid-19 yang lalu, pembatasan kegiatan wisata menyebabkan menurunnya, kalau tidak boleh menyebutnya sebagai tidak ada kunjungan wisatawan ke objek wisata di Gunungkidul. Tidak adanya permintaan terhadap ruang pariwisata sebagai komoditas mengakibatkan banyaknya ruang-ruang pariwisata tersebut menjadi terbengkalai, mangkrak dan tidak terurus.
“Tidak ada wisatawan sama dengan tidak adanya pendapatan, tidak ada pendapatan berarti tidak ada perawatan, dan tidak ada perawatan berarti diabaikan karena tidak menguntungkan. Menjadi lebih memprihatinkan dalam sudut pandang saya, ketika memikirkan seberapa banyak uang yang dulu sudah dihabiskan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur tersebut, dengan iming-iming keuntungan berganda dari “investasi” yang sudah dilakukan,”
Belum lagi ketika melihat berapa banyak lahan yang dialihfungsikan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur pariwisata seperti akomodasi, jalan raya, dan terminal transportasi. Alih fungsi lahan tersebut juga memiliki konsekuensi perubahan ekosistem yang kebanyakan justru membahayakan pariwisata dan manusianya sendiri, seperti longsor dan banjir.
Belum lagi terjadinya bencana sosial seperti permusuhan atas sengketa tanah, dan konflik sosial lain. Pada akhirnya, menjadi memprihatinkan ketika melihat semuanya yang dikorbankan untuk pariwisata tersebut hanya berujung pada terbengkalai dan mangkraknya objek wisata karena dianggap tidak lagi menguntungkan bagi pihak yang berkuasa.

Terbengkalainya ruang-ruang pariwisata yang diciptakan tersebut setidaknya memberi dua refleksi bagi diri saya pribadi. Pertama, sejauh mana pariwisata akan terus mendominasi mode penciptaan ruang dengan jenis pariwisata yang seperti apa? Pertanyaan tersebut terlalu menggelisahkan untuk saya, karena jawabannya susah sekali saya temukan. Pariwisata yang sejauh ini kita pahami selalu didasarkan pada nalar untung rugi, membangun ini berarti akan menghasilkan keuntungan itu. Hal ini menjadikan kita abai, tidak hanya dengan keberadaan ruang-ruang kehidupan lainnya yang perlu dipahami keberadaannya, tetapi kepada hakikat kita sejatinya sebagai manusia yang membutuhkan, dan berdampingan dengan entitas kehidupan lainnya.
Kita seakan terasing dengan diri kita sendiri, ketika semuanya terus menerus dikalkulasi dengan logika untung-rugi, yang membuat apa yang disebut sebagai pembangunan itu selalu abai, melupakan kebutuhan objek yang dibangun itu sendiri. Kedua, terabaikannya ruang-ruang pariwisata sekarang mungkin bisa dimaknai sebagai kesempatan untuk mengenal sejatinya apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Apa yang dibutuhkan dan diinginkan dari suatu upaya pembangunan, dan sejauh mana kita benar-benar sadar, eling, waspada, terhadap asal muasal keinginan dan kebutuhan yang kita coba proyeksikan melalui serangkaian kampanye pembangunan pariwisata.
“Terakhir, pariwisata, tidak selalu menjanjikan modernitas. Kesadaran akan kebutuhan dan keinginan, kesadaran akan keterhubungan manusia dengan ruang dan entitasnya itulah yang menjadikan pariwisata, di suatu hari nanti, akan melampaui modernitas. Pariwisata yang ayem, tentrem dan semeleh,”
pungkasnya