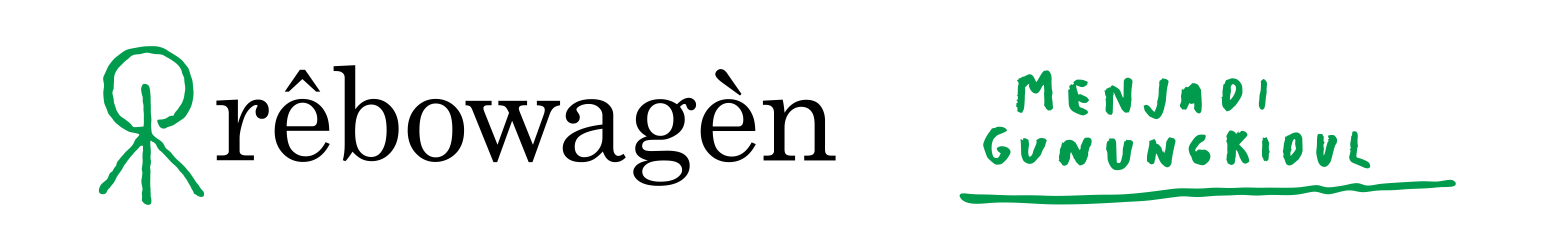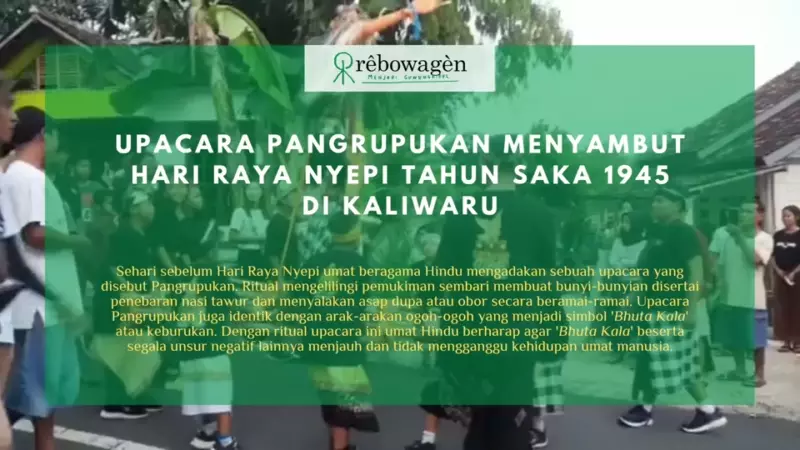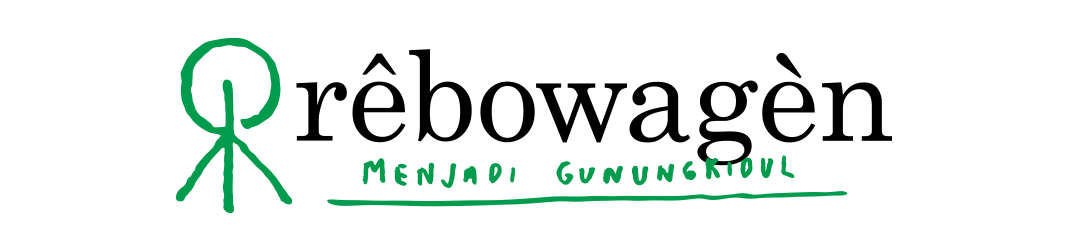Daftar isi
Budaya(rebowagen.com)– Memasuki Bulan Sura (Muharram), masyarakat Yogyakarta yang masih ‘nguri-uri‘ benda-benda pusaka atau tosan aji mulai ramai mengadakan upacara ritual ‘jamasan’. Pada beberapa daerah yang lain, ‘jamasan‘ tidak dilakukan pada Bulan Suro, tapi pada bulan yang berbeda. Misal di daerah Demak, Jawa Tengah, ‘jamasan‘ dilakukan pada Bulan Besar (Dzulhijah). Di Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka dan sekitarnya, upacara ‘jamasan‘ pusaka atau disebut ‘Ritual Panjang Jimat‘ digelar pada Bulan Maulud.
Terlepas dari waktu pelaksanaannya yang berbeda, ritual ‘jamasan‘ di berbagai daerah mempunyai maksud yang sama. Yakni sebagai upaya merawat dan melestarikan benda pusaka warisan leluhur. Sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap cerita, sejarah, dan eksistensi yang melekat pada benda tersebut.
Sejarah mencatat, peradaban yang berkembang di tanah Jawa sejak dulu memang terdiri dari banyak kerajaan. Dengan berbagai latar belakang dan zaman yang berbeda, kerajaan-kerajaan ini masing-masing mengalami pasang surut masa kejayaan. Pada akhirnya, hal ini meninggalkan berbagai cerita sejarah, baik otentik maupun dalam bentuk cerita tutur. Sampai saat ini, berbagai pelosok di tanah Jawa, kaya akan kisah-kisah perjuangan leluhur dalam membangun sebuah peradaban.
Raja, ksatria, tokoh serta ragam kejadian, menghiasi cerita yang dipercaya oleh masyarakat lokal masing-masing daerah. Nah, cerita tentang benda-benda pusaka ini selalu mengiringi pada setiap fragmen sejarah. Pada level pusaka legendaris, kita tentu pernah mendengar Keris Kyai Nagasasra Sabuk Inten, Kyai Sengkelat, Kyai Kopek, Keris Mpu Gandring, Tombak Kyai Baru Klinthing dan banyak lagi yang lain. Di Keraton Yogyakarta, ‘jamasan‘ dilakukan tidak sebatas pada senjata, namun juga pada kereta kuda, gamelan, dan benda-benda yang dianggap mempunyai nilai sejarah.

Pada masyarakat Jawa, benda pusaka tidak melulu hanya dimiliki oleh para raja, penguasa atau punggawa kerajaan. Strata sosial di bawahnya, bahkan sampai pada rakyat petani juga mempunyai pusaka yang biasa disebut ‘cekelan‘ (pegangan). Benda-benda ini diwariskan secara turun-temurun, tak heran, usia benda pusaka ini rata-rata sudah sangat tua. Perawatan dengan cara ‘jamasan‘ ini secara kasatmata memang bertujuan agar warisan pusaka yang terbuat dari logam ini tidak cepat rusak karena korosi (berkarat), sehingga akan selalu terjaga kelestariannya.
1 Makna ‘jamasan’
Beberapa waktu lalu, saya sempat mengobrol dengan Mahmudi dan Sigit Nur, warga Padukuhan Seneng, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari. Dua orang ini sedang mempersiapkan ritual ‘jamasan‘ di Sumur Gandhok, Padukuhan Papringan, Kalurahan Plembutan, Kapanewon Playen. Menurut mereka, selain mempersiapkan segala ‘ubarampe‘ yang berwujud material, persiapan batin dari sang ‘penjamas‘ juga harus dilakukan sebelum hari ‘jamasan‘.
“Jamasan adalah ritual untuk membersihkan pusaka, sebelum kita melakukan hal itu, sudah seharusnya kita berusaha untuk membersihkan diri dulu. Membersihkan jasmani ataupun rohani agar niat yang kita mohonkan kepada Tuhan bisa dilancarkan,”
kata Mahmudi, pria 64 tahun yang kesehariannya akrab disapa Mbah Mudi.
“Hakekatnya, ‘jamasan’ adalah upaya membersihkan diri, atau instropeksi. Pusaka adalah ‘cekelan’ atau pegangan. Dalam tradisi ini, kita tidak hanya membersihkan wujud benda, tapi sekaligus membersihkan jiwa dan sifat kita, dari segala hal yang bersifat buruk,” Sigit Nur menambahkan.

Ritual ‘jamasan‘ bagi masyarakat Yogyakarta, biasanya dilakukan pada hari Selasa Kliwon di Bulan Sura. Jika tidak ada hari Selasa Kliwon, maka dipilih hari Jumat Kliwon. Pemilihan hari dan pasaran yang dianggap baik ini, berdasarkan tuntunan Sultan Agung yang menggabungkan kalender Saka Jawa dan kalender Islam.
Sigit Nur menambahkan, bahwa ‘jamasan‘ benda pusaka, contohnya keris atau tombak, juga mempunyai fungsi melestarikan warisan seni ‘adi luhung’ tinggalan leluhur. Benda-benda itu dulunya tidak dibuat secara sembarangan. Sang Mpu membuatnya dengan ‘laku prihatin‘, juga dengan doa dan harapan-harapan baik, agar apa yang ia buat nantinya bisa bermanfaat untuk anak cucunya.
“Keris, tombak, atau pedang dibuat dengan ilmu ‘metalurgi’, makanya di Jawa sering dikatakan setiap pusaka mempunyai ‘pamor’ sendiri-sendiri. ‘Pamor’ ini dibuat dengan batu meteor, dan dengan teknik khusus berbahan campuran baja dan besi, ditempa menjadi bentuk senjata. Pengolahan ‘metalurgi’ ini tentu menggunakan tekhnologi tinggi pada zamannya. Ini membuktikan bahwa nenek moyang kita dulu adalah seniman yang handal,” kata Sigit menerangkan dengan bersemangat.
Terkait ‘keampuhan’ atau ‘tuah’ yang sering melekat pada benda pusaka, Sigit Nur menjelaskan, bahwa ‘asêp‘ atau ‘tuah’ benda pusaka itu terletak pada kekuatan doa sang pembuat. Dalang muda yang pernah mengenyam pendidikan pedalangan Keraton Yogyakarta ‘Habirandha‘ ini mengungkapkan, bahwa ampuhnya sebuah pusaka sangat tergantung dari ‘gentur tirakat‘, serta ‘laku‘ do’a dari Sang Mpu dalam proses pembuatannya. Selain doa, dalam prosesnya memang tak bisa lepas dari kesabaran, keuletan, ketelitian serta spirit pantang menyerah. Hal inilah yang dimaksud bahwa sebuah pusaka mempunyai nilai artistik serta pesan moral yang tinggi.
“Pembuatan keris, menggunakan teknik melipat baja, dalam proses menempa senjata, Sang Mpu selalu menyelipkan doa kepada Tuhan, pada setiap lipatan-lipatan tubuh keris. Doa yang dipanjatkan berulang-ulang atau sering disebut sebagai ‘mantra’ ini terperangkap pada ruang lipatan, sehingga abadi dan bisa membawa ‘tuah’ dari pusaka. Tapi harus tetap diingat, yang membuat ampuh bukan logam atau manusia, namun kekuatan doa Sang Mpu yang dikabulkan oleh-Nya,” terang Sigit Nur.
2 Bahan-bahan ‘jamasan’ pusaka
Banyak dari pusaka asli tanah Jawa tinggalan kerajaan yang telah hilang. Kebanyakan dari pusaka-pusaka ini hanya tinggal menyisakan cerita atau mitos yang melegenda di masyarakat. Demikian juga benda pusaka di Gunungkidul. Kurangnya pemahaman tentang nilai benda pusaka, menjadikan sang pemegang/pewarisnya akan dengan mudah menjual atau sekedar menghibahkan kepada pihak lain. Mereka menganggap bahwa merawat benda-benda ini adalah suatu hal yang repot. Bahkan dalam beberapa kejadian, ‘nguri-uri‘ benda pusaka dianggap melulu soal ‘mistis’ dan ‘tabu’.

Seiring berkembangnya komunitas pecinta ‘tosan aji‘, literasi dan edukasi tentang pelestarian benda pusaka mulai muncul di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya event ‘jamasan‘ pusaka yang diselenggarakan oleh berbagai komunitas pelestari ‘tosan aji‘.
Dari hasil obrolan dengan Mbah Mudi dan Sigit Nur, berikut beberapa bahan yang harus disiapkan dalam prosesi ‘jamasan‘ secara sederhana. Beberapa bahan yang berfungsi sama tidak harus semua ada, karena fungsinya bisa saling menggantikan.
- Kembang setaman/sri taman
Campuran bunga/kembang yang terdiri dari 5 jenis, diantaranya mawar merah dan putih, kanthil, kenanga dan bunga melati. Atau ada juga yang menggunakan bunga 7 rupa - Minyak wangi/minyak ‘jamasan‘
Minyak wangi yang berbahan dasar kayu cendana, atau bunga melati, atau minyak wangi dari bahan macam-macam bunga. - Air rendaman campuran buah nanas, jeruk nipis buah pace dan air kelapa
- Batu atau serbuk ‘warangan‘
- Sabut kelapa halus, abu gosok dan sabun
- Bekatul
- Baki/nampan/kotak kayu
- Dupa/kemenyan
- Kain mori putih (1/2 atau 1 meter)
- Tikar
- Sikat gigi yang baru (jangan bekas)
3 Langkah-langkah ‘jamasan’ pusaka
Dari hasil obrolan bersama Mbah Mudi dan Sigit Nur, begini saya sarikan langkah-langkah atau tahapan ‘jamasan‘ pusaka. Mungkin ada beberapa perbedaan teknik dari beberapa ‘penjamas‘, namun maksut dari cara itu bertujuan sama.
Ngawu

Tahap pertama yaitu ‘ngawu‘ atau ‘di awu‘. Proses ini berfungsi untuk membuka pori-pori bilah pusaka. Juga untuk mengangkat noda atau sisa dari minyak atau pengasapan dupa yang lama. Caranya, basahi bilah keris dengan air tawar biasa. Kemudian gosok menggunakan sabut kelapa halus dengan abu yang telah dicampur sabun. Penggosokan ini harus dilakukan dari bawah ke atas, tidak boleh melawan arah, karena bisa merusak ‘pamor‘ pusaka. Setelah dirasa cukup, bilas pusaka dengan air tawar biasa, kemudian dikeringkan dengan kain mori
Medhok neyeng

Setelah kering, masukkan bilah pusaka dalam rendaman air campuran air kelapa, nanas, buah pace dan air jeruk yang telah difermentasi sebelumnya. Ini berfungsi untuk membersihkan bilah pusaka dari karat. Rendam beberapa saat, hingga ‘medhok‘ (luntur) karat yang menempel. Kemudian digosok memakai sikat atau sabut kelapa halus. Pastikan semua karat dan kotoran telah hilang dari bilah pusaka. Setelah itu bilas dengan air tawar yang telah ditaburi kembang setaman atau 7 rupa.
Ngatul/di katul
Sesuai dengan namanya, proses ini menggunakan ‘bekatul‘ atau sisa penggilingan padi. Bilah pusaka yang telah dibersihkan dengan air ‘kembang setaman’ kemudian ditaburi bekatul kering. Hal ini perlu dilakukan, karena bilah pusaka yang sudah berumur tua biasanya permukaannya sudah tidak rata. Bekatul berfungsi agar bisa mengangkat atau menyerap seluruh air dari pori, sehingga bilah pusaka bisa benar-benar kering. Sambil mengeringkan bilah, maka bekatul dibersihkan dengan sikat sampai benar-benar bersih.
Mepe/ngisis
Setelah bilah pusaka benar-benar bersih, maka selanjutnya adalah proses ‘mepe/ngisis‘ atau dijemur. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan suhu yang pas pada bilah pusaka sebelum proses ‘warangan‘. Suhu bilah keris/tombak yang pas, nantinya akan sangat berpengaruh terhadap hasil ‘warangan‘ yang berupa ‘pamor‘.
Marangi

Ini adalah tahapan untuk menampakkan ‘pamor‘. Dalam ilmu ‘tosan aji‘, banyak sekali jenis dan macam ‘pamor‘ pada benda pusaka. Misal, ‘beras wutah‘, ‘blarak sineret‘, ‘junjung drajat‘, ‘klabang sayuta‘, ‘pamor kendhit‘, ‘kalacakra‘, dan banyak yang lain, dimana mungkin penyebutan setiap daerah atau orang berbeda. ‘Pamor‘ inilah yang dipercaya terbentuk dari batu meteor. Pada tahapan ‘marangi‘ ini dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian dari ‘penjamas‘. Serbuk ‘warangan‘ diketahui mengandung racun ‘arsenik‘ yang sangat berbahaya jika masuk dalam aliran darah melalui luka terbuka. Proses ‘marangi‘ juga biasa disebut ‘dikeprok‘ atau ‘pejetan‘ atau bilah pusaka dipijat dengan jari-jari tangan ‘penjamas‘. Proses ‘marangi‘ bisa diulang sampai dua kali, dan diakhiri dengan penjemuran.
Minyaki
Proses terakhir adalah ‘minyaki‘ atau pemberian minyak wangi pada pusaka. Pusaka yang telah selesai dijamas kemudian dikembalikan gagang dan ‘warangka’(sarungnya). Kemudian terakhir diberi minyak wangi. Orang dulu kemudian mengasapi bilah pusaka dengan asap dupa/kemenyan, hal ini bertujuan agar pusaka tidak gampang terkena karat.
Ada proses ‘jamasan‘ yang tidak sampai pada proses ‘marangi‘. Namanya ‘mutih‘, jadi tidak sampai menampakkan ‘pamor‘ senjata. ‘Mutih‘ berfungsi untuk membersihkan dan menghilangkan karat. Ritual ‘jamasan‘ adalah upaya untuk merawat dan melestarikan warisan karya leluhur. Seluruh proses kemudian diakhiri dengan ‘kenduri‘ atau ‘selamatan‘.
“Kita tidak melakukan permohonan kepada benda pusaka, apalagi menyembahnya. Doa-doa dipanjatkan hanya kepada Tuhan, memohon ampunan dan keselamatan serta berkah dalam kehidupan,”
pungkas Sigit Nur.