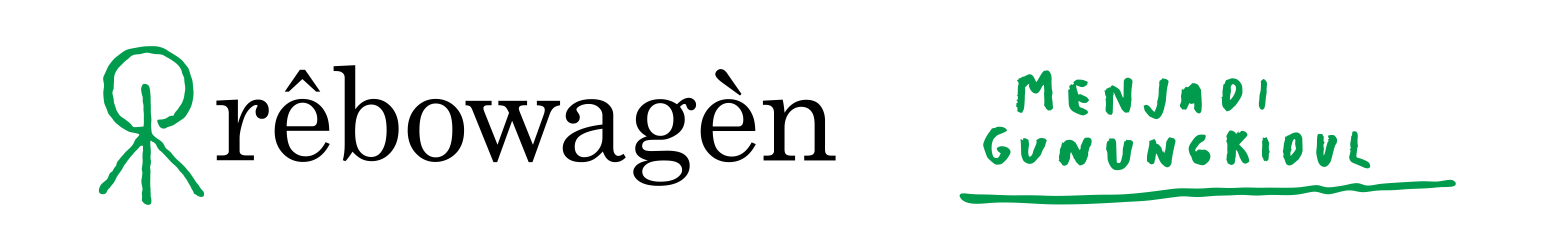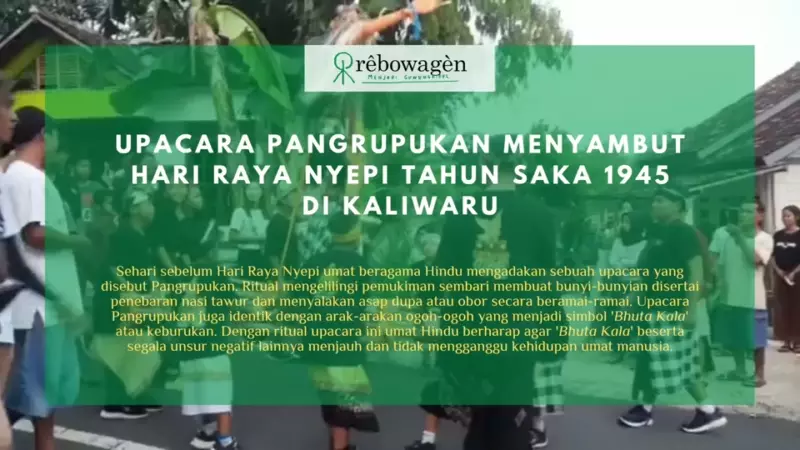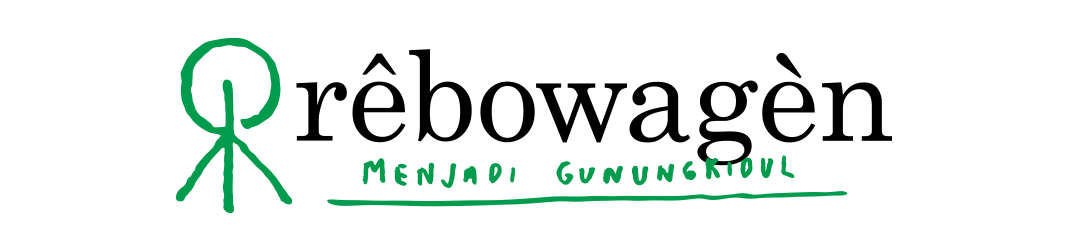Lingkungan(rebowagen.com)– Akhir pekan ini saya ke Telaga Boromo. Salah satu diantara ratusan telaga di kawasan Gunung Sewu wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan. Telaga Boromo berada di perbatasan antara Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari dan Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan.
Entah apa yang tiba-tiba membuat saya ingin bernostalgia. Waktu kecil hingga remaja banyak waktu saya habiskan di telaga ini. Mandi, mencuci, bermain air bersama teman-teman seangkatan, mencari ikan, atau sekedar nongkrong-nongkrong. Rumah orang tua saya memang termasuk dekat dengan lokasi telaga. Namun, sejak saya menikah tahun 2009 dan pindah ke Wonosari menempati pondok mertua indah, intensitas kunjungan saya ke telaga minim sekali.
Dalam perjalanan mengendarai sepeda motor, kelancaran lalu lintas sedikit terganggu. Maklum, akhir pekan. Bus dan kendaraan wisatawan pribadi lainnya dari berbagai kota banyak bergerak ke selatan menuju pantai-pantai Gunungkidul yang sekarang menjadi idola.

“Asem,” gumam saya dalam hati. Saya kaget dan spontan ‘misuh’ (mengumpat) sepersekian detik usai dikagetkan suara klakson bus yang hendak mendahului. Asap knalpot seperti cerobong pabrik keluar bergumpal-gumpal dari knallpot bus di depan saya yang terengah-engah mendaki tanjakan Sodong.
Akhirnya saya tiba di telaga Boromo. Di tempat ‘padusan’ (pemandian) laki-laki atau biasa disebut ‘lanangan’ saya agak lama tertegun. Seperti sebuah slide film, dalam lamunan saya seperti melihat Si Su kecil bersama teman-temannya mandi di sana. Telanjang bulat, tangan kiri menggenggam pelir yang belum disunat, berdiri di batu yang datar serta menjorok ke air. Lalu Si Su melompat, byurr. Sensasi dan segarnya air telaga sampai sekarang seakan masih bisa saya rasakan.

Tak jauh dari ‘lanangan’ ada ‘wedokan’, tempat mandi khusus kaum hawa. Dahulu kala, simbok-simbok serta mbak-mbak dusun tiap pagi atau sore memenuhi ‘wedokan’. Mandi, mencuci pakaian dan perabotan dapur. Penamaan tempatnya mengambil status gender. Lanang (laki-laki), tempat mandinya disebut lanangan. Wedok (perempuan) menjadi ‘wedokan’.
Meski tidak ada aturan tertulis, leluhur telah mewariskan pembagian spot mandi ini. Pantang bagi laki-laki dan perempuan yang mandi di tempat yang sama. Masyarakat sadar, telaga merupakan tempat pemandian umum. Beda dengan pengantin baru. Pasangan suami istri yang belum lama menikah mendapat toleransi. Mereka akan mandi di tempat yang sama. Bukan di wedokan dan lanangan. Mereka akan memilih tempat lain yang aksesnya mudah.
Untuk angkatan bapak-bapak, sebelum mandi terlebih dulu menjauh dari padusan untuk mengambil air pakai ‘blek’. Alat ini umumnya berbentuk balok atau tabung berbahan alumunium. Ada yang pakai bekas kemasan roti lalu ‘digapit’ atau diberi dudukan dari kayu. Air yang dipikul pakai ‘blek’ ini kemudian dibawa pulang untuk dimanfaatkan berbagai keperluan rumah tangga. Dari memasak, hingga minum baik orang maupun hewan ternak. Pokoknya peran air telaga waktu itu sangat vital untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.

Agak jauh dari tempat padusan, di tepi telaga yang lebih datar dijadikan sebagai tempat pemandian ternak. Spot ini disebut ‘sapen’. Transformasi dari nama ternak, yaitu Sapi. Dulu setiap hari banyak warga yang membawa sapi miliknya ke telaga untuk dimandikan.
Pembagian spot untuk fungsi tertentu, berikut penamaannya tidak hanya di telaga Boromo. Hal yang kurang lebih sama juga umum di telaga-telaga lain di Gunungkidul. Masyarakat sekitar telaga cukup arif dan bijak merawat dan memanfaatkan telaga.
Selain airnya, warga masyarakat juga mampu memperoleh manfaat dari biota telaga, khususnya perikanan. Meski skala hasilnya tak besar namun sekali waktu bisa diandalkan.

Sebelum bercerita potensi perikanan, saya ingin memberitahu potensi tambang, khususnya di telaga Boromo. Di telaga ini terdapat dua spot bernama ‘mbatan’. Tiap spot dengan garis tepi yang tak terlalu panjang, jenis batunya beda dengan batuan pada umumnya. Batuan yang lebih dominan di kawasan telaga adalah batu ‘bedes’. Namun di dua sudut telaga yang saya sebut tadi jenis batuannya berbeda. Sesuai nama, disebut ‘mbatan’ karena batuannya berjenis seperti batu bata. Permukaan batu cenderung halus, karakternya lebih empuk atau mudah patah. Warga yang tinggal tak jauh dari telaga, Mbah Supardi berkisah, sekitar tahun 60-an silam, masyarakat mengambil batu di ‘mbatan’ untuk membuat tungku atau dapur saat ada warga yang menggelar hajatan. Saya yang hadir ke bumi di era milenial tak lagi menemui kebiasaan ini.
Adapun untuk potensi ikan, jenis Mujair dulu paling banyak dihasilkan dari telaga Boromo. Selain itu sebagian kecil ada ikan lele, cetol atau tungkuk, kepiting dan udang. Ada periode musim tertentu masyarakat bisa dibilang panen ikan, kepiting atau yuyu hingga udang.
Mujair paling banyak dicari. Cara yang paling umum dengan memancing dan menjaring. Kebiasaan mencari ikan di telaga telah menghadirkan berbagai teknologi tradisional berupa alat tangkap ikan dan pendukungnya.
Ragam Alat Tangkap Ikan Tradisional di Telaga Boromo
Soal teknik mencari ikan dengan alat pancing saya yakin, pembaca sudah cukup paham konsepnya. Kurang lebih sama dengan yang dimiliki oleh mereka yang tinggal atau memiliki kebiasaan memancing di sungai dan pantai. Modifikasinya saja yang mungkin bisa beda. Nah di telaga Boromo ada beberapa jenis pancing, selain yang paling sederhana. Inovasi pancing ini banyak muncul oleh mereka yang berusia remaja pada tahun 90-an. Waktu itu ada pancing ‘grendel’, ‘cekrik’ dan ‘rendet’.

Pancing ‘grendel’ guna menyasar ikan yang berada di tengah dan cenderung di permukaan. Pancing ‘grendel’ dioperasikan oleh dua orang. Masing-masing orang memegang penggulung senar dari botol. Satu orang berada di tepi telaga memegang penggulung, satu lagi berada di tepi telaga yang lain. Jadi dua orang ini berhadap hadapan segaris. Kail yang berjumlah antara 5 hingga 7 yang dilengkapi umpan ditarik ke tengah. Saat memperoleh 1 atau dua ikan, kail ditarik ke pinggir. Diberi umpan lagi lalu ditarik ke tengah lagi.
Pancing ‘rendet ‘dan ‘cekrik’ konsepnya hampir sama. Keduanya dioperasikan tanpa umpan. ‘Rendet’ diisi beberapa kail yang disusun ke atas, dilempar ke tengah lalu ditarik ke pinggir. Pemancing melempar pancing secara acak. Ikan yang sial akan terkena mata pancing dan menjadi rejekinya. Beda dengan ‘cekrik’. Kail pada pancing ‘cekrik’ dibuat berdompol. Pemancing akan mencari lobang atau kubangan ikan didasar telaga. Indikatornya pakai kambang pancing berukuran panjang. Butuh jam terbang tinggi agar menguasai teknik mancing ini. Baik ‘rendet dan ‘cekrik’ hanya dioperasikan saat air telaga surut.
Selain pancing, banyak ragam alat tradisional penangkap ikan, udang atau dan kepiting. Pertama, berupa jaring. Dulu saya pernah mengoperasikan alat ini. Jaring dianyam dari senar berukuran kecil. Dibuat berbentuk semacam kerucut. Diameter bagian atas bisa mencapai 1,5 hingga 2 meter. Galah penampang atas terbuat dari bambu yang diraut sedemikian rupa sehingga lentur lalu dibuat berbentuk oval. Jaring ikan ini diberi tongkat atau ‘genter’ dari bambu lurus dengan panjang antara 5 hingga 7 meter .
Tak seperti pancing, penggunaan alat ini hanya berlaku saat musim hujan tiba. Saat volume air telaga cukup banyak. Momen ini juga bisa diartikan saatnya panen ikan mujair. Secara umum, warga menyepakati aturan itu meski tidak tertulis. Pertama, jelas untuk menjaga keberlangsungan perkembang-biakan ikan. Panen ikan setahun sekali secara tidak langsung memberi kesempatan ikan berkembang biak semakin banyak. Sebab, beda dengan memancing, penangkapan ikan dengan jaring akan mengurangi populasi ikan di telaga dalam jumlah banyak. Tak hanya itu, ketentuan menggunakan jaring hanya pada saat ketinggian air tertentu juga bertujuan agar air telaga tidak keruh. Karena kedalaman air cukup, lapisan ‘lendhut’ atau dasar air tak teraduk jaring. Pertimbangan itu mengingat air masih dibutuhkan untuk mandi serta dikonsumsi. Bagi yang nekat, jika tertangkap basah melanggar aturan, jaring bisa disita dan diberikan ke tempat Pak Dukuh.
Mbah Kis Paikin, tetangga saya dulu menyampaikan, tanda saat tiba waktu menjaring yang tepat yakni manakala tongkol jagung mulai berisi. Tanda lainnya, saat ‘Slumpring’ pada batang bambu terbuka.

Dari cerita Mbah Kis Paikin, saat ‘njaring’ disepakati dimulai, warga dari sekitar telaga beramai-ramai menjaring ikan. Meski hanya musiman, hasilnya terkadang lumayan. Manfaat yang paling praktis, asupan gizi keluarga masyarakat di sekitar telaga jauh lebih baik karena konsumsi ikan naik. Lebih-lebih yang hasil tangkapannya banyak. Ikan-ikan mujair dari Boromo lantas dijual di pasar Trowono.
“Ada warga saat tiba waktunya memupuk tanaman di ladang terkendala karena tak punya uang buat beli pupuk. Lalu, dari hasil menjaring ikan malam hari, paginya bisa buat menebus pupuk di toko,”
tutur Mbah Kis Paikin.
Tak berlebihan, hasil jualan ikan mujair itu juga bermanfaat untuk menambah penghasilan keluarga sekalipun sekali dalam setahun.
Alat tangkap ke dua berupa ‘wuwu’. Alat ini difokuskan pada jenis ikan lele. Wuwu terbuat dari anyaman bambu. Dianyam sedemikiam rupa menjadi bentuk semacam botol air mineral. Beberapa centi ke dalam dari bagian ujung diberi katup atau tutup. Jika ikan masuk dipastikan akan terperangkap dan sulit keluar. Alat ini dipasang di dalam air telaga, ditindih atau dijepit batu. Biasa dipasang saat sore sembari mandi, kemudian keesokan harinya dicek. Jika Wuwu berisi satu atau dua ekor ikan, dipastikan gairah makan pemilik ‘wuwu’ dan keluarganya naik, sebab lauknya lezat.

Ada juga ‘corik’. Ini merupakan alat tangkap udang, sesekali juga untuk kepiting. ‘Corik’ juga terbuat dari bambu dan diberi tangkai. Saat dipasang diberi pakan berupa panggangan adonan bekatul yang dicampur bahan tertentu, daun kemangi misalnya. Sekali mencari udang, pemilik ‘corik’ akan memasang di pinggir telaga dalam jumlah banyak. Bisa belasan hingga puluhan. ‘Corik’ yang sudah terpasang dicek lalu diambil udangnya urut sesuai urutan pemasangan. Begitu terus berulang-ulang.
Ada juga alat berupa ‘kepis’. Fungsinya sebagai alat wadah ikan saat menjaring mujair. Piranti berbahan anyaman bambu ini dikenakan penjaring layaknya tas ‘slempang’.
Untuk ikan kecil, semacam cetul, biasanya dijaring pakai jaring yang bahannya dari ‘selambu:. Tongkat atau ‘genter’ selambu ini lebih pendek, karena ikan kecil biasa dicari di bagian pinggir. Piranti rumah tangga yang terkadang bisa dipakai menangkap cetul atau tungkuk ada ‘kukusan’ (kerucut), penutup sajian di meja makan. Mereka yang biasa menangkap tungkuk pakai alat-alat dapur tersebut biasanya simbok-simbok saat mencuci pagi hari. Boleh dibilang sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Artinya sembari mencuci pulang juga bawa lauk. Simbok saya sering melakukannya. Tungkuk telaga Boromo rasanya sangat khas. Lezat sekali, digoreng atau dilinting (dipanggang dengan dibungkus pakai daun pisang) sama-sama nikmat.
Selain ikan dan udang, adakalanya musim Yuyu atau kepiting. Biasanya banyak kepiting muncul saat hujan telah berlangsung sekitar 2 hingga 3 bulan. Kepiting banyak menempel di batuan pinggir telaga. Bisa ditangkap dengan tangan kosong atau kepiting dijebak agar masuk ke kerucut yang dipasang di dasar telaga. Sisa-sisa nasi atau ‘tiwul’ di kerucut memancing cetul, udang dan kepiting untuk masuk. Saat diangkat ke permukaan, semua bisa ditangkap. Musim banyak kepiting dan aktivitas menangkapnya itu biasa kami sebut ‘mijah yuyu’. Kepiting santan, yang empuk cangkangnya menjadi kepiting tangkapan paling favorit.

Ekosistem Telaga Berubah
Panen menjaring ikan mujair dan menangkap kepiting sejak kurang lebih sepuluh tahun terakhir tak lagi ditemui di Telaga Boromo. Semua seakan tinggal kenangan. Ikan mujair populasinya sedikit, kalau kepiting kini kok cenderung jarang ditemui. Bahkan ada yang bilang punah dari Telaga Boromo. Entah apa sebabnya. Apakah perubahan kelestarian atau kualitas air dan ekosistem telaga, atau karena hadirnya spesies baru di telaga? Entahlah.
Saya ingin bercerita, belasan tahun lalu telaga mulai dikelola dengan sistem baru. Telaga menjadi tempat pemancingan umum yang berbayar. Sistem ini membuat tak lagi ada aktivitas panen ikan dengan cara dijaring oleh warga sekitar. Kesepakatannya memang demikian.
Berbagai jenis ikan air tawar mulai dari nila, tawes dan tombro ditebar saat awal mulai musim hujan. Kemudian selama menunggu proses panen melalui pemancingan berbayar, menangkap ikan di telaga tentu tak boleh dilakukan. Panen ikan selanjutnya dilakukan secara akbar dan menjadi semacam event yang diikuti oleh orang-orang dari berbagai wilayah setelah membeli tiket. Pembukaan pemancingan biasanya dilalukan saat musim kemarau. Saat volume air surut drastis. Saat dibuka untuk umum, orang berjejal memancing. Umpan pancing beraneka ragam. Momentum pemancingan pertama di telaga belasan tahun lalu ini kemudian mengenalkan warga sekitar dengan umpan memancing yang beragam itu. Dulu, orang-orang sekitar hanya mengenal cacing, bulir nasi, laron, dan pijer sebagai umpan. Tapi sejak pemancingan berbayar ini, umpan mancing tak lagi tradisional. Berbagai campuran umpan pelet menggunakan resep rahasia campuran essen (perasa) mulai digunakan.

Umpan kail dalam jumlah banyak dari ratusan pemancing yang masuk ke air dalam rentang waktu tertentu saat volume air sedikit, sepertinya membuat air tercemar. Ini dugaan sepintas saya, sebab, tak ada yang pernah mengukurnya. Namun yang jelas, saat ini kualitas air telaga yang tinggal sedikit memang cenderung berubah. Warna air menjadi hijau keruh. Adakalanya berbau dan sepertinya sedikit mengental.
Pernah pula, ikan jenis sapu-sapu berkembang biak tak terkendali di Telaga Boromo. Tidak tahu siapa yang sengaja memasukannya ke telaga. Ada momentum di mana pinggir telaga penuh bau busuk bangkai ikan sapu-sapu. Itu terjadi pada suatu kesempatan event pemancingan, peserta banyak yang kecewa ketika banyak ikan sapu-sapu yang terpancing. Ikan yang dianggap tak layak dikonsumsi ini dibuang begitu saja, berserakan dan mati meninggalkan bau busuk.
Saat ini, vegetasi sekitar Telaga Boromo tak banyak berubah. Pohon beringin, bulu, kuang dan serut, masih ada. Namun beberapa tumbang karena termakan usia.
Saya menyebut Telaga Boromo telah hilang. Bukan secara fisik, namun kebiasaan panen menjaring ikan dan menangkap kepiting tak ada lagi. Pun demikian dengan ‘keramaian’ Telaga, saat ini telah banyak yang hilang dan berganti mengikuti keadaan jaman.
Telaga memang semakin tersingkir perannya sebagai penyuplai air bagi kebutuhan warga. Awal tahun 2000an, Sambungan Rumah (SR) dari PDAM mulai merata. Praktis telaga semakin ditinggalkan. Orang-orang yang datang ke telaga semakin berkurang. Kurang lebih waktunya tak berselang lama dengan pengelolaan telaga untuk pemancingan berbayar.

Sementara, dulu telaga bak ruang publik. Orang-orang tak hanya mandi dan mencuci. Banyak orang datang dan berlama-lama serta betah berada di pinggir telaga. Bercengkrama sebelum atau sesudah mandi. Kemudahan mendapat air dengan cukup memutar kran membuat kebiasaan ini semakin ditinggalkan.
Kesadaran Penghijauan
Meski ‘penghuni’ telaga yang lama seperti ikan mujair dan udang masih ada, namun saat ini populasinya semakin sedikit.
Akibat Anomali musim beberapa tahun yang terakhir, Telaga yang asal-usul namanya tak diketahui warga sekitar ini pernah nyaris kering. Padahal, sejak dulu dibanding telaga lain yang berdekatan, Boromo terkenal paling awet airnya.
Kemarau cukup panjang membuatnya nyaris kering. Kemudian, siklon tropis cempaka tahun 2017 lalu membuatnya lebih parah. Hujan dengan intensitas super lebat sepertinya menjebol lapisan dasar telaga. Lubang ‘ponour’ atau ‘luweng’ terbuka di salah satu sudut telaga. Air kemudian masuk ke lubang dan menerobos masuk semakin ke dalam bersatu ke sistem saluran sungai bawah tanah.

Masyarakat, diantaranya pemuda kemudian tergerak. Lubang yang kemudian terlihat ditutup memakai sampah organik dan batuan. Tanggul penutup bahkan dibuat. Kemudian di atasnya ditanami pohon resan.
Penutupan lubang luweng diikuti penanaman pohon dalam jumlah yang lebih banyak di sekitaran telaga
Lurah Karangasem, Sigit Purnomo yang tinggal tak jauh dari telaga menyebut, ada belasan pohon yang kemudian ditanam. Dia berharap kelak vegetasi tutupan lahan sekitar telaga lebih rindang. Sekalipun airnya tak banyak dimanfaatkan, namun keawetan dan kualitas air telaga harapannya bisa lebih terjaga.