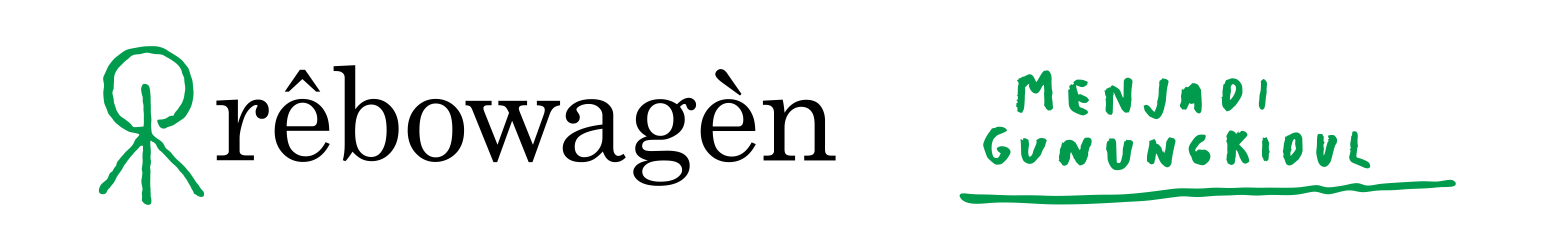Tembang lirih terdengar lamat lamat dilantunkan dari bibir seorang wanita tua yang bersandar pada sebuah batu di bukit Pengalapan pantai Nglambor. Syair tembang bahasa Jawa yang ia nyanyikan mendayu dayu terbawa angin, dengan iringan suara debur ombak pantai selatan. Nada nada itu mengalun menjadi sebuah simphony mistis yang membuat saya tiba tiba merinding. Empat wanita yang lebih muda tampak mengelilingi wanita yang sedang melantunkan tembang. Mereka semua adalah para penari Janggrung. Sementara seorang tetua adat sedang khusuk berdoa, asap dupa mengepul, bersatu dengan kabut dan butiran butiran air dari ombak yang terus berdebur menghantam batu-batu karang. Tepat di depan bukit Pengalapan, sekitar 50 meter berdiri kokoh bukit batu Nglambor yang dipisahkan oleh sebuah teluk kecil atau Laguna.
Adat (rebowagen.com)– Air laut sedang pasang, pemangku adat yang lain membawa ‘ubo rampe‘ sesaji dan seekor ayam hidup, setelah membaca doa sejenak kemudian melemparkan semuanya ke laut. Seorang yang lain memukul-mukulkan sebilah bambu dimana pada ujungnya diikat akar akar pohon. Saat matahari mulai beranjak meninggi pada hari Senin pasaran Wage itu dimulailah upacara adat Ngalangi, sebagai rangkaian menyambut hari Bersih Desa/Rasul Kalurahan Purwodadi.
“Dulu, saat air laut mulai ‘angok’ atau surut, warga kemudian beramai ramai membawa bilahan bilahan bambu yang diikat dengan tali dan berjejer-jejer pada satu sisi teluk, untuk menghalangi ikan agar tidak lari ke laut, jadi upacara Ngalangi itu berasal dari kata ‘ngalang-alangi’ atau menghalangi,”
tutur mbah Bambang, seorang tetua adat Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus, Gunungkidul, Yogyakarta.
Upacara adat Ngalangi adalah sebuah upacara adat Sedekah Laut yang rutin dilaksanakan oleh warga desa Purwodadi di pantai Nglambor. Menurut mbah Bambang, rangkaian upacara Bersih Desa Purwodadi dimulai pada hari Senin pasaran Wage, sampai Rabu Legi. Prosesi pertama yakni dengan melaksanakan upacara sedekah laut Ngalangi.

Saat air ‘angok‘ (surut), teluk kecil yang memisahkan pantai Nglambor dan bukit batu didepannya menjadi semacam Laguna dimana ikan-ikan akan terjebak di sana. Oleh warga, ikan-ikan ini secara beramai ramai ditangkap dan kemudian dikumpulkan dan dibawa ke balai desa untuk dimasak bersama, digunakan untuk menjamu para tamu dan rombongan Janggrung pada pementasan di malam Selasa Kliwon.
“Malam Rabu legi diadakan pementasan Kethoprak, sedang pada Rabu Legi pagi sampai siang diadakan arakan-arakan Gunungan oleh warga masing masing padukuhan, yang diarak dari lapangan ke balai desa, kemudian malamnya yaitu malam Kamis Pahing diadakan pementasan wayang kulit semalam suntuk,” terangnya lagi.
Upacara Ngalangi sendiri untuk saat ini prosesinya dilaksanakan tidak seperti dulu. Menurut mbah Bambang, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni diantaranya kondisi air laut surut yang tidak bisa lagi diprediksi, sehingga warga yang akan mencari ikan sering terkendala kondisi air. Seingat mbah Bambang, upacara Ngalangi dengan prosesi lengkap dilaksanakan terakhir pada sekitar akhir tahun 1970-an.
Dulu, lanjutnya ada pawang atau ‘sesepuh‘ khusus yang bisa mengadakan ritual permohonan doa agar air laut bisa surut, sehingga warga bisa turun ke laut untuk bersama sama menangkap ikan dengan cara di sepuh akar pohon Jenu. Akar pohon ini jika dipukul-pukulkan di batu, maka akan keluar getah yang bisa membuat ikan-ikan yang bersembunyi di lubang batu karang mabuk dan mudah ditangkap.
“Untuk saat ini, upacara Ngalangi masih tetap dilestarikan, namun untuk prosesi warga beramai-ramai menangkap ikan sudah tidak dilakukan lagi, sebenarnya tidak semata mata mau meninggalkan, hanya sekarang keadaan air laut tidak bisa diprediksi,”
imbuh mbah Bambang lagi.
Mbah Saido, salah satu tetua adat menambahkan bahwa ubo rampe yang dilarung ke laut terdiri dari berbagai hasil bumi dari pertanian masyarakat, juga akan dilepaskan seekor panggang hidup (ayam hidup yang dilepas ke laut). Larungan ini dilakukan saat ritual berdoa di batu Pengalapan selesai dan selanjutnya diadakan pentas Janggrung di depan pendopo pantai Nglambor.

“Jika ayam yang dilepas kembali ke pinggir maka bisa ditangkap lagi oleh warga, tapi sering juga ayam yang dilepas terbawa arus ke selatan dan hilang di laut,” terang mbah Saido.
Prosesi selanjutnya, rombongan Janggrung menggelar pementasan di depan pendopo pantai Nglambor. Kami kemudian melewati jembatan kayu yang menghubungkan batu Pengalapan dan pantai Nglambor.
Ratusan masyarakat tampak berduyun-duyun memenuhi sepanjang pantai Nglambor. Banyak diantaranya yang membawa makanan berupa nasi ‘golong‘, nasi ‘whuduk‘, ‘ingkung ayam‘ dan segala lauk pauk yang dibungkus daun pisang. Berbagai makanan ini kemudian dikumpulkan dan diadakan kenduri bersama di sekeliling ‘Watu Kaum‘.

Watu (batu) Kaum sendiri adalah sebongkah batu gunung raksasa yang berada di samping pendopo. Diseputaran batu ini, warga masyarakat yang mempunyai hajat niat atau nadzar akan duduk bersila mengelilingi Watu Kaum mengikuti prosesi kenduri yang akan segera dilaksanakan.
Tetua adat atau Kaum yang bertugas untuk ‘ngesrahke‘ atau membaca satu persatu ‘ubo rampe‘ kemudian secara khusuk memulai kenduri. Prosesi kemudian diakhiri dengan doa dan makan bersama bagi semua pengunjung dengan cara ‘kembulan‘.
Iringan gending gending Jawa terdengar mengalun lagi, seiring lima penari janggrung memulai pentas di depan pendopo.
“Gending pertama dan wajib adalah gending pitu(tujuh), semua penari Janggrung menari dan yang diperbolehkan ‘ngibing'(menari bersama) hanya Kepala Desa atau Lurah, orang lain belum boleh karena diyakini pada prosesi ‘gending pitu’ ini penari sedang didampingi oleh Ratu Pantai Selatan,” kata mbah Saido.
Setelah ‘gending pitu‘ selesai, acara ‘ngibing‘ dilanjutkan, kali ini warga boleh ikut menari bersama para penari Janggrung. Sebelumnya, pembawa acara satu persatu membacakan nadzar dari warga beserta sejumlah nominal uang yang disebut sebagai ‘tombok‘ yang digunakan untuk ‘nyawer‘ (uang yang diberikan sambil menari kepada para penari Janggrung’.

“Saniyem, padukuhan Ngandong, nek Rasul saget uwal saking tanggungan utang, ajeng tombok arto 100 ewu, ngepasi Ngalangi (Saniyem, padukuhan Ngandong, jika nanti Bersih Desa sudah lepas dari tanggungan hutang, akan memberi uang Janggrung 100 ribu, di upacara Ngalangi),” kata pembawa acara yang di dengar oleh seluruh pengunjung.
“Satino, padukuhan Kotekan, putune dawah ngantos operasi, nek enggal mantun, pas Ngalangi ajeng tombok 100 ewu (Satino, padukuhan Kotekan, cucunya jatuh sampai operasi, jika segera sembuh akan memberikan uang 100 ribu di upacara Ngalangi)“.
“Rantiyem, padukuhan Cepogo, biyen sakit pipine monyong, nek iso mari arep tombok 200 ewu, (Rantiyem, padukuhan Cepogo, dulu sakit pipinya benjol, kalau bisa sembuh akan memberikan uang 200 ribu)”.
Satu persatu, nadzar dari warga dibacakan, banyak diantaranya nadzar ini tidak semata sembuh dari sakit, tapi juga karena mendapat rejeki, seumpama sapi peliharaannya lahir, atau anaknya bisa diterima kerja. Bahkan saya mendengar satu nadzar yang tidak biasa, sehingga membuat saya terpaksa tersenyum.
“Retno, Padukuhan Ngande Ande, nak anake sing jenenge Pandu, iki putune pak Lurah, gelem bebuwang karo ndodok, ora karo ngadek meneh, arep tombok 100 ewu, (Retno, padukuhan Ngande Ande, jika anaknya yang bernama Pandu (cucunya pak Lurah), mau buang hajat dengan cara duduk, tidak lagi sambil berdiri akan memberi uang 100 ribu)“.
Semakin siang, acara semakin gayeng, banyak warga atau pengunjung yang ikut menari bersama para penari Janggrung. Saya kemudian diajak oleh mbah Bambang dan mbah Saido untuk ke bukit Watu Suweng, dimana di tempat itu dikenal sebagai ‘petilasan‘ Sunan Kalijaga. Sebuah tempat yang merupakan salah satu titik spritual penting bagi warga Kalurahan Purwadadi, yang sebelumnya bernama desa Winangun.